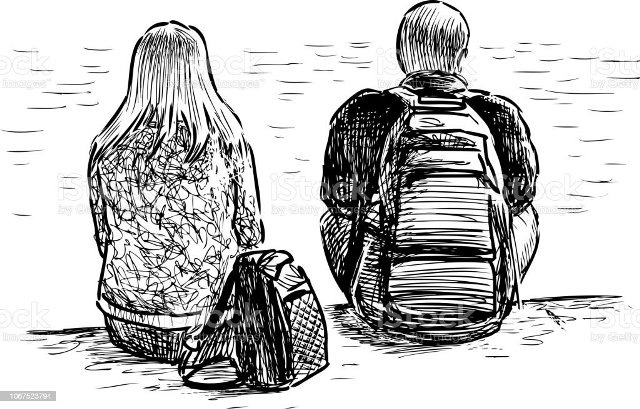
Oleh: Rara Zarary*
Malam itu, di bawah rembulan yang purnama, kami menghabiskan waktu. Seorang perempuan yang sedang tersenyum di depanku bercerita banyak hal, dan saat itu aku memilih banyak diam. Kali ini, aku tak punya banyak kata untuk menghiburnya, sebab apa yang kini ia hadapi bukan hanya soal perasaan tetapi kehidupan dan kematian.
“Aku hanya menunggu mati. Waktu yang akan menghabiskan aku. Bukankah hal ini lebih baik daripada aku bunuh diri?” matanya menatap langit, air mata yang ia tahan akhirnya membasahi pipi mungilnya. Ia masih sempat melempar senyum paling manis ke wajahku.
“kamu kenapa diam? Apa perkatanku salah?” ia membubarkan lamunanku. Aku tercekat, kata-kata rasanya terlalu hancur untuk menjawab pernyataannya soal kematian, lebih tepatnya kepasrahannya pada hidup.
“kalau kamu tak suka aku bicara seperti ini, tidak apa-apa. Aku sudah merelakan tak semua orang suka dengan pemikiran dan keberadaanku.” Air mataku jatuh tepat dia berhenti pada kalimatnya yang ini. Aku tidak tahu harus menjadi siapa di depannya malam itu. untuk sekadar menjadi pendengar, aku tak bisa memberikan solusi, untuk menjadi seorang sahabat aku tak punya kekuatan menampung deritanya yang terlampau berantakan.
“kamu masih punya semangat hidup, kan?” hanya kalimat itu yang lepas dari bibirku. Dia tersenyum sinis. Aku mencoba meneguk teh hangat di atas meja itu.
“tidak.” Ia menggeleng cepat, berkali-kali.
“tak ada alasan apapun untuk kamu bisa menikmati hidup?” aku berharap dia akan menyebut beberpa nama, mungkin keluarga, dirinya, atau orang yang paling berharga dalam hidupnya.
“tak ada siapapun yang bisa membuat aku semangat untuk bertahan. Bahkan orang tuaku, rasanya seperti penyakit dalam hidupku.” Rasanya ia telah menyerah. tidak seperti perempuan yang kutemui setahun lalu, di sebuah lembaga pendidikan yang datang atas nama menicntai ilmu pengetahuan, yang datang atas nama sebuah kerelaan dan perjuangan sebagai salah satu anak perempuan dari desa yang akan mempertahankan kesempatan terhadap pemberdayaan perempuan di sebuah desa tempat ia dilahirkan.
***
Semua yang terjadi padanya berawal dari hubungan yang penuh kepura-puraan. Ia mengaku telah terlibat dalam sebuah hubungan yang begitu toxic. Hubungan yang akhirnya membuat ia memilih menyingkirkan diri atas kalimat-kalimat begitu menyakitkan dari teman-teman seperjuangannya. Orang-orang yang selama ini ia anggap keluarga nyatanya menyulut bara di belakangnya. Bahkan saat ia sakit keras, mereka lah orang pertama yang menganggap bahwa penyakitnya hanyalah sandiwara belaka.
“adakah orang yang belum bisa kamu maafkan? Atau belum memaafkan kamu?” aku bertanya sekenanya. Kali ini matanya menatapku, “mereka.” Tatapan itu dibuang ke jalan raya, tempat kami duduk sambil minum teh hangat, di sebuah angkringan pinggir jalan raya, sebuah jalan tempat berlalu lalangnya bus provinsi membawa orang-orang memperjuangkan atau menyerahkan kehidupannya.
“perkataan mereka di belakangku terlalu menyakitkan.” Lagi-lagi air mata itu menetes. Aku melihat kekecewaan di matanya. Bibirnya bergetar, tangannya erat menggenggam ujung jilbab. Mungkin ia mengingat sesuatu yang sangat menyakitkan.
“gapapa ya, pelan-pelan maafkan dan kamu minta maaf.” Aku coba mengatakan itu.
“aku sudah cukup mengalah, kak. Pembullyan yang dilakukan padaku tak bisa kita biarkan hanya dengan memaafkan, mereka harus paham bahwa itu harus dihentikan. Itu membunuh mental, membunuh kehidupan seseorang. Aku tak mau ada orang lain yang mengalami hal seperti aku.” Matanya tajam, dia tampak marah, emosinya aku rasakan dengan cara ia beranjak dari duduknya.
“kamu mau ke mana?” aku dengan cepat membayar dua gelas teh pada penjual kaki lima itu sambil berusaha mengejar langkah kakinya.
“Aulia capek kak. Sudah begitu lama aku lemah di hadapan kehidupan dengan cara memaafkan semua orang. nyatanya mereka semakin menginjak-injak harga diriku. Aku sudah bosan membiarkan mereka berbicara tentang aku dan mereka itu fitnah. Dan kakak meminta aku memafkan lagi?” tubuh kurusnya diam tegak di hadapanku. Kali ini aku diam. Aku tidak bisa mengatakan apapun.
“sekarang, biarkan aku memilih apa yang bagiku bisa menyelamatkan diriku. Paling tidak ini tak akan menambah penyakit di tubuhku.” Dia melanjutkan langkahnya ke arah kos, di belakang sekolah madrasah tempat ia mengajar tiap sore.
“sebentar.” Langkahnya berhenti, memahami permintaanku.
“aku minta maaf, tak benar-benar bisa melindungimu.” Aku menyesali kelemahanku di hadapannya. Aku menyadari, aku dan Aulia tak ada hubungan apapun, tetapi sejak awal ia di kota ini, keluarganya yang baginya tak begitu peduli padanya, menitipkan ia padaku.
“kak Elang ga salah. Aku hanya butuh latihan lebih kuat dan sabar melalui ujian hidup ini.” Dia tersenyum lagi. Lagi-lagi dia tersenyum di antara lukanya.
“kamu benar, Aulia. Kita tak boleh membiarkan seseorang melakukan kesalahan secara terus menerus, itu akan dianggap kebenaran. Kita juga tak bisa mentoleransi ketidakadilan memperlakukan manusia.” Aku memeluknya. Tangisnya meledak di bahuku. Benar, mungkin ia memang butuh teman mendengarkan, bukan penghakiman.
“Terima kasih, kak. Sudah mempercayai pilihanku.” Kami saling menatap. Setelah malam itu, ia lebih terbuka tentang apa yang telah ia lakukan selama ini untuk membuat dirinya bertahan hidup di antara penyakit, pelecehan, dan segala yang menimpanya, yang membuatnya menjadi pribadi yang bodoamat saat ini.
“Maafkan aku yang mungkin terkesan hanya menjustifikasi, aku tak benar-benar paham apa yang kamu butuhkan dalam hidupmu.” aku benar-benar merasa menjadi gagal memahami orang lain. Memahami orang yang paling dekat denganku.
“cukup kak. Kakak telah menjadi orang paling berharga dalam hidupku. Aku hanya butuh sembuh dari pola pikirku yang sudah tak sehat karena terlanjur masuk ke circle yang begitu toxic itu.” senyumnya aku balas dengan senyuman yang sama. Malam itu, kubiarkan ia sendirian di kosan barunya. Baru kemarin malam ia memilih pindah kos, setelah menyadari butuh mengasingkan diri dari orang dan banyak hal yang baginya adalah cukup dijadikan kenangan saja.
***
Aulia benar. Ada saatnya kita berhenti terlalu mengedepankan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan diri sendiri, dengan cara mengabaikan diri, tak enak untuk bilang tidak, dan cukup sekadarnya saja untuk peduli sesama manusia, tak lebih dari itu yang akhirnya bisa menyakitkan dan begitu menyebalkan. Aulia juga benar, perbuatan yang membunuh mental tak boleh dibiarkan dengan cara memaafkan.
“Sudah lama menunggu?” Aulia hari ini tampak lebih ceria, wajahnya penuh senyum. Aku sengaja lebih awal tiba di depan kosnya. Hari ini ada jadwal ia menemui psikiater. Ini yang ternyata ia lakukan selama berbulan-bulan tanpa aku dan siapapun tahu. Ia melakukannya sebab tak merasa percaya lagi pada janji manusia, pada komitmen dalam sebuah relasi. Ia hanya ingin menenangkan dirinya, menyelamatkan dirinya dari pembunuhan mental oleh manusia lainnya.
“kalu pun nanti aku mati, itu bukan karena aku putus asa, tapi karena memang sudah waktunya.” Kalimatnya seperti mampu menanggapi apa yang sedang ada di pikiranku. Aku melempar senyum padanya.
“tenang ya. Mulai sekarang jangan merasa sendirian. Jangan takut pada kematian.” Ia mengangguk dan tersenyum. Meski aku tahu mungkin kalimat-kalimat ini tak akan mengubah jawabannya, “aku tinggal menunggu waktu.” Walau kalimat ini mungkin tak akan menyembuhkan lukanya. Sore itu kami menuju sebuah tempat di mana Aulia biasa menenangkan diri.










