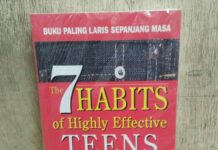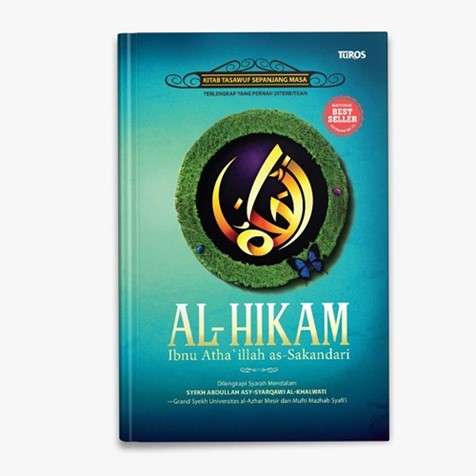
Allah memerintahkan hamba-Nya untuk melakukan ketaatan dan melarang untuk melakukan maksiat tidak lain karena kemaslahatan hamba itu sendiri. Karena Allah tidak membutuhkan itu semua, tapi hambalah yang butuh terhadap Allah dan karunia-Nya. Contoh kecilnya perintah shalat. Allah memerintahkan seluruh hambanya yang beriman untuk mendirikan shalat karena shalat memiliki beberapa manfaat, di antaranya menjadi pembersih hati dari pengaruh dan kotoran dosa, juga shalat merupakan tempat bermunajat seorang hamba kepada Tuhannya.
Dengan shalatlah, seorang hamba akan menampakkan sifat-sifat ubudiyyah-nya di hadapan Sang Pencipta. Dengan begitu seorang hamba akan sadar bahwa dirinya lemah dan membutuhkan kepada Dzat yang maha segalanya. Hal ini sesuai dengan kalam hikmah Syekh Ibnu Atha’illah yang berbunyi: “Ketaatanmu tidak bermanfaat untuk Allah dan maksiatmu tidak mendatangkan bahaya kepada-Nya. Allah memerintahkan ini dan melarang itu tidak lain hanyalah untuk kepentinganmu.”
Tugas manusia adalah beramal, baik amal yang bersifat duniawi ataupun ukhrawi. Namun, semua amal bukanlah hanya bagaimana kita mengerjakannya. Tapi setiap amal yang dilakukan manusia harus ada ruhnya yaitu keikhlasan, seperti yang dikatakan Ibnu Atha’illah “Amal itu bagaikan jasad, sedangkan keikhlasan adalah ruhnya (hlm. 19).” Bisa dibayangkan bagaimana jika jasad tidak ada ruhnya. Tentunya telah mati. Maka ia hanyalah bangkai yang tidak bisa mendatangkan manfaat. Begitupun amal tanpa keikhlasan juga tidak akan berarti apa-apa.
Dari sini, keikhlasan menjadi hal yang penting dalam beramal sehingga disamakan dengan ruh terhadap jasad. Keikhlasan setiap orang pun berbeda-beda. Keikhlasan paling rendah (keikhlasan orang awam seperti kita) adalah bersihnya amal dari sifat riya’ yang nyata maupun yang samar dan dari niat yang didasari hawa nafsu (hlm. 19). Setiap amal yang dilakukan manusia semuanya bergantung pada penilaian Allah, bukan penilaian makhluk-Nya. Tugas seorang hamba hanyalah menjaga keikhlasan tersebut dalam setiap amal dengan selalu memohon pertolongan, hidayah-Nya, dan meluruskan niat.
Selanjutnya, dalam mengarungi bahtera kehidupan ini, manusia tidak akan terlepas dari dosa. Namun hal yang terpenting adalah menyesali dosa tersebut. Sebaliknya jika hati kita tidak merasa sedih dan menganggap kalau dosa yang diperbuat adalah biasa-biasa saja berarti hati kita telah mati, sebagaimana yang diungkapkan Ibnu Atha’illah “Di antara tanda matinya hati adalah tidak adanya perasaan sedih atas ketaatan yang kau lewatkan dan tidak adanya perasaan menyesal atas kesalahan yang kau lakukan.” Mengenai tentang dosa, Ibnu Atha’illah berkata: “Tidak ada dosa kecil jika kau dihadapkan pada keadilan Allah dan tidak ada dosa besar jika kau dihadapkan pada karunia-Nya.”
Maksud kalam ini menurut Syekh Abdulllah asy-Syarqawi adalah jika sifat adil Allah muncul di hadapan orang yang dibenci-Nya, kebaikan-kebaikan orang itu akan diabaikan dan dosa-dosa kecilnya akan dipandang besar. Dan jika karunia Allah berupa sifat kasih sayang-Nya diberikan kepada orang-orang yang dicintai-Nya, maka semua kesalahan dan keburukannya akan diabaikan, begitupun dosa besarnya akan mengecil di hadapan karunia Allah (hlm. 94-95).
Selain soal ikhlas dan dosa, banyak hal yang dibahas oleh Ibnu Atha’illah dalam kitab Al-Hikamnya. Petikan-petikan hikmahnya sarat akan makna yang mendalam yang beliau peroleh dari hasil perenungan mendalam pada Al-Quran dan as-Sunnah. Al-Hikam sendiri merupakan salah satu karya sastra klasik yang sudah populer di Indonesia, terutama di pesantren-pesantren. Kitab ini sudah diajarkan kepada santri yang taraf keilmuannya sudah tinggi. Sebelum mengaji kitab ini, biasanya para santri akan diberi pengajian kitab Sullamut Taufiq dan Bidayatul Hidayah sebagai landasan awal agar lebih mudah memahami kitab Al-Hikam ini, karena tidak sembarang orang bisa mengaksesnya. Inilah yang membuat kitab ini menjadi unik ditambah kitab ini hebat bagi yang mengamalkan isinya, bukan hanya sekedar membacanya.
Kitab Al-Hikam ini merupakan salah satu karya sastra yang monumental di dalam tasawwuf. Al-Hikam dikarang oleh seorang sufi tarekat Syadziliyah yang lahir di kota Iskandariah (Alexandria), Mesir, yaitu Ibnu Atha’illah as-Sakandari. Sejak masih belia, beliau telah menguasai beberapa disiplin ilmu, seperti ilmu nahwu, tafsir, ushul fiqih, fikih dan hadis. Ini membuktikan bahwa Ibnu Atha’illah merupakan ulama yang produktif dalam berkarya. Banyak sekali karya-karya beliau yang bisa kita jumpai sampai sekarang. Namun yang lebih populer dan legendaris adalah Al-Hikam ini.
Secara garis besar terdapat dua tema pokok dalam Al-Hikam, yaitu sikap makhluk kepada Sang Khaliq, dan sikap makhluk terhadap perbuatan Sang Khaliq. Mengenai sikap makhluk terhadap perbuatan Sang Khalik, Ibnu Atha’illah mengajak kita untuk berpikir dan memiliki prasangka baik terhadap ketetapan Allah. Hal ini beliau kemukakan di salah satu kalam hikmahnya, “Yang membuatmu kecewa ketika tidak diberi adalah karena engkau tidak memahami hikmah Allah di dalamnya.” (hlm.153).
Kalau kita merenungkan kalam hikmah ini dengan akal sehat tentunya kita tidak akan memaksakan keinginan kita kepada Allah. Karena semua yang kita inginkan kepada Allah ataupun yang kita minta kepada-Nya tidaklah harus terwujud semua. Mungkin Allah tidak memberi, karena itulah yang terbaik bagi kita. Atau bisa saja Allah memberikan semua yang kita inginkan, tak lain sebagai karunia yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang wajib disyukuri. Semua ketentuan Allah, baik yang sesuai dengan keinginan dan harapan kita ataupun sebaliknya, pasti ada hikmah di dalamnya.
Buku Al-Hikam ini berisi 266 bait hikmah yang terkumpul dalam dua buku yang dijadikan satu sesuai kitab aslinya. 157 hikmah pada buku pertama dan 109 hikmah pada buku kedua. Disusul 42 bagian doa-doa Ibnu Atha’illah serta 20 surat-surat Ibnu Atha’illah kepada sahabat-sahabatnya. Buku setebal 532 halaman ini merupakan terjemahan yang bisa dibilang paling lengkap, mulai dari teks Arabnya kitab Al-Hikam yang diterjemahkan ke dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan juga buku ini diberi penjelasan secara mendalam oleh seorang ulama al-Azhar, Mesir yang tidak diragukan lagi keilmuannya, yaitu Syekh Abdullah asy-Syarqawi al-Khalwati.
Al-Hikam ini dikarang oleh seorang sufi tarekat Syadziliyah yang menganut madzhab Maliki, namun ditasyrih (diuraikan atau diberi penjelasan) oleh seorang sufi tarekat Khalwatiyah penganut madzhab Syafi’i. Ini adalah salah satu bukti yang menunjukkan bahwa buku ini bisa diterima oleh semua kalangan dari masa ke masa baik lintas tarekat maupun lintas madzhab. Bahkan sekarang kita bisa menjumpai berbagai kitab yang mensyarahi kitab Al-Hikam ini.
Dengan ulasan yang sangat jelas dari Imam Abdullah asy-Syarqawi, buku ini akan lebih mudah dipahami. Dengan begitu, upaya untuk menyelami hikmah menjadi terbantu dan bisa dilakukan semua kalangan, masyarakat awam pun bisa. Dengan adanya kitab-kitab yang mensyarahi Al-Hikam, bukan berarti Al-Hikam kehilangan daya tarik dan kehebatannya. Justru dengan munculnya kitab-kitab yang mengulasnya, keberagaman pemahaman atas Al-Hikam Ibnu Atha’illah lebih hidup dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman.
Dengan membaca buku ini, pembaca akan tahu bagaimana cara menjalani kehidupan secara Islami, baik secara lahir maupun batin. Dan juga buku ini menjelaskan berbagai persoalan yang berkaitan dengan tauhid, etika, dan perilaku sehari-hari terutama bagaimana cara seorang hamba berhubungan dengan Allah (Hablumminallah). Oleh karena itu, buku ini sangat tepat menjadi panduan dan sangat cocok bagi orang-orang yang ingin menggapai puncak spiritual. Wallahu A’lam.
| Judul | Al-Hikam |
| Penulis | Syekh Abdurrahman Bin AhmadIbnu Atha’illah as-SakandariAl-Qadhi |
| Penerbit | TUROS PUSTAKA |
| ISBN | 978-623-7327-23-3 |
| Halaman | 532 halaman |
| Cetakan | 4, Februari 2021 |
| Peresensi | M.Rizal (Santri Pondok Pesantren Annuqayah) |