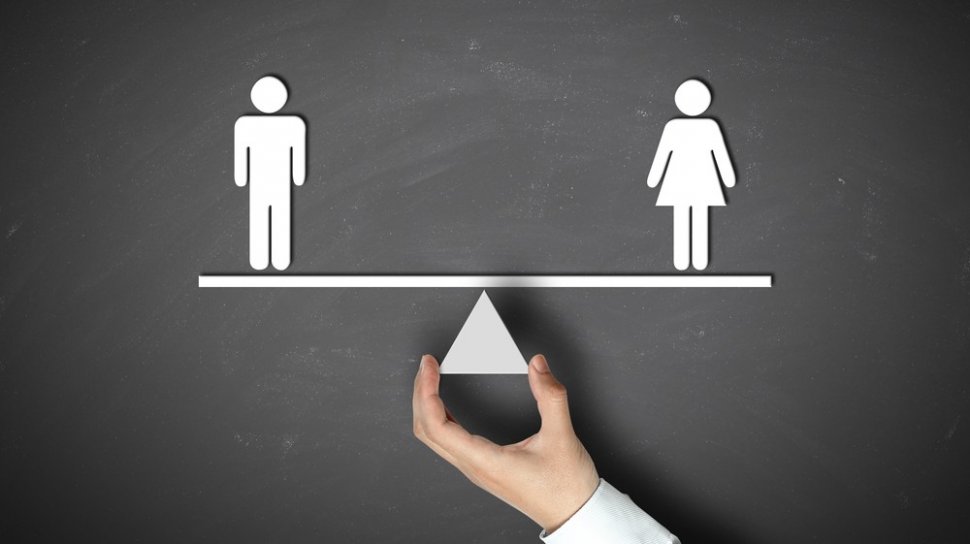
Oleh: Quratul Adawiyah*
يٰۤاَ يُّهَا النَّا سُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَا رَفُوْا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَ تْقٰٮكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ
“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”
(QS. Al-Hujurat 49: Ayat 13)
Ayat di atas memberikan gambaran kepada kita tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan baik dalam ranah ibadah (dimensi spiritual) maupun dalam persoalan sosial (urusan karier profesional). Ayat ini juga berperan dalam mengikis tuntas sebuah pandangan yang menyatakan bahwa dalam keduanya, yakni antara laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan yang memarginalkan salah satu di antara keduanya. Kesetaraan yang dimaksud meliputi berbagai hal, misalnya dalam bidang ibadah. Perbedaan kemudian lahir karena disebabkan kualitas nilai pengabdian dan ketakwaan mereka kepada Allah SWT.
Ayat ini juga mempertegas misi agama Islam yang di antaranya adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis dan ikatan-ikatan primordial lainnya. Namun demikian sekalipun secara teoritis al-Quran mengandung prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun ternyata dalam tatanan implementasi seringkali prinsip-prinsip tersebut terabaikan. [1]
Dewasa ini agama sering dituduh sebagai sumber terjadinya ketidakadilan di tengah masyarakat, termasuk ketidakadilan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan yang sering disebut dengan ketidakadilan gender. Hal ini dapat dicontohkan dengan sebuah statement yang masyhur bahwa laki-laki itu kuat, berani, cerdas, menguasai. Demikian sebaliknya yang juga mengatakan perempuan itu lemah, penakut, kurang cerdas (bodoh), dikuasai dan lain-lain.
Isu gender menguat ketika disadari bahwa perbedaan gender antara manusia laki-laki dan perempuan telah melahirkan ketidak adilan dalam berbagai bentuk. Seperti marginalisasi atau pemiskinan ekonomi, subordinate atau anggapan tidak penting dalam urusan politik, stereotype atau pencitraan negatif bagi perempuan. Stereotype yang dimaksud adalah bahwa kaum perempuan hanya mampu dan pantas bergelut dalam 3R (dapur, sumur, kasur) saja. Kekerasan dan doubleburden (beban ganda) terhadap perempuan masih pula sering menghiasi topik berita dan pembicaraan lintas golongan. Sementara itu peran perempuan semakin dibutuhkan dalam berbagai kehidupan.
Tidak diragukan lagi bahwa sebagai makhluk yang dimuliakan Tuhan dengan dijadikannya khalifah di muka bumi, maka manusia secara normal sudah memiliki fitrah, dimensi dan potensi individual. Salah satunya ialah manusia sebagai makhluk sosial, dan makhluk berketuhanan. Sebagai makhluk sosial setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sudah melekat pada dirinya ketika ia telah menjadi bagian dari komunitas masyarakat.
Meskipun hak dan kewajiban tersebut tidak tertulis secara keseluruhan dalam Undang-undang suatu negara, namun juga bukan berarti dengan hal tersebut masalah tadi malah diabaikan begitu saja. Sebab ia sudah menjadi ketentuan umum dan melekat pada masing-masing individu. Karenanya, bila ada hak dan kewajiban seseorang sebagai warga negara diabaikan atau bahkan dihancurkan, maka dengannya timbullah pelanggaran asasi yang dapat menggoyahkan kehidupan suatu bangsa.
Sebagaimana Nasaruddin Umar mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang dapat digunakan sebagai standar dalam menganalisa prinsip-prinsip kesetaraan gender dengan mengaca pada ayat-ayat al-Qur’an. Hal tersebut antara lain sebagai berikut:
- Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba
Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Zariyat: 56 artinya sebagai berikut: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.” Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan siapa yang banyak amal ibadahnya, maka itulah mendapat pahala yang besar tanpa harus melihat dan mempertimbangkan jenis kelaminnya terlebih dahulu. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam al-Quran biasa diistilahkan dengan orang-orang bertaqwa (muttaqûn), dan untuk mencapai derajat muttaqûn ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu.
- Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi
Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah, di samping untuk menjadi hamba (âbid) yang tunduk dan patuh serta mengabdi kepada Allah Swt., juga untuk menjadi khalifah di bumi (khalifah fîal-ard). Kapasitas manusia sebagai khalifah di bumi ditegaskan di dalam QS. Al-An’am: 165 artinya sebagai berikut: “Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Kata “khalifah” dalam ayat tersebut tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi, sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan.[2]
Oleh karena itu dengan berkembangnya zaman, tentu kesetaraan gender sudah mencapai kemajuan dan perkembangan. Khususnya di Indonesia, kemajuan dalam kesetaraan gender jauh lebih besar. Sejarah mencatat bahwa Menteri Agama A. Wahid Hasyim memberi hak kepada perempuan untuk menjadi hakim agama sejak tahun 1951. Oleh karena itu, bab mengenai kepemimpinan sosial politik adalah mungkin yang paling “aktual”. Pada saat diskusi soal peran publik perempuan dalam Muktamar NU di Lombok pada tahun 1997, Kiai Nur Muhammad Iskandar secara tegas menolak seorang perempuan menjadi presiden. Sedangkan Masdar Farid Mas’udi tidak menemukan alasan agama untuk menolak hak perempuan untuk menjadi presiden. Akan tetapi, karena ada perbedaan pendapat, deklarasi NU mengenai peran publik perempuan tidak membuat pernyataan yang jelas dan tegas mengenai hal itu. Akan tetapi, ketua NU yakni Gus Dur, dalam pernyataannya kepada pers waktu itu, mendukung ide bahwa permpuan dapat menjadi presiden seperti halnya Megawati yang terbukti bisa menjadi presiden. [3]
Selanjutnya, fakta-fakta dalam peradaban agama Islam awal ini menunjukkan dengan pasti betapa banyak perempuan yang menjadi ulama, cendekia, dan intelektual dengan beragam keahlian dan kapasitas intelektual yang relatif sama. Bahkan sebagian mereka mengungguli ulama laki-laki. Fakta ini juga menggugat anggapan banyak orang bahwa akal, intelektualitas, kecerdasan, dan moralitas perempuan lebih rendah daripada akal, intelektualitas, dan moralitas laki-laki.
Nama-nama perempuan ulama, intelektualitas, cendikia, perjalanan hidup, dan karya-karya mereka terekam dengan baik dalam banyak buku serta terukir indah dalam kaligrafi. Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ahli hadits terkemuka, dalam buku Al-Ishabah Fi Tamyiz ash-Shahabah, menyebut lima ratus perempuan ahli hadits. Ia menulis jejak langkah dan sejarah hidup mereka. Nama-nama mereka juga ditulis sejumlah ulama, seperti Imam Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyq, muhaddist faqih besar dalam Tahzib al-Asma wa ar-Rijal.[4]
Lebih dari itu, kita semua melihat bahwa kehidupan masyarakat manusia sedang menuju sekaligus menghadapi tuntutan-tuntutan demokratisasi, keadilan, dan penegakan hak-hak asasi manusia. Semua tema ini meniscayakan kesetaraan manusia. Tidak berhenti di situ, semua hal tersebut merupakan nilai-nilai yang tetap diinginkan oleh kebudayaan manusia.
Oleh sebab itu, nilai-nilai yang disebut tadi seharusnya menjadi landasan bagi semua kepentingan wacana kebudayaan, ekonomi, hukum, dan politik. Dengan begitu, diharapkan nantinya dengan wacana-wacana tadi dapat melahirkan sebuah gerakan positif yang saling menguntungkan lintas gender tanpa adanya penindasan. Selanjutnya tidak akan ada lagi pernyataan-pernyataan yang memberi peluang bagi terciptanya sistem kehidupan yang diskriminatif, subordinatif, memarginalkan manusia, siapapun orangnya dan apa pun jenis kelaminnya, laki-laki maupun perempuan. Sebab yang paling utama di antara manusia ialah yang paling bertakwa kepada Allah Swt.[5]
[1] Sarifa Suhra, 2013, Kesetaraan Gender dalam Perspektif al-quran dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam, Diakses pada tanggal 21Juni dari https://media.neliti.com/media/publications/195698-none- .
[2] Ibnu Khaldun, Filsafat Islam Tentang Sejarah, terj. M. Hashem dari judul asli SocietyandHistory, (Bandung: Mizan, 1986), h. 15.
[3] K.H. Muhammad, Husein, Fiqih Perempuan, (Yogyakarta : IRCiSOD, 2019), h. 21.
[4] K.H. Muhammad, Perempuan Ulama di atas Panggung Sejarah, (Yogyakarta : IRCiSOD, 2020), h. 35-36.
[5] Ibid
*Mahasantri Ma’had Aly Hasyim Asy’ari



















