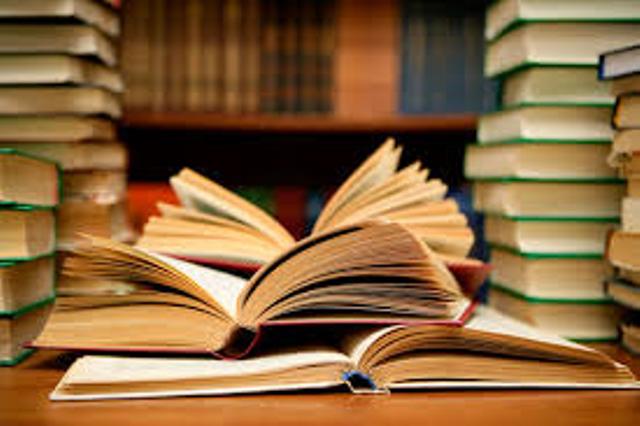
Oleh: Wulida Ainur Rofik*
Ceritanya para mahasiswa suatu kampus sedang membahas metode istidlal Ibnu Rusyd dalam perkuliahan bersama dosen. Melalui analisis redaksi dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid karya tokoh yang dibahas, satu kelompok mempresentasikan sebuah keterangan yang cukup memuaskan. Dengan menunjukkan tabel olahannya, salah satu mahasiswa dalam kelompok tersebut mulai berbicara.
“Para imam madzhab dalam fikih Islam berbeda pendapat tentang hukuman bagi orang yang meninggalkan shalat. Imam Ahmad, yang paling muda di antara empat imam lainnya, mengharuskan orang tersebut dibunuh. Imam Malik, Hanafi, dan Syafi’i mengahruskan hukum pidana. Dua pendapat tersebut mempunyai dalil masing-masing,”
Lalu, bagaimana pendapat Ibnu Rusyd sebagai tokoh yang lebih muda dari para Imam Madzhab? Biasanya, dalam perbedaan pendapat seperti itu, Ibnu Rusyd akan melakukan dua hal. Pertama, menjelaskan mengapa para imam madzhab berbeda pendapat berserta menyebutkan dalil mereka secara rinci tanpa memilih salah satu pendapat. Kedua, setelah menjelaskan poin pertama, Ibnu Rusyd akan menegaskan mana yang dipilih oleh Ibnu Rusyd disertai alasan pemilihan.
Ternyata, dalam pembahasan hukuman bagi orang meninggalkan shalat, Ibnu Rusyd tidak melakukan tahap kedua. Ibnu Rusyd tidak memilih salah satu pendapat dari keempat imam madzhab, melainkan menawarkan sebuah pendapat baru versinya sendiri, yaitu tidak ada hukuman bagi orang yang meninggalkan shalat. Ibnu Rusyd lebih condong kepada penyerahkan kehendak kepada sang manusia untuk melakukan shalat atau meninggalkannya. Dalam artian, penegak hukum di daerah tempat tinggal sang manusia tersebut tidak usah mengawasi urusan shalat masyarakat satu persatu, pun menetapkan norma hukum (pidana) tertentu.
Hal yang menarik dari cerita di atas adalah keberanian Ibnu Rusyd dalam menetapkan hukum baru. Ibnu Rusyd yang lebih muda dari keempat imam madzhab tidak melulu taqlid kepada produk hukum para imam. Tentunya hal itu disertai pertimbangan logis dan tinjauan maslahah.
Dalam masalah shalat di atas, pertimbangan logis yang dapat kita tangkap adalah perbedaan kondisi. Generasi imam madzhab relatif dekat dengan generasi awal Islam. Kepedulian mereka terhadap agama tentulah besar, juga ditunjang dengan karakter zahid dan saleh. Berangkat dari latar belakang seperti itu, para imam madzhab akhirnya tidak ragu untum memutuskan hukuman yang berat kepada orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja.
Sementara itu, Ibnu Rusyd hidup di zaman dan daerah yang jauh dari pusat peradaban Islam, yaitu daerah Andalusia. Kondisi umat Islam pada saat itu jelas berbeda dengan kondisi umat pada periode imam madzhab. Maka Islam yang garang akan sulit diterima dan akan berujung pada alienasi penerapan hukumnya. Kiranya di sinilah nilai mashlahah yang dijunjung Ibnu Rusyd.
Dari sini terlihat jelas bukti fleksibilitas ilmu fikih. Fikih sebagai ilmu pengetahuan, bukan produk yang disakralkan. Bayangkan saja jika hari ini, di Indonesia, hukuman mati diterapkan bagi orang yang meninggalkan sholat secara sengaja. Betapa garang wajah Islam. Kecaman bahwa Islam adalah agama brutal, keras, kejam, dan tidak berperikemanusiaan akan muncul. Orang-orang pada akhirnya akan lari dari Islam. Di sinilah perlunya memahami fikih sebagai ilmu pengetahuan yang fleksibel.
Fleksibilitas hukum Islam yang dimaksud tentunya bukan peralihan hukum secara sembarangan. Terdapat metode tersendiri yang harus dilalui. Ushul fiqh, itulah metodenya. Tanpa metode, fikih tak layak disebut ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan harus mempunyai pakem yang jelas. Dalam ushul fiqh hal itu ditemukan.
Mengenai pendapat Ibnu Rusyd di atas, pendapat bahwa tidak ada hukuman bagi orang yang meninggalkan shalat secara sengaja didasarkan pada tidak adanya nash yang spesifik menetapkan hukuman sebagaimana pendapat para imam madzhab. Para imam madzhab menentukan hukum dengan dasar nash umum, bukan nash khusus. Oleh karenanya Ibnu Rusyd berani menetapkan hukum baru dengan menolak penggunaan nash umum untuk membuat hukum spesifik.
Fleksibel namun ketat. Kiranya itulah kalimat yang bisa menggambarkan fikih sebagai ilmu pengetahuan. Satu persoalan dapat melahirkan berbagai pendapat. Perbedaan-perbedaan sudah barang tentu menjadi niscaya jika fikih dipandang seperti itu. Maka jangan kaget jika para imam madzhab sering berbeda dalam menetapkan suatu hukum. Begitu pula para penerus mereka, seperti Ibnu Rusyd di atas.
Adanya perbedaan hukum bukan menunjukan bahwa hukum Islam tidak konsisten. Sebaliknya, dalam ranah fikih, Islam memberikan toleransi yang tinggi atas penerapan hukum untuk dilaksanakan sesuai dengan keadaan masyarakat yang bersangkutan. Jika selama ini muncul suatu opini bahwa antara hukum Islam dan adat kebiasaan masyarakat selalu bertentangan, maka berdasarkan karakteristik dari hukum Islam yang fleksibel, seharusnya hal tersebut bisa diminimalisir.
Salah satu problem terbesar umat saat ini adalah anti dengan perbedaan. Perbedaan dianggap perpecahan. Semestinya kita belajar dari ulama-ulama klasik dalam menyikapi perbedaan. Mereka tidak pernah memaksakan pendapatnya karena bagi mereka, “Pendapat saya benar tapi bisa jadi mengandung kemungkinan salah, sementara pendapat anda itu saya anggap keliru, namun bisa jadi mengandung kebenaran yang belum saya pahami,”
Dalam Bidayatul Mujtahid, Ibnu Rusyd menulis banyak perbedaan pendapat di antara para mujtahid. Perbedaan pendapat tersebut hampir terjadi dalam setiap masalah. Ibnu Rusyd mengajari kira agar tidak kagetan ketika terjadi perbedaan pendapat. Jika kita terbiasa dengan keragaman pendapat, kita tidak akan heran, ngeyel, atau dengan mudahnya mnyalahkan orang lain. Persis dengan wajarnya kita melihat pilihan menu makanan yang berbeda di warung padang, warteg, atau restoran. Semua punya hak memilih. Selera boleh berbeda, pilihan boleh tak sama, namun kita tetap umat yang satu.
*Mahasantri Ma’had Aly Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang.










