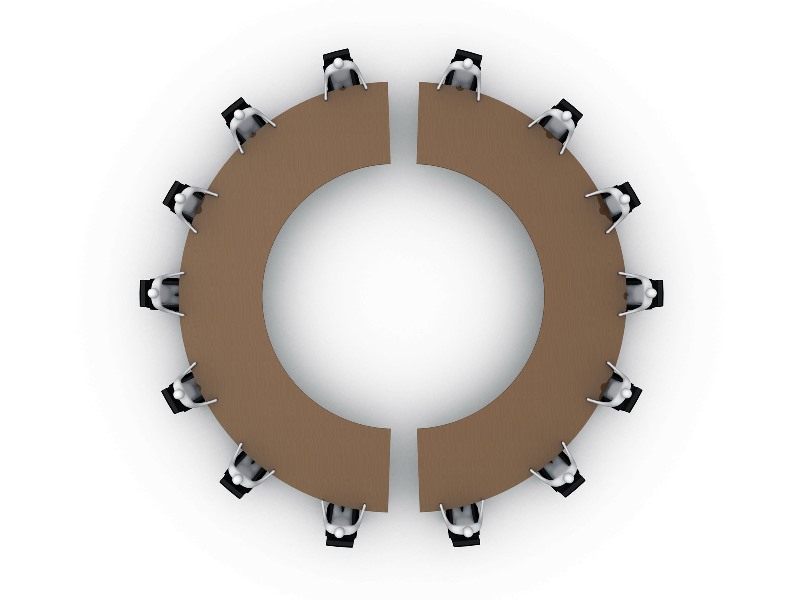
Oleh: Hilmi Abedillah*
Semenjak runtuhnya Kesultanan Islam Dinasti Abbasiyah di sekitar abad 13, dunia keilmuan Islam ikut-ikutan lesu. Taraf intelektual, yang dibuktikan dengan banyaknya ulama berpengaruh hingga karya yang mendunia, ikut menurun. Tak terkecuali di bidang fikih. Abad pertengahan menciptakan banyak mujtahid-mujtahid multak, mujatihd fatwa, maupun mujtahid madzhab, hingga dikerucutkan menjadi empat madzhab yang dijadikan pegangan umat Islam seluruh dunia. Ditambah lagi, kemunculan isu ditutupnya pintu ijtihad setelah abad ke-3 hijriah yang ternyata disebabkan tidak adanya ulama yang berkompeten melakukan ijtihad karena tidak memenuhi syarat.
Bahkan sejak Nabi Muhammad SAW tiada, ijtihad kolektif menjadi cerminan sebuah kesepakatan kaum untuk memecahkan masalah. Tidak aneh, karena Nabi SAW semasa hidupnya selalu mengedepankan musyawarah yang berpijak pada surat Ali Imran ayat 159, “… dan bermusyawarahlah kalian dalam suatu perkara …”, sehingga pemilihan khalifah sepeninggal Nabi SAW dilaksanakan dengan musyawarah antara kaum muhajirin dan anshar. Terpilihlah Abu Bakar ra merupakan hasil dari ijtihad kolektif masa sahabat.
Penerapan ijthad kolektif pada zaman sekarang bisa dillihat dalam beberapa bentuk lembaga kajian ilmu khususnya fikih, seperti Haiah Kibaril Ulama di Arab Saudi, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Nahdlatul Ulama di Indonesia.
Dalam skala internasional, ada lembaga ijtihad kolektif bernama al Majma’ al- Fiqhi al-Islami di bawah Rabithat al Alam al Islami yang bertempat di Mekah dan Majma’ al-Fiqhi al Islami ad Duwali di bawah Organization of Islamic Cooperation yang berpusat di Jeddah.
Ijtihad kolektif dilandasi kelangkaan ulama yang menguasai banyak disiplin ilmu. Kelangkaan ini bukan hanya disebabkan karena dekadensi kualitas manusia secara global, tetapi juga kondisi yang memaksa seseorang untuk menjadi spesialis. Zakariya al Anshari dalam kitab Ghayatul Wushul menyebutkan syarat ijtihad yakni baligh, berakal, mempunyai kecerdasan berpikir, tajam dalam memahami maksud kalam, mengetahui dalil ‘aqli, pandai bahasa Arab, menguasai ushul fikih, mengetahui ijmak ulama, nasikh-mansukh, asbabun nuzul, hadits mutawatir dan ahad, hadis shahih, dan keadaan rawi hadis. (Ghayatul Wushul, 147-148)
Selain Zakariya al Anshari, banyak ulama yang memiliki syarat-syarat tersendiri dalam ijtihad. Maklum, tidak ada ayat maupun hadis yang dengan gamblang menunjukkan syarat-syarat ijtihad, sehingga terjadi perbedaan standar antarulama. Tentunya untuk menjadi seorang mujtahid bukan perkara mudah. Oleh karena itu, tidak ditemukan ulama yang mencapai derajat mujtahid pada zaman milenial ini.
Satu-satunya cara untuk menghasilkan hukum yang kuat dengan pondasi ijtihadnya ialah dengan melakukan ijtihad kolektif (ijtihad jama’i) sebagai ganti dari ijtihad individu (ijtihad fardi). Dalam Syarh Waraqat, Jalaluddin al Mahalli menyebutkan bahwa ijtihad adalah mengupayakan segenap kemampuan dalam mencapai maksud berupa ilmu agar terwujud hasil baginya. (Syarh al-Waraqat, 23)
Wahbah Zuhaili memaparkan definisi ijtihad kolektif lebih rinci. Yakni, hukum yang disepakati oleh sejumlah ulama yang diakui kapasitasnya setelah melakukan kajian terhadap objek tertentu dan mendahulukan kajian atasnya serta dengan mengkaji pendapat-pendapat yang didapati dari ulama-ulama terdahulu. Kemudian mendatangkan dalil-dalil ulama tersebut serta mendiskusikannya, kemudian melakukan tarjih di antara pendapat-pendapat tersebut sehingga menghasilkan suatu pendapat berdasarkan dalil yang kuat beserta kepastian maslahahnya. Ijtihad kolektif berbeda dengan ijmak. Karena ijmak harus disepakati oleh seluruh ulama semasa, sedangkan ijtihad kolektif bisa diikuti oleh sebagian saja. (al-Ijtihad fi ‘Ashrina Hadza min Haitsun Nadhariyah wat Tathbiq, 1)
Ini semacam upaya produser dalam membuat sebuah film. Ia mengumpulkan banyak potensi mulai dari sutradara, kameramen, pengisi suara, penata musik, editor, aktris, aktor, perias, tata busana, penata artistik, dan lain-lain. Dari banyak keahlian itu terciptalah sebuah karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Usaha dalam menelurkan produk fikih juga demikian, membutuhkan banyak ahli di bidang masing-masing.
Misalnya dalam menentukan hukum suatu merek penyedap rasa masakan yang dikabarkan mengandung zat babi. Untuk mengetahui hukumnya, tidak cukup hanya mendatangkan ahli fikih dan ahli hadis saja (sebagaimana yang disyaratkan Zakariya al-Anshari di atas), tetapi juga ahli zat, ahli kesehatan, ahli penyedap rasa, atau ahli apapun kita menyebutnya. Dengan kehadiran ahli spesialis itu dalam satu forum, hukum yang tercipta menjadi tandas. Penuh dengan argumen dan penjabaran yang jelas. Problem senantiasa up-to-date menuntut proses produksi hukum agama tidak hanya dilakukan oleh ahli agama.
Ketidaksadaran kita dalam mendatangkan ahli di bidang hukum yang dibahas membuat konseptualisasi (tashawwur) masalah tidak berhasil. Sering kita menemukan di mana sebuah majlis bahtsul masail tidak berjalan lancar karena peserta, penanya, moderator, maupun yang hadir tidak memahami masalah secara mendalam. Mereka hanya paham di permukaan saja. Sehingga jawaban yang dihasilkan cenderung tafshil bahkan mauquf.
Ijtihad kolektif telah menyatukan banyak ragam keilmuan dari berbagai ahli. Kiranya ini menjadi wajah keilmuan Islam yang terus-menerus berkembang dalam lingkup musyawarah. Bukan sebagai semangat membenturkan pendapat yang bisa memercikkan api perpecahan. Ijtihad kolektif sudah dilakukan sejak dulu, namun di masa kini menjadi sangat perlu.
*) Redaktur Majalah Tebuireng



















