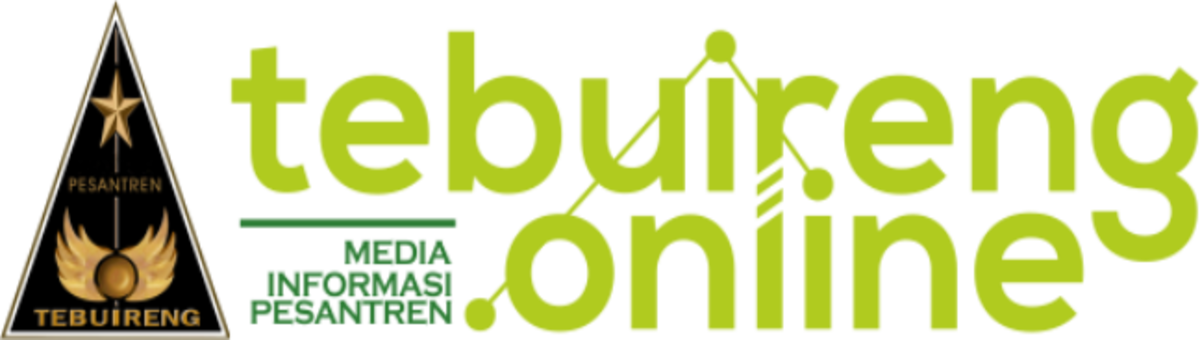Ilmu pengetahuan merupakan salah satu rahasia kekuasaan Tuhan. Dengan mengetahui makna dari ilmu pengetahuan dan dasar-dasarnya, kemudian mengembangkannya, akan memperkuat fungsi manusia sebagai khalifah fi al-ard (penguasa di bumi, penjaga di bumi dan pengganti “Tuhan” di bumi).
Secara bahasa, ilmu (Bahasa Indonesia) itu berasal dari bahasa Arab, terserap dari a’lama yang memiliki arti pengetahuan. Kata ilmu sering disejajarkan dengan science, serapan dari Bahasa Latin, scio dan scire, yang ketika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia diartikan dengan pengetahuan. Ada juga yang menyebut bahwa science berasal dari Bahasa Latin, sciere dan scientin, yang artinya pengetahuan dan aktivitas mengetahui.
M. Quraish Shihab berpendapat bahwa ilmu berasal dari bahasa Arab, ‘ilm yang berarti kejelasan. Karena itu, segala bentuk kata yang terambil dari akar kata ‘ilm seperti ‘alama (bendera), ‘ulmat (bibir sumbing), ‘alam (gunung- gunung), dan ‘alamat selalu mengandung objek pengetahuan. Melalui nalar ini, M. Quraish Shihab menyebut ilmu dengan pengetahuan yang jelas tentang sesuatu. Artinya, yang tidak jelas atau tidak membuat sesuatu menjadi jelas, maka hal itu tidak dapat disebut sebagai ilmu.
Apakah sama atau beda antara makna ilmu dengan makna pengetahuan? Mengapa dalam bahasa Inggris kata ilmu disemaknakan dengan science sedangkan pengetahuan disemaknakan dengan kata knowledge? Apakah dengan perbedaan penyebutan itu, secara otomatis antara keduanya berbeda?
Menurut Prof. Dr. Cecep Sumarna, ilmu dan pengetahuan itu berbeda. Pengetahuan (Indonesia) semakna dengan kata knowledge (B. Inggris). Kata ini sering diartikan sebagai sejumlah informasi yang diperoleh manusia meski tidak melalui proses pengamatan, pengalaman (empirik) dan penalaran (rasio). Sedangkan ilmu atau sains, cara perolehannya mengharuskan adanya proses pengamatan, pengalaman, dan penalaran.
Oleh karena itu, pengetahuan tentu berbeda dengan ilmu, terutama dalam pemakaiannya. Ilmu lebih menitikberatkan pada aspek teoretis dari sejumlah pengetahuan yang diperoleh dan dimiliki manusia. Sedangkan pengetahuan tidak mensyaratkan adanya teoretisasi dan pengujian. Kebenaran ilmu menuntut generalisasi karena diperoleh melalui sejumlah penelitian dan pembuktian, bukan hanya sekadar pembenaran atas penalaran rasio. Sedangkan pengetahuan belum dapat digunakan untuk sebuah proses generalisasi. Pengetahuan tidak menuntut adanya penelitian dan pengkajian lebih lanjut atasnya.
Harus juga diakui, bahwa setiap jenis pengetahuan pada prinsipnya selalu berguna untuk memberikan jawaban terhadap berbagai pertanyaan yang muncul dalam diri seseorang. Pengetahuan selalu memberi rasa puas dengan menangkap tanpa ragu terhadap sesuatu. Pengertian pengetahuan seperti itu telah membedakannya dengan ilmu yang selalu menghendaki penjelasan lebih lanjut dari hanya sekadar dituntut pengetahuan. Dalam makna ini, pengetahuan hanya mungkin menjadi semacam informasi yang menjadi landasan awal bagi lahirnya ilmu. Tanpa didahului oleh pengetahuan, ilmu tidak akan pernah ada dan mungkin tidak akan pernah lahir.
Al-Ghazali mengartikan pengetahuan sebagai hasil aktivitas mengetahui, yakni tersingkapnya suatu kenyataan ke dalam jiwa sehingga tidak ada keraguan terhadapnya. Menurut al-Ghazali, jiwa yang tidak ragu terhadap apa yang diketahui menjadi syarat mutlak diterimanya sebuah pengetahuan. Misalnya, jika ada seorang yang mengetahui, lalu karena pengetahuannya dia yakin bahwa ada sepuluh malaikat yang wajib diketahui. Pengetahuan dia tentang sepuluh malaikat yang wajib diketahui itu tetap dipertahankannya meskipun ada master atau kaum cerdik cendekiawan lain menyatakan bahwa bukan sepuluh jumlah malaikat yang wajib diketahuinya, Pengetahuan yang dibarengi dengan keyakinan seperti itu disebut al-Ghazali sebagai pengetahuan.
Ahmad Tafsir berpendapat bahwa pengetahuan berlangsung dalam dua bentuk dasar dan fungsi yang berbeda. Pertama, pengetahuan berfungsi untuk dinikmati dan memberikan kepuasan kepada hati manusia seperti terdapat dalam kajian mistik dan filsafat. Kedua, pengetahuan yang patut digunakan atau diterapkan dalam menjawab kebutuhan praktis kebutuhan manusia seperti yang terdapat dalam sains. Masing-masing jenis dan fungsi pengetahuan itu kemudian memiliki objek, paradigma, metode, dan ukurannya sendiri-sendiri, yang satu sama lain sangat mungkin berbeda.
M. Le Ray seolah menjadi antitesis dari pemikiran Poincare. Le Ray, di mana ia menyatakan, misalnya, bahwa: “Science it consist only of conventions and it is solely to this circumstance that it owes its clear apparent certainly.” Le Ray juga menyatakan bahwa: “Science can’t teach us the truth, it’s can serve us only as a rule of action” (ilmu tidak mengerjakan tentang kebenaran, ia dapat menyajikan sejumlah kaidah dalam berbuat).
Dari beberapa definisi ilmu di atas, maka kandungan ilmu berisi tentang; hipotesis, teori, dalil, dan hukum. Hakikat ilmu bersifat koherensi sistematis. Artinya, ilmu harus terbuka kepada siapa saja yang mencarinya. Ilmu berbeda dengan pengetahuan. Ilmu tidak pernah mengartikan kepingan-kepingan pengetahuan berdasarkan satu putusan tersendiri. Ilmu justru menandakan adanya satu keseluruhan ide yang mengacu kepada objek atau alam objek yang sama dan saling berkaitan secara objektif. Setiap ilmu bersumber di dalam kesatuan objeknya.
Ilmu tidak memerlukan kepastian lengkap berkenaan dengan penalaran masing-masing orang. Ilmu akan memuat sendiri hipotesis-hipotesis dan teori-teori yang sepenuhnya belum dimanfaatkan. Karena itu, ilmu pasti membutuhkan metodologi, sebab, dan kaitan logis. Ilmu menuntut pengamatan dan kerangka berpikir metodis. Alat bantu metodologis yang penting dalam konteks ilmu adalah terminologi ilmiah
Baca Juga: Integrasi Ilmu Pengetahuan dan Spiritual Ala KH. Hasyim Asy’ari
Penulis: Wahyu Nur Oktavia, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.