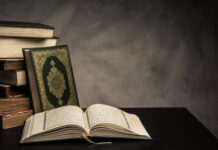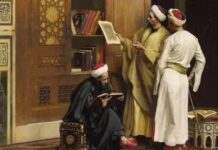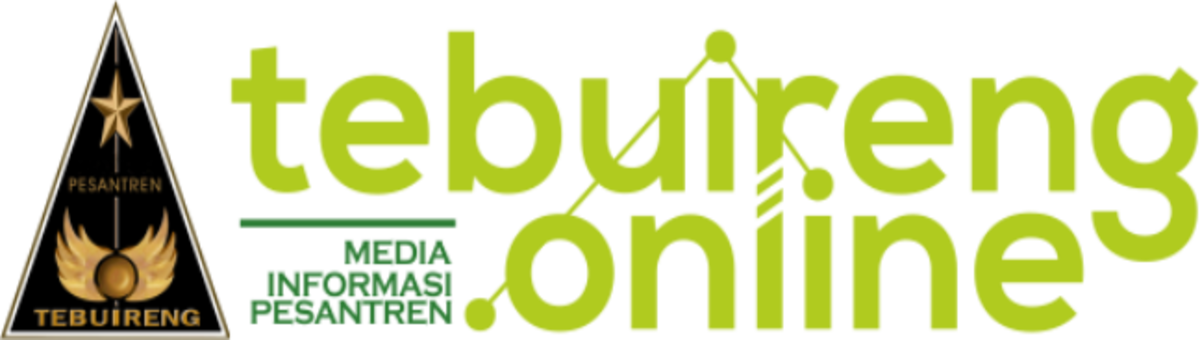Haji adalah ibadah yang terbilang istimewa di mata umat Islam. Pasalnya, ibadah ini memiliki waktu khusus dalam pelaksanakannya, yakni bulan Syawal, Dzulqa’dah, dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Sebab itulah, umat Islam berbondong-bondong ingin mendaftarkan dirinya untuk haji, kendati pun sebagian mereka tahu bahwa ia baru bisa melaksanakannya 25-40 tahun kedepan, sebab ketentuan kuota haji yang telah ditetapkan oleh kerajaan Arab Saudi. Hanya saja, hal ini tidak menjadi penghalang bagi sebagian orang yang berani melaksanakannya dengan menggunakan visa selain haji seperti kejadian yang sempat viral pada 14 Mei kemarin.
Disadur dari tempo.co, sebanyak 117 warga negara Indonesia (WNI) harus menerima kenyataan pahit setelah kedatangan mereka di Bandara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdulaziz, Madinah, ditolak oleh otoritas Imigrasi Arab Saudi. Mereka diduga berupaya menjalankan ibadah haji dengan menggunakan visa kerja, yang tidak sesuai peruntukannya.
Seluruh WNI tersebut akhirnya dipulangkan ke tanah air pada 15 Mei 2025. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Yusron B. Ambary, menyampaikan bahwa Tim Pelindungan Jamaah dari KJRI Jeddah memperoleh laporan pada 14 Mei mengenai sejumlah WNI yang ditahan oleh petugas imigrasi setempat. Diketahui bahwa para WNI tersebut masuk ke Arab Saudi menggunakan visa kerja jenis amil. Namun, aparat mencurigai adanya penyalahgunaan visa karena tujuan kedatangan mereka diduga bukan untuk bekerja, melainkan untuk berhaji secara tidak resmi atau non-prosedural.[1] Nah, fenomena ini mendorong penulis untuk menganalisis hukum pelaksanaan haji dengan visa selain haji, semisal visa kerja.
Baca Juga: Doa Agar Bisa Menunaikan Ibadah Haji
Dalam Al-Qur’an, Allah memerintahkan umat Islam untuk berhaji bagi mereka yang memenuhi syarat kemampuan (istitha’ah):
وَلِلَّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ البَيتِ مَنِ استَطاعَ إِلَيهِ سَبيلًا [ آل عمران: ٩٧ ]
“Dan [diwajibkan] bagi manusia untuk melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana.”(QS. Ali Imran: 97)
Kemampuan ini meliputi aspek finansial, kesehatan, dan keamanan perjalanan, serta menjadi syarat mutlak untuk memenuhi kewajiban haji. Namun, realitas di berbagai negara menunjukkan adanya perbedaan kemudahan akses dalam melaksanakan ibadah haji. Dalam literatur fikih kontemporer, di antara yang termasuk hal yang dianggap dalam isthitha’ah (kemampuan) adalah visa haji sebagaimana pejelasan dalam kitab Fadhlu Rabbil Bariyyah.[2] Begitu juga paspor sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji;
بم تتحقق الاستطاعة؟ والاستطاعة تتحقق بأن يملك الإنسان المال الذي يلزمه لأداء الحج والعمرة، من أجرة مركوب ونفقة ذهاباً وإياباً، بالإضافة لما تفرضه عليه اليوم الحكومات من نفقة جواز سفر، وأجرة مطوف، ويجب أن يكون هذا المال زائداً عن دينه وعن نفقة عياله مدة غيابه
“Dengan apa syarat mampu (istitha’ah) itu terpenuhi? Syarat mampu terpenuhi apabila seseorang memiliki harta yang dibutuhkan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, seperti biaya transportasi dan kebutuhan selama perjalanan pergi dan pulang, ditambah dengan biaya-biaya yang kini diwajibkan oleh pemerintah, seperti biaya paspor dan upah bagi petugas haji (muthawwif). Harta tersebut juga harus melebihi jumlah utangnya dan cukup untuk menafkahi keluarganya selama ia bepergian.”[3]
Oleh karena itu, seorang yang tidak memiliki visa haji dikarenakan terbatas kuota, maka ia belum masuk kategori isthitha’ah (mampu) sehingga ia tidak wajib untuk melaksanakannya. Namun, apabila haji dilakukan oleh orang yang tidak mampu, maka hajinya tetap sah.[4]
Baca Juga: Tiga Amalan Berpahala Setara Ibadah Haji
Hanya saja, hukum ini belum meninjau aspek penggunaan visa selain haji yang dianggap ilegal dalam peraturan negara. Dalam Islam, menaati peraturan yang bermuatan mashlahah ‘ammah (kemasalahatan umum) hukumnya adalah wajib. Termasuk di antaranya adalah peraturan mengenai visa haji. Kewajiban taat pada pemerintah ini sebagaimana firman Allah Swt.,
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِى اْلأ َمْرِ مِنكُمْ
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (Surat An-Nisa ayat 59).
Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman:
والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة
“Kesimpulannya adalah bahwa kepatuhan pada imam adalah wajib baik secara lahir maupun batin dalam apa yang ia perintahkan selagi apa yang ia perintahkan bukan hal yang haram atau makruh. (Dengan perintah imam ini), sesuatu yang wajib menjadi kukuh kewajibannya dan yang sunah menjadi wajib. Hal yang mubah juga menjadi wajib ketika di dalamnya terdapat kemaslahatan umum.”[5]
Adapun mengenai keabsahan hajinya maka terdapat (khilaf) perbedaan pendapat di antara ulama madzhab. Hal ini dikarenakan khilaf yang ada dalam kaidah ushul-fiqh, yakni sebuah larangan yang bersifat eksternal (amrin kharij) apakah berdampak pada tidak sah (fasad) atau tidak. Syekh Hasan Al-‘Ath-thar, ulama ushul-fiqh madzhab Syafi’iyyah menjelaskan, apabila larangan (nahyu) bersifat eksternal (amrin kharij), semisal shalat di tanah yang dighasab (tanpa izin), maka menurut mayoritas ulama hukum haram tetapi tidak berdampak pada ketidakabsahan sebuah ibadah atau akad, sedangkan menurut Imam Ahmad berdampak tidak sah.[6] Mengapa disebut eksternal, karena tindakan ghasab dapat terjadi dengan hal lain selain shalat, beda halnya dengan kasus larangan shalat di waktu-waktu yang dimakruhkan maka selain berhukum haram, status shalat juga tidak sah, sebab larangannya bersifat internal (nafsihi), dengan artian tindakan tersebut hanya dapat dilakukan dengan shalat, tidak bisa dengan tindakan lain.[7]
Karena dalam kaidah ushul-fiqh tadi terdapat khilaf di antara ulama, maka tak heran jika kita menjumpai keterangan khilaf yang sama dalam kitab-kitab fikih yang otoritatif (mu’tabar). Imam An-Nawawi dalam karya monumentalnya, Majmu’ Syarhul Muhadzdzab, menyatakan bahwa hukum haji dengan menggunakan uang yang dighasab (uang orang lain tanpa izin) haram dan sah menurut mayoritas ulama, sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal tidak sah.[8] Hal ini diperkuat oleh penjelasan Imam Al-Mardawi, salah seorang ulama Hanbali;
الْحَجُّ بِمَالٍ مَغْصُوبٍ، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ. نَصَّ عَلَيْهِ
“Haji dengan harta yang dighasab, menurut pendapat yang shahih dalam madzhab hanbali tidak sah”.[9]
Namun, yang perlu digarisbawahi adalah meskipun mayoritas ulama mengatakan sah, tetapi mereka tetap mengatakan haji dengan cara yang tidak legal secara syariat dianggap tidak mabrur dan kecil kemungkinan untuk diterima di sisi Allah Swt. Hal ini sebagaimana penjelasan Imam An-Nawawi;
فإن خالف وحج بما فيه شبهة أو بمال مغصوب صح حجه فى ظاهر الحكم ،ولكنه ليس مبرورا ويبعد قبوله،هذا هو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة رحمهم الله وجماهير العلماء من السلف والخلف
“Jika seseorang menunaikan haji dengan sesuatu yang syubhat (meragukan kehalalannya) atau dengan harta hasil ghasab, maka hajinya sah secara hukum lahiriah, tetapi tidak dianggap sebagai haji yang mabrur dan kecil kemungkinan untuk diterima. Inilah pendapat Imam Syafi’i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah rahimahumullah, dan mayoritas ulama dari kalangan salaf maupun khalaf.”[10]
Baca Juga: Keistimewaan Haji Mabrur
Dari uraian singkat di atas, dapat kita simpulkan bahwa hukum haji dengan menggunakan visa non-resmi (selain visa haji) berhukum haram. Hanya saja, statusnya sah menurut mayoritas ulama dan tidak sah menurut Madzhhab Hanbali. Oleh karena itu, tindakan haji seperti ini sebaiknya dihindari karena disamping memiliki dampak berbahaya kepada pelakunya, haji tersebut tidak dianggap haji mabrur menurut para ulama.
Penulis: Moh. Wildan Husin, Mahasantri dan penikmat Kopi.
[1] https://www.tempo.co/politik/117-wni-ditolak-masuk-saudi-karena-gunakan-visa-kerja-untuk-haji-1464018
[2] Fadhlul Rabbil Bariyyah fi Syarhil Durar al-Bahiyyah, Ibrahim Bin Muhammad 236
[3] Al-Fiqhu Al-Manhaji ‘ala Madzhabil Imam Asy-Syafi’i, 2/123
[4] Hasyiyatul Bajuri, Ibrahim Al-Bajuri, 1/309
[5] Bughyatul Mustarsyidin, Abdurrahman, 1/189
[6] Hasyiyatul ‘Ath-thar ‘ala Jam’il Jawami’, Hasan Ath-Thar, 1/501
[7] Ghayatul Wushul, Zakariya Al-Anshari, 72
[8] Al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab, Syarafuddin An-Nawawi, 7/62
[9] Al-Inshaf fi Ma’rifatir Rajih Minal Khilaf, Alauddin Al-Mardawi, 6/205
[10] Al-Idhah fil Manasik, Syarafuddin An-Nawawi,16