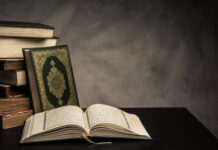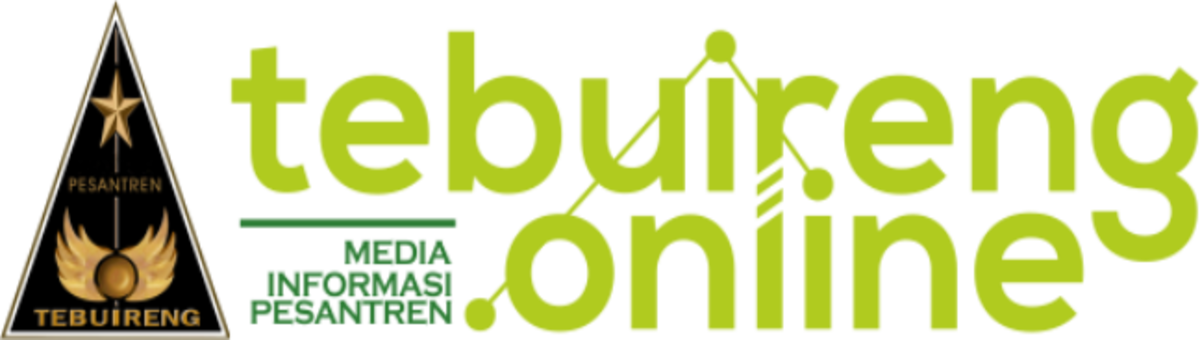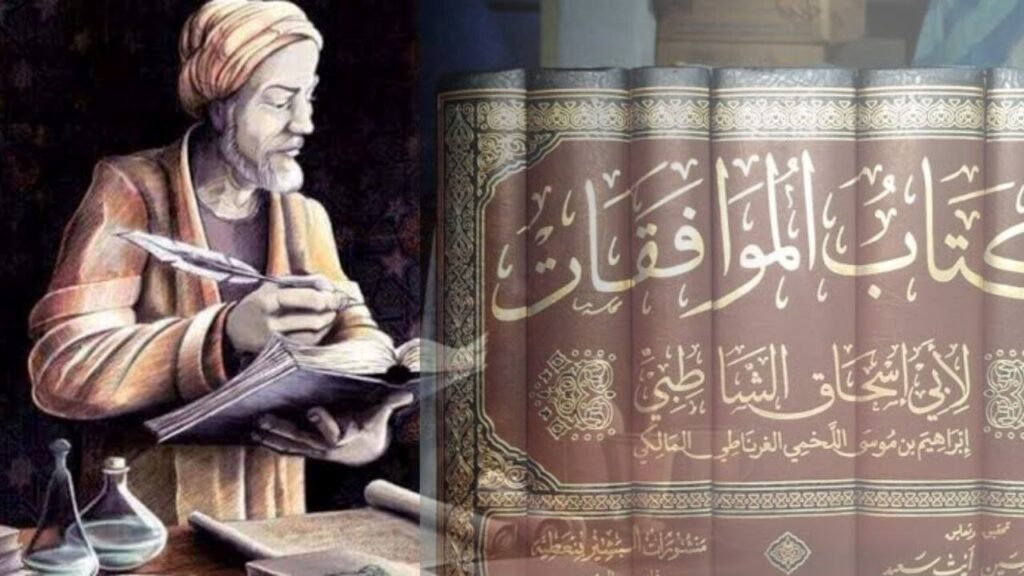
Dalam disiplin ilmu syariat tidak lepas dari pembahasan maqashid al- syari’ah. Maqashid al-syari’ah merupakan disiplin ilmu yang spesifik membahas mengenai tujuan dari adanya syariat itu sendiri. Pada dasarnya tujuan dari syariat adalah untuk meraih kemaslahatan dan menjauhkan kemafsadatan.
Adapun beberapa kasus yang terjadi di dunia adakalanya di banyak sisi mengandung nilai maslahat, namun di dalam sisi tertentu terdapat nilai mafsadat. Begitu juga adakalanya beberapa kasus banyak mengandung nilai mafsadat, namun di sisi lain mengandung nilai maslahah. Yang menjadi problematika adalah bagaimana menentukan apakah kasus tersebut bernilai maslahat atau mafsadat.
Abu Ishaq al-Syathibi dan Kitab al-Muwafaqat
Salah satu ulama yang membahas problematika tersebut adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syathibi, atau dikenal dengan al- Syathibi. Al-Syathibi adalah ulama Andalusia yang hidup di abad 14 Masehi. Dia banyak mengarang kitab, seperti al-Majalis, al-I’tisham, dan al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah.
Al-Syathibi dalam kitabnya al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah menegaskan bahwa dalam kehidupan di dunia ini tidak ada yang namanya maslahat yang benar-benar murni, begitu pula tidak ada mafsadat yang benar-benar murni. Artinya memang lumrah jika suatu kasus mengandung potensi maslahat sekaligus mafsadat.
Al-Syathibi memperingatkan bahwa dalam menentukan apakah suatu kasus termasuk maslahat atau mafsadat tidak bisa menggunakan perspektif nalar dan hawa nafsu manusia, akan tetapi harus menggunakan perspektif ilmu syariat yang mumpuni. Oleh karena itu, sikap yang diperlukan adalah muwazzanah(menimbang) dan tarjih(mengunggulkan/memprioritaskan).
Acuan Al-Syathibi dalam Menimbang Antara Maslahat dan Mafsadat
Beberapa hal yang dijadikan acuan dalam mempertimbangkan antara kemaslahatan dan kemafsadatan suatu perkara adalah maslahat adalah:
Analisa makna al-amr (perintah) dan al-nahy (larangan) dalam kandungan nash (Al-Quran dan Hadis).
Al-Quran dan hadis memuat al-amr (perintah) dan al-nahy (larangan). Al-amr adalah kandungan yang memuat perintah atau tuntutan untuk melakukan sesuatu dan al-nahy memuat kandungan tuntutan untuk meninggalkan sesuatu. Aspek al-amr dan al-nahy bisa dilihat dengan dua analisa.
Analisa pertama adalah dengan mujarrad al-amr wa al-nahy al-ibtida’ al- tasrihi, yaitu melihat perintah dan larangan dalam suatu dalil secara jelas dan tegas. Apabila suatu perintah dan larangan sudah jelas illat-nya maka harus diikuti. Contohnya adalah Q.S. al-Jumu’ah ayat 9 yang melarang aktivitas jual-beli saat waktu shalat Jum’at
Analisis kedua adalah jika ada dalil yang kandungan al-amr dan al-nahy tidak terlihat secara jelas dan tegas, dalam hal ini dibutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteksnya dengan mempertimbangkan illat-nya.
Contohnya adalah adanya al-amr untuk bersuci. Sebenarnya yang diperintahkan dalam nash adalah menunaikan shalat, namun di dalam perintah shalat juga mengandung perintah untuk bersuci dari hadas dan najis, karena itu menjadi syarat sah shalat. Dalam hal ini shalat adalah illat dari al-amr untuk bersuci tersebut.
Mengetahui maqashid al-ashli dan al-tawabi’.
Maqashid al- ashli merupakan tujuan awal dari suatu syariat dan maqashid al-tawabi’ adalah tujuan pengikut dari maqashid al-ashli. Adapun adanya maqashid al-ashli dan maqashid al-tawabi’ itu sudah termaktub dalam nash dan sebagian dari dalil-dalil lain.
Adanya tujuan pengikut berfungsi sebagai penguat dari tujuan awal. Jika al-Syathibi membagi maqashid menjadi dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat/kamaliyat. Maka bisa diilustrasikan bahwa tujuan awal merupakan hal yang bersifat dharuriyat, sedangkan tujuan pengikut bersifat hajiyat dan kamaliyat.
Contoh dari maqashid al-ashli dan al-tawabi’ adalah bab nikah. Pernikahan memiliki maqashid al-ashli yaitu menyambung nasab(keturunan), dan maqashid al-tawabi’ dari pernikahan adalah menjaga syahwat, membantu rumah tangga, dan sebagainya.
Menganalisa sukut al-syar’i
Menganalisa sukut al-syar’i merupakan menganalisa hal-hal yang tidak disebutkan oleh nash. Pasca wafatnya Rasulullah Saw, beberapa permasalahan yang terjadi tidak semua pernah dijelaskan secara tekstual dalam nash, seperti adanya penemuan baru seperti pesawat untuk pergi haji, mushaf digital, dan sebagainya.
Hal-hal yang tidak disebutkan dalam nash tersebut tidak dapat dihukumi secara tergesa-gesa. Hal tersebut merupakan sebuah pintu ijtihad. Oleh karena itu, dapat dilakukan ijtihad dengan pendekatan maslahah mursalah, yaitu dengan mempertimbangan antara maslahat dan mafsadat di dalamnya.
Jika dalam suatu kasus memiliki lebih banyak kandungan maslahat, maka hal tersebut boleh dilakukan. Contohnya adanya mushaf digital yang manfaatnya besar. Sedangkan jika dalam suatu kasus memiliki lebih banyak sisi kemafsadatan, maka perkara tersebut menjadi tidak boleh dilakukan. Seperti pendirian khilafah di negara demokrasi.
Istiqra’ (Teori Induksi)
Istiqra’ secara bahasa berarti “pengikutsertaan”, juga bisa dikatakan induksi. Secara istilah, istiqra’ merupakan metode yang digunakan untuk menentukan maqashid dari yang ‘am (umum) ke khas (khusus). Jika antara ‘am dan khas bertentangan maka istiqra’ tidak dibenarkan. Adapun istiqra’ bisa dilakukan dengan dua cara.
Pertama adalah istiqra’ pada nash syar’iyyah untuk mencari tujuan yang umum dari nash tersebut untuk menghasilkan dalil qath’i secara mutlak. Kedua, adalah istiqra’ terhadap arti-arti nash dan illat hukum. Dalil yang dipakai adalah dalil induksi dari beberapa dalil yang bersifat spekulatif sehingga terkumpul satu arti yang memberikan pengertian yang pasti.
Contoh dari istiqra’ adalah adanya jual beli online yang meskipun tidak tertulis secara khusus dan tekstual di dalam nash. Tapi hal ini berhubungan dengan Q.S. Al-Baqarah ayat 75 yang memiliki arti “Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.” Redaksi jual beli di ayat tersebut bersifat umum.
Baca Juga: Fikih Kemaslahatan Najmuddin al-Thufi untuk Kebhinekaan Indonesia
Penulis: Izzulhaq At Thoyyibi
Editor: Muh. Sutan