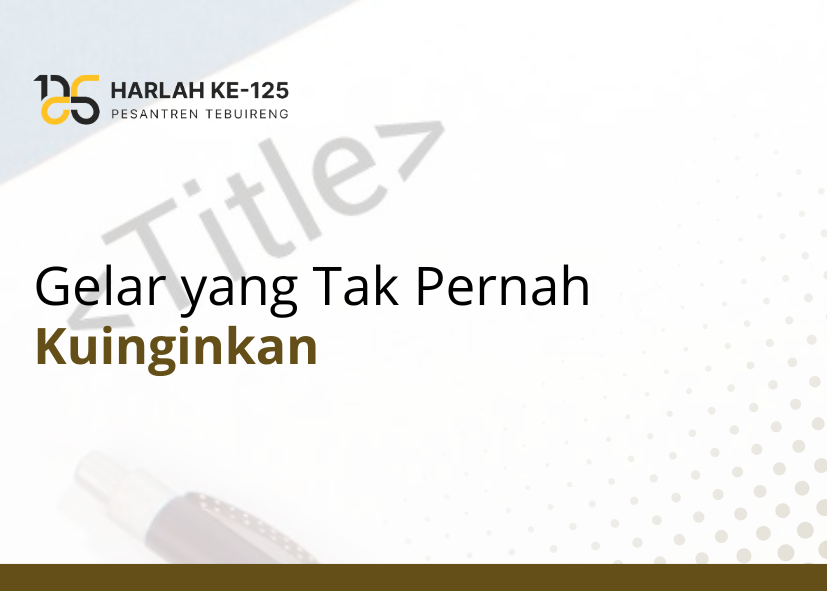
Langit sore di Tebuireng memancarkan warna oranye keemasan, membias lembut di antara pohon-pohon yang menjulang di sekitar pesantren. Suara adzan maghrib menggema dari kejauhan, bersatu dengan suara langkah-langkah santri yang bergegas menuju masjid. Udara sore yang sejuk berhembus pelan, membawa serta aroma khas tanah basah setelah hujan. Di halaman, beberapa santri duduk bersila, membaca kitab kuning dengan suara lirih yang berpadu dengan gumaman angin. Di kejauhan, menara masjid berdiri megah, seakan mengawasi segala aktivitas di bawahnya. Di tengah keheningan ini, hatiku terasa jauh, masih terjebak dalam keraguan tentang apa sebenarnya yang kucari di tempat ini.
Hari-hariku dimulai dari jam tayang pukul 03.00, di mana saat dunia masih terlelap, aku bangkit dari pembaringan. Langit di atas pesantren masih gelap, tapi keheningan ini begitu dekat dengan kehadiran-Nya. Salat tahajud mengalir, membawa sejuk ke dalam hati yang mungkin masih setengah terjaga. Saat adzan subuh berkumandang, langkah-langkah santri mulai melintasi lorong masjid. Selepas salat, lantunan Surah Al-Waqiah terucap dalam kebersamaan, ayat-ayat yang menjanjikan perlindungan, harapan, dan ketenangan. Selepas pengajian ba’da subuh, hari baru pun dimulai. Aku membereskan tempat tidur, menyuap sarapan dengan rasa syukur meski sederhana, lalu bersiap menuju sekolah. Di sana, dhuha berjamaah adalah jembatan menuju ilmu, sebuah doa yang kupanjatkan setiap pagi, semoga hari ini lebih baik dari kemarin.
Waktu terus berjalan hingga matahari mulai meninggi. Pelajaran demi pelajaran silih berganti sampai akhirnya sore menyapa. Pukul 15.00, aku kembali ke asrama, merebahkan tubuh sejenak sebelum rutinitas sore dimulai. Makan sore hanya sekedar mengisi perut sebelum menyalakannya lagi untuk shalat magrib berjamaah. Seusai magrib, pengajian kitab kuning membawaku ke dalam lautan ilmu yang begitu luas, meski terkadang terasa sulit, aku tahu ini adalah perjalanan panjang untuk memahami jalan hidup. Salat isya menjadi penutup malam, tetapi hatiku belum sepenuhnya tenang. Ada waktu luang, saatnya merenung di tengah malam yang akan segera kembali cerah. Setiap detik di pesantren ini seperti aliran air, tak bisa ditahan, dan aku masih bertanya-tanya, apakah hatiku sudah benar-benar larut dalam aliran ini?
Aku masih ingat hari ketika ayah memaksaku untuk mondok. Sebelumnya, aku sudah terbiasa dengan rutinitas mengaji, menghadiri halaqah setiap sore, meskipun aku tidak benar-benar tinggal di pesantren. Aku hanyalah santri kalong—datang dan pergi, menimba ilmu tanpa terikat pada aturan ketat pesantren. Itu cukup bagiku. Namun, entah mengapa, ketika aku mulai masuk SMA, ayah berkeras agar aku tinggal di pesantren, agar aku benar-benar menjadi “santri”.
Hari itu, aku duduk di depan meja makan, memandang wajah ayah yang serius. Suara sendok beradu dengan piring, namun keheningan terasa menusuk. Ayah menatapku dengan penuh keyakinan, seolah keputusan ini sudah lama ia pikirkan.
“Kamu harus mondok,” ujarnya tanpa basa-basi.
Aku menelan ludah, mencoba menata argumen yang mungkin bisa membuatnya mengubah pikiran. “Ayah, aku sudah mengaji. Setiap sore aku belajar di pesantren tanpa perlu mondok. Aku merasa cukup.”
Ayah menggeleng, ekspresi wajahnya tak sedikit pun berubah. “Mengaji saja tidak cukup. Kamu harus memahami arti sesungguhnya menjadi santri. Mondok di pesantren akan mendidikmu lebih dalam tentang kehidupan, tentang kemandirian, dan yang terpenting, tentang hati.”
Tentang hati? Aku tak yakin memahami apa yang dimaksud ayah. Mondok bukanlah hal yang kuinginkan. Selama ini aku sudah merasa cukup dengan jadwal harian yang penuh; belajar di sekolah di pagi hari, mengaji sore hari, dan kembali ke rumah pada malamnya. Apa lagi yang kurang? Apakah menjadi santri harus sesulit itu?
Namun, melawan kehendak ayah sama saja seperti melawan takdir. Jadi, pada akhirnya, dengan berat hati, aku mengemasi barang-barangku dan bersiap untuk pindah ke pesantren Tebuireng. Hari pertama tiba, dan aku merasa asing di lingkungan yang seharusnya sudah kukenal. Bangunan-bangunan yang selama ini kulihat dari luar kini menjadi rumahku. Tapi entah mengapa, meski aku ada di dalamnya, aku merasa tak sepenuhnya menjadi bagian dari dunia ini.
Hari-hari awal di Tebuireng terasa berat. Aku merindukan kebebasan—merindukan rumah, tempat di mana aku bisa menuntut ilmu tanpa harus menjalani segala rutinitas pesantren. Bangun sebelum subuh, shalat berjamaah, hafalan Qur’an, dan berbagai kegiatan yang seolah tiada henti. Semua itu menghimpit dadaku. Aku merasa terpaksa, seperti burung yang dipaksa masuk ke dalam sangkar, terbang di bawah aturan yang bukan keinginanku.
Namun, satu hal yang membuatku terus bertahan adalah wejangan para kiai. Ada kedamaian dalam setiap kata mereka, meskipun aku tidak selalu mengerti apa maksudnya. Setiap sore, kami duduk di aula, mendengarkan ceramah yang penuh hikmah. Hingga tibalah satu hari yang berbeda, hari perayaan 125 tahun berdirinya pesantren Tebuireng.
Di aula besar yang penuh sesak oleh santri dan masyarakat sekitar, aku duduk di antara mereka, seperti yang lain, tapi perasaanku tetap berbeda. Aku masih belum bisa menyebut diriku “santri” dengan sepenuh hati. Aku hanya menjalani rutinitas, tidak lebih dari itu. Hatiku masih ada di luar, terjebak di antara kebebasan dan kewajiban yang aku sendiri tidak tahu harus ke mana.
Di depan kami, seorang Kiai berdiri, wajahnya yang teduh memancarkan aura kebijaksanaan. “Hari ini, kita merayakan 125 tahun Pesantren Tebuireng. Selama itu pula kita telah melihat banyak santri datang dan pergi, membawa ilmu yang telah diajarkan di sini. Namun, pada kesempatan ini, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang lebih mendasar. Tentang apa artinya menjadi santri,” suara Kiai lembut namun tegas.
Aku mendengar dengan setengah hati, berpikir bahwa ini hanyalah ceramah biasa. Tapi kemudian, kata-kata beliau mulai menusuk. “Santri bukanlah tentang penampilan. Bukan tentang bagaimana kamu berpakaian dengan sarung atau kopiah, atau bagaimana kamu menghafal ratusan ayat dan hadits. Santri adalah soal hati. Soal ketulusan menerima ilmu, soal niat yang ikhlas, dan soal menjaga amanah ilmu itu di dalam kehidupan sehari-hari.”
Kata-kata itu membuatku tertegun. Tentang hati? Bukankah aku selama ini merasa hatiku tidak ada di sini? Bukankah aku hanya menjalani semua ini sebagai kewajiban, tanpa keinginan dari dalam diriku?
“Menjadi santri,” lanjut Kiai, “adalah proses perjalanan batin. Mungkin di awal, kamu merasa terpaksa. Mungkin kamu berpikir bahwa ini bukan tempatmu. Tapi percayalah, jika kamu membuka hatimu, kamu akan menemukan makna yang lebih dalam. Menjadi santri bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan dari luar. Itu harus datang dari dalam diri. Dari hatimu sendiri.”
Aku merasakan gelombang emosi yang aneh. Bagaimana mungkin Kiai tahu apa yang aku rasakan? Seolah-olah setiap kata yang ia ucapkan menyentuh langsung perasaanku yang terdalam. Aku mulai merenung, mungkin selama ini aku salah. Aku terlalu fokus pada penampilan luar, pada aturan-aturan yang mengikat, tanpa benar-benar memahami makna di balik semua ini.
Ketika Kiai selesai berbicara, aula hening sejenak, sebelum akhirnya disusul dengan tepuk tangan dari para santri dan hadirin. Tapi aku tidak bisa ikut bertepuk tangan. Bukan karena aku tidak setuju, tetapi karena aku masih mencerna apa yang baru saja kudengar. Hati ini terasa berat, seolah ada sesuatu yang harus kuperbaiki, sesuatu yang telah lama kulewatkan.
Malam itu, aku merenung di kamar. Di antara heningnya pesantren yang sudah mulai tertidur, aku teringat akan wejangan ayah tentang hati. Mungkin inilah yang ia maksudkan. Bahwa ilmu yang kuterima di sini tidak hanya tentang kitab, tentang hafalan, atau tentang aturan. Semua itu hanyalah alat untuk mendidik hati, untuk menanamkan ketulusan dalam setiap langkahku. Dan mungkin, selama ini aku terlalu menutup hati, terlalu mengeluhkan apa yang aku anggap sebagai paksaan, tanpa mencoba melihat kebaikan di baliknya.
Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Aku mulai menjalani rutinitasku dengan cara yang lain. Tidak lagi merasa terbebani, tetapi mencoba menemukan makna di balik setiap langkah. Ketika aku menghafal ayat, aku merenungkan artinya, bukan hanya sekadar mengingat. Ketika aku menghadiri halaqah, aku membuka pikiranku untuk menerima nasihat yang diberikan. Dan ketika aku duduk bersama santri lainnya, aku mulai melihat mereka sebagai saudara seperjalanan, bukan sekadar teman satu pondok.
Kini, ketika aku berdiri di bawah langit Tebuireng yang mulai diterangi oleh bintang-bintang malam, aku menyadari sesuatu yang penting. Mondok di sini mungkin bukan keinginanku dari awal. Tapi di balik setiap detik yang kulalui, ada pelajaran berharga yang mulai kuterima. Pelajaran tentang hati yang tulus, tentang ilmu yang harus dijaga, dan tentang menjadi santri—bukan hanya dari penampilan, tetapi dari hati.
Penulis: Mei Nurwanda



















