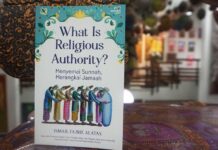Alya duduk di serambi musala putri, menatap langit sore yang mulai temaram. Angin pondok berhembus pelan, membawa harum tanah yang baru disiram. Di tangannya, sebuah buku catatan kecil terbuka, penuh coretan puisi dan doa yang tak pernah sempat dikirimkan.
Hari itu, kabar menyebar seperti angin: Mas Faiz akan menikah. Alya tak menangis. Tidak di depan siapa pun. Tapi hatinya? Retak pelan-pelan seperti kaca yang ditahan untuk tidak pecah.
Mereka tak pernah berpacaran. Bahkan tak pernah benar-benar bicara. Tapi diam-diam, mereka saling menjaga. Saling tahu. Saling mendoakan dalam diam yang suci.
Pertemuan pertama mereka terjadi setahun lalu, di perpustakaan pondok saat kegiatan gabungan. Faiz sedang mencari kitab kuning, Alya sedang mencatat tafsir. Mata mereka sempat bertemu. Hanya sebentar. Tapi cukup untuk membuat hati Alya gelisah seminggu penuh.
Sejak itu, Alya mulai sering menemukan kertas kecil di sela kitab-kitabnya. Bukan surat cinta, hanya catatan ilmu atau kutipan hadits. Tapi ia tahu, siapa pengirimnya. Tulisan tangan itu terlalu khas untuk disalahkan.
Faiz tak pernah menyapa. Tak pernah mendekat. Tapi selalu ada dalam setiap bait puisi Alya, dan dalam sujud-sujud panjangnya.
Beberapa minggu setelah sering menemukan tulisan Faiz, Alya mulai gelisah. Ia ingin membalas. Tapi bagaimana? Bicara langsung bukan pilihan. Maka ia memilih jalannya sendiri: menulis puisi.
Di suatu pagi yang sepi, Alya menyelipkan selembar kertas kecil ke dalam kitab kuning yang biasa dipakai saat kajian gabungan.
Puisi itu ia tulis diam-diam:
“Kita tak saling sapa, tapi saling tahu arah doa.
Kita tak berjalan berdampingan, tapi menunduk di jalan yang sama.
Jika ini tak sampai di dunia, semoga Allah satukan di akhirat sana.”
Ia menulis tanpa nama. Hanya sebuah inisial: A.
Kitab itu kemudian ia titipkan pada ustazah dengan alasan “tertinggal di musala putra.” Sebuah trik sederhana, tapi cukup untuk menyampaikan rasa tanpa melanggar adab.
Sejak hari itu, Faiz tak lagi meninggalkan catatan. Tapi Alya tahu… kadang diam juga bisa jadi bentuk jawaban paling jujur.
Hingga hari itu tiba.
Beberapa hari setelah kabar itu menyebar, Alya berusaha menerima. Tapi menerima bukan hal mudah bagi hati yang pernah berharap. Terlebih saat rasa itu tumbuh dalam sunyi, dan ia tak pernah punya cukup alasan untuk melupakannya.
Sore itu, gerimis turun malu-malu. Seorang santri memanggilnya di depan kamar.
“Alya… ada titipan buatmu. Dari pondok putra.”
Alya keluar dengan langkah pelan. Seorang santri akhwat menyerahkan kantong kertas kecil.
“Mas Faiz titip ini. Katanya, tolong dibuka saat sendiri.”
Alya mengangguk. Tangannya gemetar saat membuka bingkisan itu. Di dalamnya ada sebuah buku kecil berjudul “Sabar Itu Indah”, dan selembar surat yang dilipat rapi. Tulisan tangan yang ia kenal.
“Alya, terima kasih karena pernah menjadi alasan aku menjaga hati.”
“Aku pamit. Bukan karena lupa, tapi karena ini jalan yang Allah pilihkan.”
“Semoga kita tetap bertemu, di jalan ilmu dan dalam doa yang sama.”
Air mata Alya jatuh perlahan. Ia tak tahu rasa ini harus disimpan di mana. Tak bisa marah, karena mereka tak pernah mengikat. Tapi juga tak bisa benar-benar merelakan.
Malamnya, ia menutup jendela kamar, lalu membuka catatan kecilnya. Di halaman terakhir, ia menulis:
“Tak semua harap harus sampai. Ada yang cukup tumbuh, lalu direlakan. Aku hanya ingin dia bahagia, meski bukan denganku”.
Ia menatap langit, lalu memeluk buku itu erat.
Penulis: Wan Nurlaila Putri
Editor: Rara Zarary