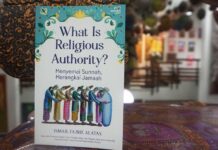Aku sudah lima kali jadi panitia wisuda tahfidz di pondok ini. Lima kali menyusun kursi, mempersiapkan panggung, menata makanan, menyambut para orang tua yang datang dengan wajah penuh bangga. Lima kali juga aku berdiri di pojokan, memeluk mushafku sendiri. Menatap teman-teman seangkatanku naik ke panggung, menerima piagam, mencium tangan Kiai, dengan senyum lebar di wajah mereka.
Aku tersenyum. Tapi di dalam hati, aku remuk. Aku bertanya pada diriku sendiri, Kapan aku? Kapan namaku dipanggil di antara mereka? Aku tidak malas. Aku tidak main-main. Aku hanya lambat. Menghafal satu halaman saja butuh berkali-kali murojaah. Setiap salah satu ayat, aku mengulang dari awal lagi. Dan di balik senyumanku di acara itu, aku tahu… aku berjuang lebih keras daripada yang orang lihat. Orang tuaku tidak pernah benar-benar bangga.
“Anaknya Bu Rani itu udah hafal 30 juz waktu kelas 3 SMP, loh,” kata ibu suatu sore, ketika aku pulang mondok.
Aku hanya mengangguk, menahan kata-kata yang mengganjal di tenggorokanku.Tapi aku diam. Aku percaya, Allah tidak buta. Hari itu, akhirnya tiba setelah bertahun-tahun, aku khatam. Tanganku gemetar waktu menyelesaikan ayat terakhir. Aku sujud syukur sambil menangis, menggenggam mushaf kecilku yang lusuh.
Kiai memanggilku dengan senyum hangat.
“Alhamdulillah, akhirnya ya, Nak. Kau selesai.” Aku mengangguk sambil mengusap air mata. “Iya, Yai…”
Namaku masuk dalam daftar wisuda tahun ini. Aku menjemput ayah dan ibu di bandara untuk menuju kepenginapan yang sudah ku pesan. Di perjalanan, aku mengemudi mobil sewaan sambil sesekali melirik ke belakang, memastikan mereka nyaman.
“Ibu seneng ya?” tanyaku pelan. Ibu hanya tersenyum kecil.
“Nanti kamu jangan malu-malu ya, waktu cium tangan Kiai. Akhirnya bisa juga kamu kayak yang lain.”
Aku mengiyakan, walau di dalam hatiku, aku hanya ingin mereka berkata: Kami bangga padamu, bukan karena kamu wisuda, tapi karena kamu bertahan.
Tapi takdir berkata lain. Di tikungan sempit, sebuah truk melaju dari arah berlawanan. Aku hanya sempat melihat lampu sorot itu, sebelum dunia gelap.
****
Hari wisuda itu, bukan aku yang berdiri di panggung bukan aku yang mencium tangan Kiai. Bukan aku yang mengangkat mushaf sambil tersenyum bangga. Hanya ada kursi kosong dengan namaku yang tertulis rapi di atasnya. Ibu menangis tanpa suara. Ayah menunduk dalam. Aku sudah tidak di sana.
Yang naik ke panggung adalah orang tuaku. Dengan langkah gontai, mereka menerima piagamku dari tangan Kiai. Suasana sunyi. Bahkan udara pun terasa berat. Kiai memegang mikrofon. Suaranya bergetar.
“Ananda ini,” katanya sambil menunjuk piagam itu, “adalah salah satu santri yang paling istimewa bagi saya.” Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang.
“Dia tidak cepat. Dia tidak mudah. Tapi dari setiap ayat yang dia perjuangkan… saya sebagai gurunya ikut dapat pahala.
Setiap kesulitannya… menambah keberkahan bagi pondok ini. Dia adalah cobaan bagi saya sebagai seorang Kiai, apakah saya sabar dalam mendidik, ataukah saya hanya mau mendidik anak-anak yang mudah.” Air mata jatuh dari mata Kiai.
“Anak ini… bukan gagal. Dia pemenang. Dia tidak berlari kencang seperti yang lain, tapi dia tidak pernah menyerah. Dan itu yang membuat Allah lebih mencintainya.” Ibu terisak keras di bangku tamu. Ayah memejamkan mata, menggenggam erat piagam yang seharusnya ada di tanganku.Penyesalan datang terlambat. Mereka baru tahu, betapa besar perjuanganku. Baru sadar, bahwa anak yang lambat ini…telah berjuang lebih dari sekadar kecepatan.
Surat yang Tak Pernah Tersampaikan
Untuk Ayah dan Ibu,
Kalau surat ini sampai ke tangan kalian, mungkin aku sudah tidak lagi bisa memeluk kalian. Aku cuma mau bilang… aku tidak pernah marah. Aku tahu, semua kata-kata yang dulu menyakitiku… mungkin kalian ucapkan karena kalian ingin aku jadi yang terbaik.
Tapi seandainya waktu bisa diputar, aku ingin sekali kalian tahu: Setiap halaman mushaf yang kubaca, aku bacakan juga untuk kebahagiaan kalian. Setiap ayat yang kuhafal sambil menangis, aku niatkan supaya kelak kita bisa berkumpul lagi di surga.
Bukan soal siapa yang tercepat. Bukan soal siapa yang paling banyak dapat piagam. Aku hanya ingin menjadi anak yang cukup, meski jalanku penuh jatuh dan bangun. Aku ingin kalian bangga, bukan pada kehebatanku… tapi pada ketabahanku.
Ayah, Ibu,
Kalau hari ini kalian memegang piagamku, itu bukan karena aku hebat. Itu karena Allah tahu aku mencoba sekuat yang aku bisa. Dan sekarang, aku sudah tenang.
Aku sudah selesai berjuang. Tinggal kalian yang aku titipkan doa, semoga Allah menguatkan hati kalian, sama seperti dulu aku berjuang menguatkan hatiku, diam-diam, sendirian.
Kalau nanti kalian rindu, bacalah satu ayat dari mushaf. Itu cukup bagiku. Karena di antara ayat-ayat itu… ada aku.
Dengan cinta,
Anakmu yang tak pernah berhenti berusaha.
Penulis: Wan Nurlaila Putri
Editor: Rara Zarary