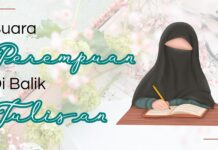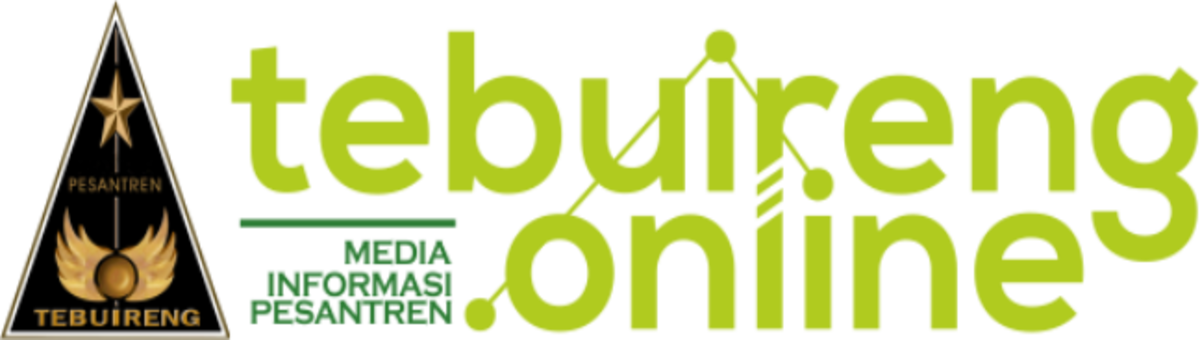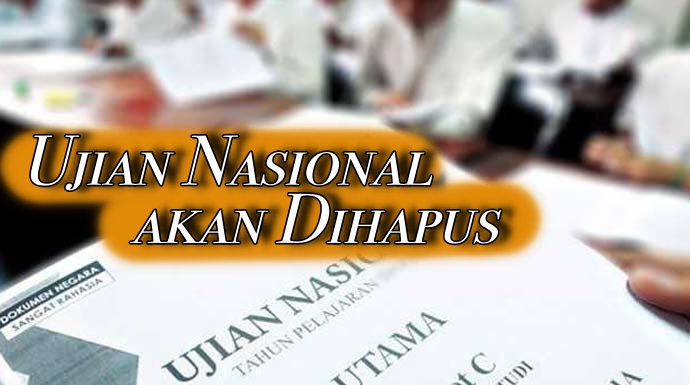
Oleh: Muhammad Abror Rosyidin*
Riwayat evaluasi akhir belajar dalam setiap tingkatan pendidikan di Indonesia memang mengalami perubahan cukup banyak secara periodik. Mulai dari Ujian Penghabisan (UP) pada tahun 1950-1960, Ujian Negara pada 1965–1971, Ujian Sekolah pada 1972–1979, Evaluasi Belajar Tahap Nasional (Ebtanas) pada 1980–2002, Ujian Akhir Sekolah (UAS) pada 2003-2007, Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) pada 2008-2010 dan Ujian Nasional (UN) pada 2011-sekarang dan Ujian Sekolah/Madrasah pada 2014-sekarang (Khusus SD/MI).
Tahapan itu tentu adalah bentuk realiasasi program kebijakan pendidikan kementerian terkait dengan berbagai pertimbangan. Mata pelajaran yang diujikan juga berubah-ubah. Begitu juga nilai minimumnya. Tentu formulasi yang berganti-ganti merupakan usaha dalam penyempurnaan kualitas pendidikan bangsa sebagai realisasi amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, bagaimana jika penyempurnaan itu dihentikan? Dalam arti, evaluasi akhir belajar semacam UN dihapus?
Ujian Nasional, Dihapus atau Diganti?
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mengumumkan rencana pemerintah menghapus Ujian Nasional pada 2021 nanti. Berarti pada 2020, UN terakhir dilaksanakan dalam pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo. Tentu keputusan ini menimbulkan silang pendapat di kalangan masyarakat, terutama akademisi dan praktisi pendidikan. Karena UN seperti tradisi turun-temurun, rutin saban tahun dilaksanakan. Walaupun namanya diganti-ganti sepanjang sejarah pendidikan Nasional pasca kemerdekaan.
Presiden Joko Widodo menyatakan dukungan terhadap gebrakan sang Mantan CEO Gojek itu. Namun, baru-baru ini, “Mas” Menteri menolak disebut menghapus UN, tetapi menggantinya dengan formula yang lain. Ia akan mengubah versi lama ujian nasional dan diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang akan mengukur kemampuan nalar siswa.
Penulis teringat dengan wacara-wacana penghapusan ujian untuk masa akhir belajar di setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah, kemudian menghadirkan nama baru dengan format baru. Sekali lagi, format, bukan konsep dasar. Dari masa Ujian Penghabisan hingga Ujian Nasional, menurut hemat penulis, kementerian terkait hanya mengubah sistem, pola, metode, dan penilaian saja, tidak sampai pada tataran konsep dasar.
Wacana menghapus UN sebelumnya telah berkali-kali dicuatkan ke permukaan layar pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Muhammad Nuh pada 2013 lalu telah menyatakan wacana penghapusan UN karena dianggap tidak efektif. Pada masa akhir jabatannya, memulai dengan penghapusan UN di tingkat SD/MI saja. UN masih tetap berlaku hingga sekarang.
Mendikbud 2014-2019 Muhajir Effendy juga pernah menyatakan ingin menghapus UN. Namun, pernyataan yang terburu-buru dan berbelit-belit membuatnya tak meyakinkan masyarakat, bahwa ia bakal jadi menghapus UN. Sempat yakin akan disetujui oleh Presiden, tetapi lagi-lagi UN masih terus berjalan. Perubahan sistem dan format dalam kebijakan setiap menteri pastinya ada, tetapi tidak menyentuh ranah konsep dasar sama sekali. Itu artinya, mereka gagal menghapus UN.
Lalu, pernyataan Nadiem bahwa ia tidak menghapus UN apakah hal itu sesuai? Mari kita teliti pernyataan Mas Menteri itu ketika momen mengumumkan “penggantian konsep” di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, pada Rabu, 11 Desember 2019 lalu.
“Asesmen kompetensi minimum adalah kompetensi yang benar-benar minimum di mana kita bisa memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimum. Apa itu materinya. Materinya yang bagian kognitifnya hanya dua. Satu adalah literasi dan yang kedua adalah numerasi”.
Dari pernyataan itu, menurut penulis, Mas Menteri jelas upaya menghapus bukan sekedar memperbaiki atau menyempurnakan sistem, justru tampak sangat berbeda dengan konsep dasarnya. Hanya saja, waktu pelaksaannya sama, akhir dari pembelajaran setiap tingkatan pendidikan dasar dan menengah. Berbeda dengan wacana dan realiasasi upaya penghapusan UN pada kasus dua menteri sebelumnya.
Analoginya begini, “Saya mengganti tulisan di papan tulis ini dengan tulisan yang yang lain”. Mengganti sesuatu dengan yang lain, ada dua kemungkinan, memindahkan hal yang lama, lalu diganti dengan yang baru, atau menghapusnya lalu diganti. Keduanya sama-sama berangkat dari semangat sama, memindah atau menghapus.
Berbeda jika begini, “Saya menulis di papan, setelah saya baca, saya merasa ada yang kurang tepat, maka saya revisi beberapa bagian tulisan saya dengan yang lebih tepat”. Tulisannya secara utuh tidak hilang, tapi direvisi dan disempurnakan seiring dengan dinamika pemikiran manusia dan kebutuhan pendidikan.
Mas Nadiem melakukan yang mana? Penulis melihat upaya Mas Nadiem sesuai dengan analogi pertama. Jika terealisasi, UN tidak ada, secara sistem maupun konsep dasar dihapus, baru diganti dengan program lain. Bisa jadi di-pause, di-skip, atau di-delete selamanya. Kalau dipindahkan rasanya tidak mungkin. Sementara kasus yang sudah-sudah, hanya namanya saja berganti, diiringi dengan proses evaluasi dan penyempurnaan, lalu disesuaikan dengan kebutukan dan dinamika sosiokultural manusia.
Bukan soal menghapus atau tidak, karena itu merupakan pemikiran yang sangat revolusionis dan futuristik. Tapi mbok ya kalau menghapus, menghapus saja, tidak usah berkilah diganti. Sama saja. Mas Nadiem kalau memang ingin mengubah tatanan lama, harusnya sekalian saja. Tidak mengkaburkan istilah yang berujung pada ketidaksesuaian dengan faktanya.
Komentar Tokoh
Mantan Ketua PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif meminta rencana Mendikbud Nadiem untuk mengubah format UN tidak diputuskan secara tergesa-gesa. Ia khawatir jika UN diganti formatnya bisa membuat para siswa tidak sungguh-sungguh dalam belajar. Kritikan juga datang dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. JK berpesan agar kebijakan ini jangan sampai melemahkan kemampuan siswa. Dua tokoh ini meminta Nadiem agar dara mudanya tak terlalu menggebu-gebu, sehingga lupa dengan high impact-nya bagi keberlangsungan pendidikan.
Yang menarik lagi adalah usulan dari Pengasuh Pesantren Tebuireng, Gus Sholah yang menyarankan agar UN tidak dihapus, melainkan mengulur waktunya hanya tiga tahun sekali. Kebutuhannya jelas, untuk mengukur kualitas pendidikan kita saja, bukan fokus untuk tolok ukur kemampuan siswa.
Alasannya, katanya, tekanan mental kepada siswa bisa dikurangi jika UN dilaksanakan tiga tahun sekali. Sementara juga biayanya bisa dipakai untuk melatih meningkatkan mutu guru. Titik berat Gus Sholah, bahwa masalah paling berat kita adalah mutu guru yang masih tidak baik. Lebih dari separuh guru tidak baik. Seharusnya ini jauh lebih segera ditindaklanjuti dan dievaluasi, lalu dicarikan solusinya, karena pendidikan sangat bergantung pada kualitas tenaga pendidik.
Menghafal Tak Selalu Buruk
Penulis membaca berita dalam merdeka.com bahwa Mas Menteri berujar “Dunia tidak membutuhkan anak-anak yang jago menghafal”. Pikiran penulis langsung tertuju pada pengalaman penulis ketika nyantri di pesantren sejak SLTP hingga bangku kuliah. Penulis disibukkan dengan tradisi menghafal, misal saja hafalan nadhaman gramatika Arab. Ada bait syiir Imrithi dan Alfiyah Ibn Malik, hafalan malfudhat (pepatah) Arab, Hadits, Al Quran, dan lain-lain.
Hingga sekarang, metode hafalan masih diterapkan, bahkan menjadi salah satu ukuran kelulusan santri di beberapa pesantren, seperti Lirboyo, Ploso, Sidogiri, dan pesantren model salafiyah (tradisional) lainnya. Memang pesantren bukanlah garapan Kemendikbud, tapi tentunya perlu Mas Nadiem sowan ke pesantren, meneliti soal hafalan, agar mengetahui seberapa efektif metode itu diterapkan untuk para santri. Kok bisa mereka, para penghafal itu, kemudian hari setelah ditempa bisa menjadi ulama, kiai handal, bahkan cendekiawan dan intelektual. Di antara mereka ada yang sangat memahami ilmu, baik teks maupun konteks.
Mas Nadiem ini, penulis lihat, sama dengan anak-anak muda era ini yang cenderung ingin patas, akseleratif, dan cepat sampai tujuan. Mas Nadiem perlu tahu, yang ditumpangi itu, kereta, pesawat, sepeda onthel, andong kuda, atau cikar sapi? Sama-sama berpotensi sampai tujuan, tapi berbeda soal waktu tempuh. Tak selamanya pesawat bisa mengantarkan kita pada tujuan, begitu juga kereta yang lain. Atau tak selalu andong dan cikar, memiliki pontensi rendah sampai pada tujuan.
Artinya, pernyataan Mas Menteri harusnya dikaji secara mendalam. Metode menghafal tak selalu buruk. Karena dalam satu dua kasus, ia masih sangat dibutuhkan. Bisa jadi untuk orang-orang atau lembaga-lembaga tertentu menghafal dipercaya memiliki pontensi memahami yang cukup tinggi. Jika tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, maka alat dan pirantinya dapat disediakan secara bebas, tinggal memilih yang mana. Bukan menyudutkan metode hafalan, biarkan saja dia mewarnai. Toh, lagi-lagi, sistemnya juga yang harus diperbaiki. Menghafal baru memahami, menghafal sambil memahami, atau langsung memahami dengan penalaran, ya silahkan saja.
Butuh Kajian Lebih Dalam
Tahun 2021 masih dua tahun lagi kurang lebih. Tentunya masih ada waktu bagi Kemendikbud untuk mengkaji secara lebih dalam. Tak perlu buru-buru menentukan kebijakan. Apalagi hanya sekadar mengejar prestasi 100 hari kerja. Halo, kita harus ingat bahwa kebijakan pemerintah sangat berpengaruh terhadap rakyat untuk masa yang tak sebentar.
Dinamika pemikiran manusia dan kebutuhan zaman bisa jadi berubah. Jutaan pelaku dan objek pendidikan bergantung pada kebijakan periodik dan temporal, tentu ini bukan tujuan adanya pemerintah. Karena tujuannya jelas, mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan uji coba semata. Bisa jadi apa yang direncakan Mas Menteri baik bagi keberlangsungan pendidikan, bisa jadi juga sebaliknya. Wallahu a’lam.
Relatifitas masih terus berjalan, senada dengan perkembangan kebutuhan. Jangan sampai, dinamika kebijakan sektoral, dapat membuat generasi bangsa menjadi pengekor sistem. Penulis tidak bermaksud menyudutkan, bahkan sebenarnya sangat salut dengan semangat revolusionis Mas Menteri sangat luar biasa. Gebrakan-gebrakan lain, penulis lihat juga sangat bagus, misal soal penyederhanaan administrasi dan birokrasi pendidikan yang selama ini cenderung menghabiskan energi pelaku pendidikan, dari pada proses belajar mengajar.
Lagi, termasuk program penyederhanaan materi sekolah, misal teori pelajaran bahasa Inggris dihabiskan di SD, dan menerapkan praktik berbahasa di tingkatan selanjutnya, cukup membuat penulis terpukau. Sangat futuristik dan kekinian. Tapi, tetap, harus dikaji lebih mendalam, tidak usah terburu-buru. Kalau jalannya terjal dan licin, hati-hati terpeleset, apalagi di bawah banyak ranjaunya.
Wah, kalau sudah bahas ini panjang lagi perbincangannya. Sudahlah, yang terpenting sekarang, semoga Mas Menteri sukses dengan programnya. Sebagai rakyat, penulis hanya mampu memberikan saran-saran sebagai bukti kecintaan dan kepedulian. Selamat bekerja Mas Nadiem. Semoga selamat sampai tujuan dan jet super cepatnya tidak tergelincir. Ma’as Salamah fi amanillah.
*Mahasiswa Pascasarjana Universitas Hasyim Asy’ari (Unhasy) Tebuireng Jombang
Editor: Rara Zarary