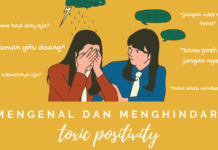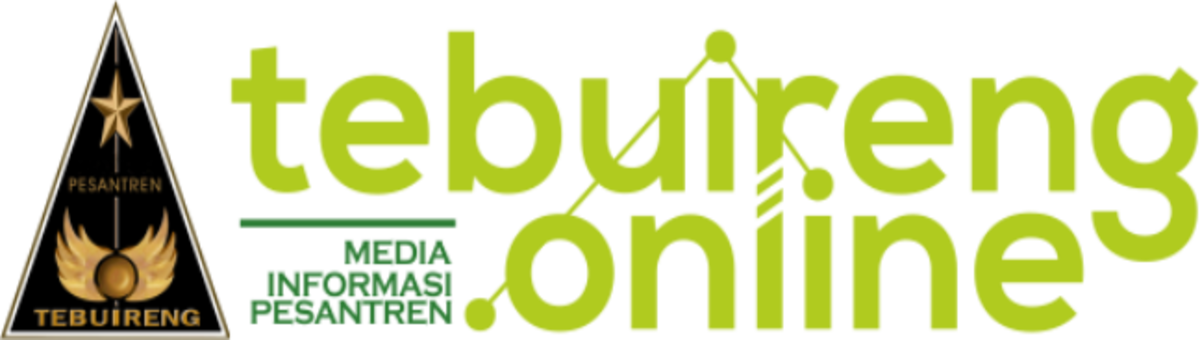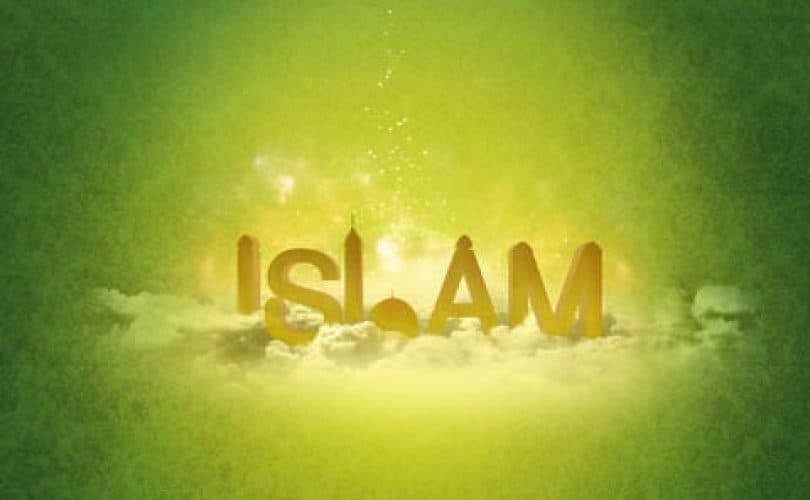
“La qoth’a fi ‘am al-muja’ah”, Tidak ada kewajiban potong tangan di tahun krisis bahan pangan.” Begitulah, secara eksplisit sang khalifah Umar bin Khathab mengatakan demikian, di kala memutuskan untuk tidak melaksanakan had potong tangan pada pelaku pencurian, yang mana pada saat itu masyarakat sedang megalami krisis pangan. Apakah keputusan beliau dapat dikatakan tepat?
Dengan prinsip mencegah kerusakan (mafsadah) dan menarik kerukunan umat, khalifah Umar bin Khathab lebih memperhatikan keberlangsungan hidup (hifdzh an-nafs) dibanding dengan menjaga harta kekayaan (hifdzh al-mal). Proses demikian secara metodelogi biasa dikenal dengan tahqiq al-manat, yang mana sang penggali hukum tidak merubah hukum sedikit pun, akan tetapi layak atau tidaknya suatu hukum itu dilaksanakan pada kasus tertentu (Ed: K. A Muntaha, 2024).
Sejak Nabi wafat, secara historis, hukum Islam mengalami banyak perubahan. Para sahabat banyak menghadapi beberapa persoalan yang belum ditemukan pada saat Nabi masih hidup, sehingga dalam memutuskan hukum mereka memakai cara yang berbeda dengan semasa Nabi masih hidup, Karena mereka dihadapkan dengan persoalan yang tidak pernah terjadi di masa Nabi. Namun demikian secara substansinya, semangat serta tujuannya tidaklah berbeda.
Para sahabat dalam memutuskan hukum yang berbeda dengan apa yang Nabi putuskan, tidaklah dapat dikatakan mereka keluar dari hukum tuhan, justru perubahan hukum yang mereka tetapkan tiada lain dengan tujuan untuk menegakkan hukum tuhan. Imam Ghazali mengomentari hal ini dalam kitab ihya ‘ulumiddin–nya: “ia bertindak berbeda dengan Nabi, karena ia tahu zaman sudah berubah” (Muhammad, 2020).
Penerapan Hukum Syariat Islam
Dalam buku Wajah Baru Fiqh Nusantara Fiqh Manhaji Sebagai Respon Solutif Isu-Isu Kebangsaan, (2024) disampaikan bahwa “para ulama telah menyatakan, bagi pemerintah yang ingin menerapkan hukum syari’at Islam haruslah mempertimbangkan tiga hal:
Pertama, persyaratan distatuskan wajib tidaknya suatu hukum. Kedua, sebab-sebab wajib atau tidaknya suatu hukum. Ketiga, penghalang yang dapat mencegah wajib atau tidaknya hukum tersebut dilaksanakan, atau biasa dikatakan dengan al-mani’.”
Jika kita mengingat sejarah dalam Piagam Jakarta, warga Indonesia bagian timur akan memisahkan diri jika poin pertama Piagam Jakarta disahkan. Mereka tidak setuju dengan salah satu keputusan yang tercantum di dalamnya yang berbunyi “menjalankan syari’at Islam bagi para pemeluknya”. Dengan keragaman bangsa Indonesia yang terdiri dari bebereapa ras, suku, dan agama, jika poin dari piagam jakarta tersebut direalisasikan maka akan terjadi kerusakan yang berupa disintegrasi sosial yang menjauhkan kerukunan bangsa Indonesia ini. Hal demikian merupakan penghalang (mani’) sendiri untuk menerapkan hukum syari’at Islam di Indonesia ini.
Dalam persoalan potong tangan yang dihadapi Umar bin Khathab sendiri, terdapat sebuah penghalang (mani’), yaitu masyarakat sedang mengalami krisis pangan. Dengan begitu, ambiguitas terjadi pada penentuan pencuri mana yang membutuhkan bahan pangan dan yang tidak membutuhkan, dan ambiguitas (syubhat) sendiri merupakan penghalang atas penetapan had potong tangan, sebagaimana hadist:
ادرءوا الحدود بالشبهات
Artinya: “Tolaklah hukum-hukum had dengan adanya syubhat”
Tak hanya itu, dalam literatur Islam sendiri, selain khalifah Umar bin Khathab, hal yang serupa juga pernah terjadi pada masa pimpinan khalifah Harun ar-Rasyid dan khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dapat kita lacak di dalam kitab i’anatu ath-thalibin karya Abu Bakar Syatha ad-Dimyati, bahwa khalifah Harun ar-Rasyid pernah membatalkan hukuman qisas pada seseorang yang membunuh kafir dzimmy, dengan pertimbangan yang paling mendasar yaitu tiada lain menolak kerusakan. Karena jika qisas itu dilaksanakan maka terjadi kericuhan tersendiri dalam tubuh umat muslimin pada saat itu.
Sementara khalifah Umar bin Abdul Aziz menolak desakan dari putranya sendiri yang ingin menerapkan syari’at sepenuhnya, juga dengan pertimbangan yang sama. Beliau menolak dengan mengatakan: “jika memaksakan untuk menerapkan syari’at sepenuhnya, umat akan serentak menolaknya dan hal ini akan menimbulkan fitnah yang sangat besar” (Ed: K. A Muntaha, 2024).
Kelompok yang menginginkan Indonesia menerapkan hukum syariat Islam dan menolak demokrasi, serta berkampanye sistem pemerintahan khilafah, akan membuka gerbang disintegrasi sosial yang menjauhkan kerukunan umat. Hal demikian juga merupakan pembekuan pemikiran islam yang bersifat sholih li kulli zaman wal-makan.
A. Helmy Faizal Zaini dalam bukunya Nasionalisme Kaum Sarungan (2018), dengan meminjam istilah Lawrence J. Peter, bahwa kebijakan pemerintah yang tidak mendatangkan kemashlahatan haruslah dikaji ulang, dan jika memang terbukti tidak mendatangkan kemashlahatan malah justru mendatangkan kemadhorotan dan keburukan, maka ia harus ditolak dan itu termasuk dalam istilah polusi birokrasi. Pendeknya tidak diterapkannya syari’at Islam sepenuhnya di Indonesia ini, tiada lain untuk menahan arus keamdhorotan dan keburukan yang terjadi di Indonesia.
Indonesia menerapkan hukum di atas konstitusi yang sebagiannya diadopsi dari syari’at Islam walaupun tidak seluruhnya. Alhasil, sistem pemerintahan Indonesia maupun sistem yang dipilih oleh para khalifah setelah Nabi Muhammad wafat, memiliki kesamaan prinsip yang berupa “Menolak kerusakan dan menarik kemashlahatan”. Sehingga dapat kita ketahui Indonesia dengan kemampuan pemerintahnya dalam melaksankan syari’at Islam walaupun tidak sepenuhnya, syari’at Islam tetap ditegakkan sesuai dengan batas kemampuan dan tuntutan kemashlahatan. Sekian, wallahu a’lam.
Baca Juga: KH. Salahuddin Wahid: Semangat Memadukan Keislaman dan Keindonesiaan
Penulis: Muhammad Asyrofudin