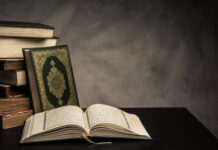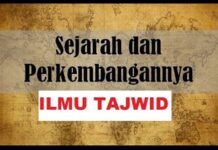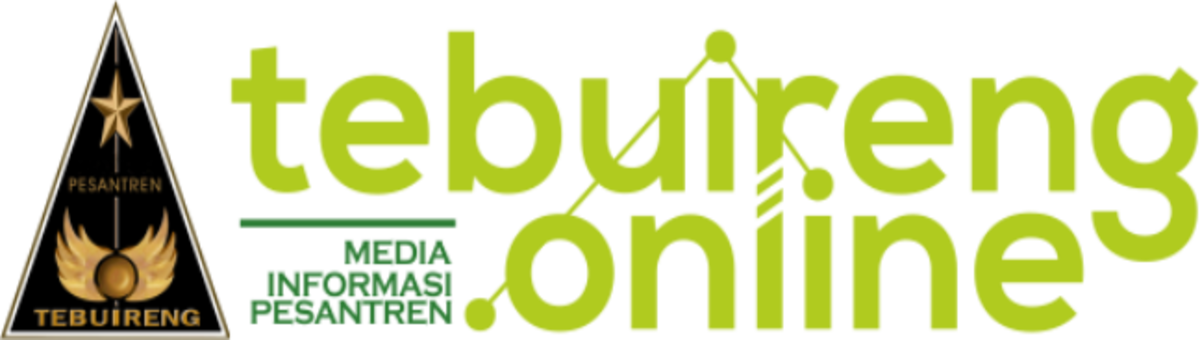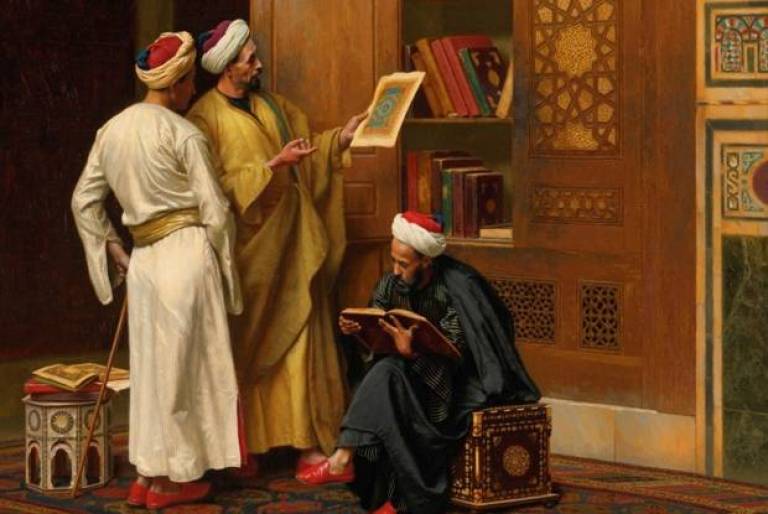
Dalam pembahasan dalil pada ilmu ushul, terdapat salah satu pembahasan tentang pertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lain yang disebut dengan ta’arudl. Memang suatu hal yang tak terhindarkan bahwa kadang anara nash satu dengan yang lainnya saling bertolak belakang. Tapi, bagaimana mungkin suatu hukum dapat dimunculkan, namun nashnya mengalami kontradiksi dengan nash yang lain?
Oleh karena itu, kali ini kita akan membahas bagaimana sikap seorang ulama ketika melihat suatu dalil mengalami kontradiksi dengan dalil yang lain. Namun tetap harus digarisbawahi bahwa esensi suatu nash tidak pernah bertentangan dengan dengan nash yang lain. Lantas, dari manakah suatu nash dapat ber-ta’arudl?
Memahami Konteks Ta’arudl
Suatu dalil dapat bertentangan dengan dalil lain berdasarkan pendapat seorang mujtahid yang layaknya manusia lain, bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang terbatas terhadap suatu nash. Dari sini jelas bahwa kontradiksi yang terjadi hanya pada makna tersirat dari suatu nash. Dan pada nash lain, ketika nash tersebut tidak dapat di-jam’u, naskh, ataupun tarjih maka nash tersebut tidak mungkin mengalami ta’arudl.
Andai suatu nash yang bertolak belakang dengan nash lain tetap dibiarkan tanpa ada suatu sikap yang diambil, niscaya akan menimbulkan kesulitan kepada umat Islam. Sedangkan suatu hukum tidak disyariatkan kecuali untuk menciptakan suatu kemaslahatan dan menghindari suatu kerusakan. Saat masih ada ta’arudl yang belum disikapi untuk jalan keluarnya, maka tujuan dari suatu hukum di atas tidak akan pernah ada.[1]
Untuk pembahasan ta’arudl kali ini, kita akan membahas kontradiksi pada suatu nash berdasarkan penjelasan kitab waraqat dan syarah-nya karya Imam Haramain dan Imam Mahalli. Dalam kitab waraqat kita hanya akan membahas empat bentuk ta’arudl yang ada dalam al-Quran dan hadis:
Pertama, kontradiksi antara dua dalil yang sama-sama bersifat umum. Kedua, kontradiksi antara dua dalil yang sama-sama bersifat khusus. Ketiga, kontradiksi antara dua dalil yang bersifat umum dan khusus. Keempat, kontradiksi antara dua dalil yang sama-sama bersifat umum dan khusus dari setiap sisi.
Tapi, sebelum kita membahas sikap para ulama untuk menanggapi bentuk-bentuk ta’arudl, kita pahami dahulu pengertian dari ta’arudl itu sendiri. Secara bahasa ta’arudl bermakna saling berhadap-hadapan dan saling mencegah. Sedangkan secara istilah ta’arudl adalah dua dalil yang saling bertolak belakang, saling berhadapan, atau bertemu. Seperti salah satu dalil memperbolehkan, sadangkan dalil lain melarang maka keduanya saling berhadapan dan bertolak belakang.
Namun, di antara hal lain yang harus digarisbawahi pada pembahasan ta’arudl kali ini yaitu, dalil yang bertolak belakang adalah dalil yang bersifat dhanni bukan qath’i. Karena dalil qath’i akan langsung memberikan pengetahuan dan amal. Andai kata, dalil qath’i mengalami kontradiksi maka akan terjadi hukum yang saling membatalkan satu sama lain pada syariat yang seharusnya tidak terjadi. Berbeda halnya saat terjadi naskh atau takhshis pada dalil qath’i tersebut. Dan kontradiksi pun tidak terjadi antara dalil dhanni dan dalil qath’i¸ kecuali terjadi takhshis.[2]
Menyikapi Ta’arudl di Dalam Nash
Selanjutnya, kita akan mulai membahas tentang jalan keluar pada dalil-dalil yang saling bertentangan. Kita bahas dari dua dalil yang umum ketika saling bertolak belakang. Dalam kondisi ini, setidaknya ada tiga sikap yang diambil para ulama untuk memunculkan suatu hukum. Sikap pertama adalah jam’u, yaitu menempatkan kedua dalil yang bertentangan sesuai konteksnya masing-masing.
Salah satu contoh adalah dalam permasalahan saksi yang baik dan buruk. Dalam hadis yang muttafaq, Nabi menjelaskan bahwa saksi yang buruk adalah saksi memberikan persaksian sebelum diminta.[3] Berbeda degan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam hadis tersebut Nabi memberikan pernyataan bahwa saksi yang memberikan persaksiannya sebelum diminta adalah saksi yang baik.[4] Kemudian, ulama menyikapi kedua hadis di atas yang saling berkontradiksi dengan cara menempatkan kedua hadis itu pada konteksnya. Untuk hadis mengenai saksi yang buruk, kita tempatkan ketika seorang pendakwa mengetahui persaksian dari saksi tersebut. Sedangkan untuk saksi yang baik, kita kontekskan pada saat saksi itu memberikan persaksiannya kepada pendakwa yang tidak tahu tentang kesaksiannya.
Kemudian, sikap kedua yang diambil ulama pada bentuk kontradiksi yang pertama ini adalah tarjih. Ini dilakukan ketika suatu dalil yang bertolak belakang dengan dalil lain tidak dapat dikontekskan sesuai tempatnya, serta tidak dapat dilakukan naskh antar dua dalil tersebut dikarenakan tidak diketahuinya waktu kemunculan dalil-dalil tersebut.
Di antara contoh dalam hal ini adalah ayat mengenai kepemilikan dua budak perempuan bersaudara. Pada surat Al-Mukminun ayat 6, seorang majikan diperbolehkan memiliki budak perempuan bersaudara.[5] Akan tetapi, dalam surat An-Nisa’ ayat 23, untuk memiliki dua budak perempuan bersaudara itu dilarang.[6] Dalam kasus ini, tidak dapat dilakukan jam’u atau naskh. Karena hal tersebut, dilakukanlah tarjih dengan mengambil hukum yang lebih pasti, yakni tidak ada kebolehan untuk memiliki dua budak perempuan bersaudara. Seandainya kita ambil hukum boleh dalam memiliki dua budak perempuan bersaudara, maka ada kemungkinan bahwa apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang seharusnya tidak diperbolehkan. Maka, diambillah keputusan yang paling aman, yakni tidak diperbolehkan untuk memiliki dua budak perempuan bersaudara. Andai hukum seharusnya dalam memiliki dua budak perempuan bersaudara adalah boleh, setidaknya kita tidak melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan.[7]
Lalu, metode ketiga yang dilakukan ulama selanjutnya dalam menyelesaikan kontradiksi dua dalil yang bersifat umum adalah nash. Seperti ayat tentang masa‘iddah seorang wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya. Untuk perempuan yang telah ditinggal wafat suamianya diharuskan melakukan ‘iddah selama satu tahun berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 240.[8] Akan tetapi, dalam surat Al-Baqarah ayat 234 menunjukkan bahwa masa‘iddah hanya tiga bulan sepuluh hari atau seratus hari dalam hitungan hijriah.[9] Maka, pada dua ayat ini ayat pertama telah dihapus hukumnya dengan ayat yang kedua. Seharusnya masa ‘iddah seorang perempuan yang telah ditinggal wafat oleh suaminya adalah satu tahun, dihapus dengan masa yang baru yaitu seratus hari.
Juga merupakan hal yang sama ketika di antara dua dalil khusus ini bertentangan, jika memungkin kan untuk dijadikan satu untuk mencari kesimpulan yang lain, maka diperbolehkan untuk mengumpulkannya.
Seperti hadis yang sudah masyhur dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim dan kitab hadis yang lain, bahwasannya Rasulullah ketika berwudlu’ dan membasuh kedua kakinya[10]. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam An–nisa’i dan Imam Al-Baihaqi yang menyatakan bahwasannya Rasulullah ini berwudlu’ dan mencipratkan air ke kedua telapak kakinya yang sedang memakai sandal[11]. Maka di antara dua dalil tersebut bisa disimpulkan bahwasannya Nabi melakukan mencipratkan air itu karena beliau wudlu’ dalam keadaan tidak berhadast atau untuk memperbaruhi wudlu’. Seperti dalam sebagian metodologi untuk pengambilan hukum bahwasannya mencipratkan air pada telapak kaki dan sandal itu dilakukan dalam keadaan tidak berhadas.
Mauquf di Antara Dua Dalil
Lalu bagaimana kalau ternyata dua dalil yang bertantangan ini tidak dapat untuk dijadikan satu dan tidak diketahui sejarah yang ada pada dalil tersebut? Maka sikap kita di-mauquf-kan dahulu sampai di antara keduanya ini memunculkan kejelasan.
Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang menceritakan ketika ada seseorang yang datang kepada Nabi lalu dia bertanya, ‘Wahai Rasulullah, apa saja yang diperbolehkan bagi seorang suami terhadap istri yang sedang haid? Maka Rasulullah menjawab, apapun yang berada di atas sarung[12]. Di hadis lain, riwayat Imam Muslim berisi bahwa datang lagi seorang yang berbeda dengan sebelumnya tapi memiliki pertanyaan yang sama, tetapi nabi memberikan jawaban yang berbeda yaitu, lakukan sesukamu kecuali jima’[13].
Maka sebenarnya dari dua hadis di atas ini sudah menandakan bahwasannya keduanya ini bertentangan. Tapi yang diunggulkan adalah yang ada pada hadis pertama yakni diharamkan dengan alasan untuk berhali-hati, dan sebagian ulama’ yang lain menghalalkan dengan alasan mengikuti hukum asal dari pernikahan itu sendiri yaitu halal. Ketika memang diketahuai kapan dalil itu turun, maka dalil yang turun lebih dahulu ini di-nashakh dengan dalil yang turun lebih akhir seperti dalam pembahasan ziaroh kubur.
Jika terdapat dua dalil, yang satu umum dan yang lain khusus, maka dalil yang umum dikhususkan dengan dalil yang khusus, seperti pengkhususan dalil pada kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim, yakni jika ada perkebunan yang disiram dengan air hujan maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1/10[14]. Dalil tersebut dikhususkan dengan dalil pada kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim juga yakni, tidak ada kewajiban shodaqah pada perkebunan yang kurang dari 5 wasaq[15]. Maka dalil yang pertama menjadi khusus dikarenakan hadis yang kedua menjelaskan wajib zakat biji bijian ketika sudah lebih dari 5 wasaq, karna dalil yang pertama tidak menjelaskan nominalnya.
Ketika terdapat dalil yang umum di satu sisi dan khusus di sisi yang lain, maka dalil yang umum dikhususkan dengan dalil khusus yang lain jika memungkinkan, seperti contoh pada hadis Abu Daud dan selainnya, bahwasannya air yang mencapai dua qulah tidak bisa najis[16]. Juga pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majjah, yang berisi bahwasannya air tidak akan bisa najis kecuali telah berubah warna, bau, dan rasanya[17]. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalil yang yang pertama terdapat keumuman dalam segi berubahnya air, dan khusus dalam ukuranya. Lalu dalam dalil yang kedua bersifat khusus dalam perihal perubahannya, dan bersifat umum dalam ukurannya. Maka keumuman dari dalil yang pertama dikhususkan dengan dalil yang kedua, hingga memunculkan hukum baru yakni air yang mencapai dua qullah bisa menjadi najis jika berubah rasa, bau, dan warnanya, dan pada dalil yang kedua dikhususkan dengan dalil yang pertama, dan memunculkan hukum air yang kurang dari dua qulah, ketika kemasukan najis maka menjadi najis meskipun tidak berubah rasa, bau dan warnanya.
Ketika kedua dalil ini tidak memungkinkan untuk saling mengkhususkan, maka di antara keduanya masih harus di-tarjih terlebih dahulu. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yang berisi tentang kita harus membunuh orang yang keluar dari Islam[18]. Hadis dari Imam Bukhori dan Imam Muslim yang berisi yaitu Rasulullah melarang untuk membunuh Wanita[19]. Pada dalil yang pertama ini diketahui bahwasannya di situ ada keumuman dalam segi laki-laki atau Perempuan yang harus dibunuh dan ketika keluar dari Islam atau murtad ini menjadi kekhususan dalil tersebut. Untuk dalil yang kedua, itu mengkhususkan perempuan, lalu dalil ini bersifat umum, entah nanti kafir harbi atau orang yang murtad. Maka dua dalil ini tidak bisa saling men-takhsis dikarenakan akan menjadi rancau,d an akan memunculkan hukum yang salah seperti pada dalil yang pertama yang dikhususkan dengan dalil yang kedua maka kita diperbolehkan membunuh orang murtad asalkan dia berjenis kelamin laki-laki (dilarang membunuh perempuan), lantas pada dalil yang kedua jika dikhususkan dengan dalil yang pertama kita akan diperbolehkan untuk membunuh perempuan.[20]
Baca Juga: Konsep Kaidah Amr dalam Ushul Fiqih beserta Contohnya
[1] Syarhul waraqat li Syaikh ‘Abdillah Bin Shalih Al-Fauzan
[2] Syarhul waraqat li Syaikh ‘Abdillah Bin Shalih Al-Fauzan dan Hasyiah an-nafahat li Syaikh Ahmad Bin ‘Abdillathif Al-Khathib Al-Jawi
[3] «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا» رواه مسلم
[4] «خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» – قَالَ عِمْرَانُ: لَا أَدْرِي أَذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً – قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلَا يَفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ» متفق عليه
[5] اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَۚ
[6] وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا…
[7] Hasyiah an-nafahat li Syaikh Ahmad Bin ‘Abdillathif Al-Khathib Al-Jawi
[8] وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًاۖ وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ۚ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ
[9] وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ
[10] أنه ﷺ توضأ وغسل رجليه
[11] أنه ﷺ توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين
[12] أنه ﷺ سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال: ما فوق الإزار
[13] أنه ﷺ * قال (اصنعوا كل شيء إلا النكاح)
[14] (فيما سقت السماء العشر)
[15] (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)
[16] إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس
[17] الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه
[18] (أنه ﷺ نهى عن قتل النساء)
[19] (وذهب شرذمة من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه لا يتناول الإناث)
[20]حاشية النفحات على شرح الورقات
Penulis: Hasan Marzuqi Mu’thi