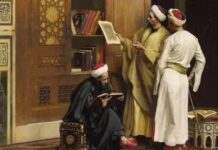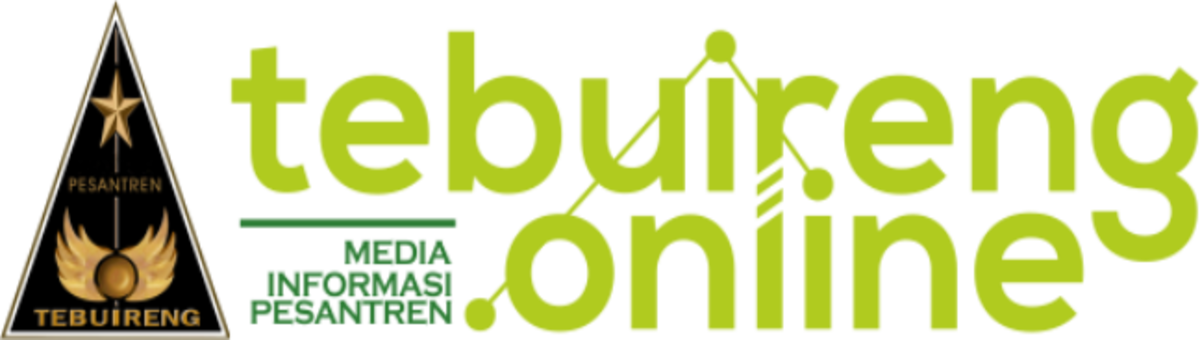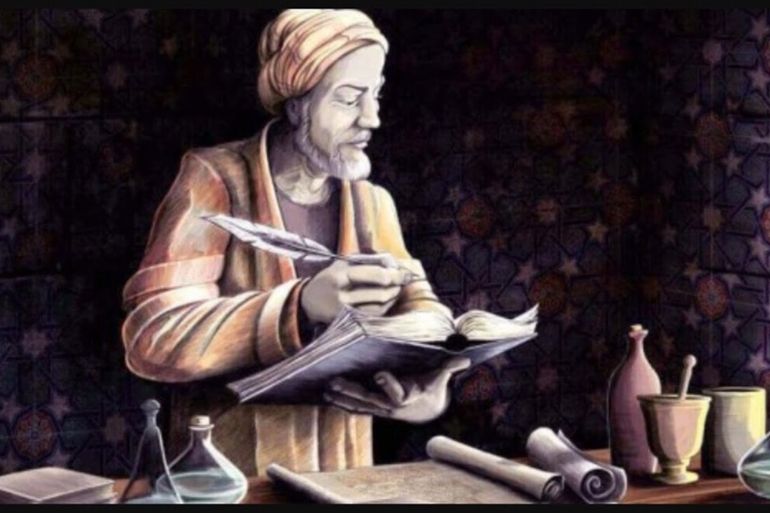
Sejarah pendidikan dan peradaban Islam menunjukkan bahwa tradisi literasi senantiasa memainkan peran sentral dalam membentuk arah perkembangan masyarakat. Para tokoh Islam memberikan teladan bahwa aktivitas dakwah tidak hanya dilakukan melalui lisan (bil qaul) melainkan juga melalui tulisan (bil qolam) yang keduanya memiliki kekuatan dalam menyebarkan ajaran Islam. Ragam karya ilmiah para ulama dan intelektual muslim menjadi bukti nyata bahwa budaya literasi berkembang pesat dan menjadi fondasi penting dalam sistem pendidikan dan kebudayaan Islam. Bahkan sejak masa Rasulullah SAW, antara tahun 611–632 M atau 12 SH–11 H, praktik literasi telah dikenal dan diaplikasikan secara aktif.
Tradisi ini kemudian diteruskan oleh para sahabat Nabi selama masa Khulafa al-Rasyidin (632–661 M / 12–41 H), yang melanjutkan pengembangan literasi dan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari misi keislaman. Perkembangan literasi semakin signifikan pada masa Dinasti Umayyah (661–750 M / 41–132 H), ketika masjid tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah, tetapi juga dikembangkan menjadi pusat kegiatan ilmiah yang menyerupai perguruan tinggi. Konsep masjid sebagai lembaga keilmuan ini menunjukkan komitmen masyarakat Islam terhadap pendidikan yang terstruktur dan berkelanjutan.
Dengan adanya penekanan terhadap fungsi ilmiah masjid, berbagai disiplin ilmu mulai diajarkan di lingkungan tersebut, meliputi puisi (syair), sastra, kisah-kisah historis bangsa terdahulu, serta ilmu kalam (teologi). Metode pengajaran yang digunakan pun menunjukkan dinamika intelektual yang tinggi, salah satunya dengan mengadopsi teknik debat sebagai sarana pengembangan pemikiran kritis. Semua ini menegaskan bahwa tradisi literasi dalam Islam bukan sekadar aktivitas membaca dan menulis, tetapi merupakan bagian integral dari proses transformasi intelektual dan spiritual umat.[1]
Menulis merupakan salah satu sarana utama bagi manusia untuk mengekspresikan pemikirannya. Karakter seseorang tak hanya tampak dari cara ia berbicara tetapi juga dari bagaimana ia merangkai kata dalam tulisan. Bahkan menulis membawa manfaat yang lebih mendalam dibandingkan sekadar membiasakan diri berbicara. Sebuah karya tulis yang bermutu tak hanya bisa dinikmati oleh orang-orang sezaman tetapi juga dapat menjembatani pemikiran penulis kepada generasi setelahnya bahkan setelah ia tiada. Para ulama misalnya mampu menyampaikan gagasan-gagasan besar mereka melalui tulisan yang tidak hanya menginspirasi tetapi juga mampu menggerakkan orang lain untuk bertindak tanpa harus berkomunikasi langsung. Inilah mengapa menulis menjadi media penyampaian yang sangat efektif. Dalam perspektif sejarah, kata-kata dalam tulisan mampu merekam dan menjelaskan peristiwa yang terjadi pada masa lalu secara lebih utuh. Meskipun peninggalan peradaban sering hadir dalam bentuk benda atau warisan budaya pemahaman yang lebih mendalam kerap hadir melalui teks. Seperti halnya para intelektual muslim di Indonesia untuk mengenal pikiran dan jati diri mereka, bacalah karya-karya tulis mereka.[2]
Di masa lalu kebiasaan menulis telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan para ulama dalam berbagai bidang keilmuan Islam. Ribuan karya yang mereka hasilkan melalui tradisi ini telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Islam sendiri sangat menekankan pentingnya ilmu sebagaimana terlihat dari wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan untuk membaca. Dari perintah inilah tradisi menulis pun tumbuh. Selain itu menulis juga dianggap sebagai amal yang bernilai tinggi karena ilmu yang dituliskan dapat diwariskan dan memberikan manfaat bagi generasi-generasi setelahnya.[3]
Dalam ranah dunia Islam, kita mengenal tokoh besar Al-Ghazali yang memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Ia lahir di kota Thus, salah satu wilayah di Khurasan (sekarang bagian dari Persia), pada pertengahan abad ke-5 Hijriyah (sekitar tahun 450 H/1058 M). Al-Ghazali dikenal sebagai salah satu pemikir besar dalam Islam dan mendapatkan gelar Hujjatul Islam (argumen kebenaran Islam) serta Zain ad-Din (hiasan agama).[4]
Sebagai salah satu ulama paling terkemuka dalam sejarah Islam Al-Ghazali tidak hanya dikenal sebagai sosok cendekiawan yang mumpuni dalam berbagai bidang keilmuan tetapi juga sebagai figur sentral dalam pengembangan dan pematangan ajaran tasawuf di mana ia berhasil menggabungkan kedalaman spiritual dengan ketajaman intelektual. Hal ini tercermin dari beragam karyanya yang meliputi berbagai disiplin ilmu, mulai dari filsafat, teologi, hingga etika dan tasawuf, dengan mahakaryanya yang paling monumental yaitu Ihya’ Ulumuddin, yang hingga saat ini tetap menjadi rujukan utama dalam kajian keislaman serta dianggap sebagai warisan pemikiran yang terus relevan dan hidup di kalangan umat Islam lintas zaman dan generasi.
Di kawasan Nusantara sendiri terdapat banyak ulama besar yang telah menghasilkan karya-karya luar biasa dan masih terus dipelajari hingga hari ini. Salah satu tokoh penting di antaranya adalah Syekh Nawawi al-Bantani, seorang ulama besar yang memiliki nama lengkap Abu Abdul Mu’thi Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi al-Jawi al-Bantani. Beliau lahir di Kampung Tanara yang terletak di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten, wilayah yang dahulu masuk dalam bagian Jawa Barat pada tahun 1230 Hijriyah atau sekitar 1813 Masehi. Syekh Nawawi dikenal sebagai seorang ulama yang sangat produktif dalam menulis dan meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai jumlah pasti karyanya ada yang menyebutkan sebanyak 99 karya sementara pendapat lain menyatakan jumlahnya mencapai 115 buah tidak dapat disangkal bahwa beliau memberikan kontribusi besar dalam khazanah keilmuan Islam terutama dalam bidang akhlak dan tasawuf yang hingga kini tetap dijadikan rujukan oleh para pelajar dan pencari ilmu.[5]
Dalam hadis nabi yang diriwayatkan oleh Abu Darda’ dikatakan;
عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُوزَنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ وَدَمُ الشُّهَدَاءِ»
Artinya: Dari Abu al-Darda’a, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Darah para ulama dan darah para syuhada akan ditimbang pada hari kiamat.”
Kalimat ini mengisyaratkan bahwa kontribusi intelektual dan perjuangan ilmiah yang dilakukan para ulama memiliki nilai yang sebanding dengan pengorbanan nyawa para syuhada yang gugur di medan perang demi membela agama. Ungkapan tersebut mengandung makna mendalam tentang pentingnya ilmu dalam Islam sekaligus menunjukkan bahwa jihad intelektual dalam bentuk pencarian, pengajaran, dan pengamalan ilmu diakui sebagai bentuk perjuangan yang agung. Islam tidak hanya memuliakan orang-orang yang berjuang secara fisik untuk menegakkan kebenaran tetapi juga menghargai mereka yang mendedikasikan hidupnya dalam medan dakwah dan pendidikan. Penimbangan darah para ulama dan syuhada kelak di hari kiamat adalah simbol dari penilaian yang adil terhadap segala bentuk pengorbanan demi kemuliaan Islam. Alhasil pernyataan tersebut bukan sekadar retorika religius saja melainkan sebuah bentuk pengakuan terhadap dimensi spiritual dan sosial dari peran ulama dalam masyarakat Islam.
Dengan menulis juga akan menjaga ilmu tidak akan hilang sebagaimana sabda rarulullah
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ” قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ
Artinya: Dari Abdullah bin Amr ia berkata, “Rasulullah -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- bersabda, ” Ikatlah ilmu dengan dengan menulisnya”.
Hadis ini menegaskan pentingnya menulis sebagai sarana untuk menjaga, mengembangkan, dan mewariskan ilmu pengetahuan. artinya menulis bukan hanya tindakan personal untuk mengikat ilmu saja tetapi juga bentuk kontribusi intelektual kepada masyarakat luas dan generasi yang akan datang. karenanya menulis juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses keilmuan dan merupakan upaya konkret dalam memastikan bahwa pengetahuan tetap hidup, terjaga, dan bermanfaat sepanjang zaman.
Imam syafi’I juga memaparkan dalam syair diwannya:
الْعِلْمُ صَيْدٌ وَالْكِتَابَةُ قَيْدُهُ قَيِّدْ صُيُوْدَكَ بِالْحِبَالِ الْوَاثِقَهْ . فَمِنَ الْحَمَاقَةِ أَنْ تَصِيْدَ غَزَالَةً وَتَتْرُكَهَا بَيْنَ الْخَلاَئِقِ طَالِقَهْ
“Ilmu adalah buruan dan tulisan adalah ikatannya, Ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Termasuk kebodohan kalau engkau memburu kijang, Setelah itu kamu tinggalkan terlepas begitu saja.”
Bagi para pencari ilmu dan kalangan akademisi, menulis bukan sekadar aktivitas melainkan sebuah seni dalam mengasah nalar dan menyalurkan gagasan serta kreativitas. Melalui tulisan, ide dan pemikiran tidak hanya tersampaikan tetapi juga diabadikan melampaui batas usia penulisnya. Maka tidak mengherankan jika muncul ungkapan bijak bahwa sejarah adalah milik mereka yang menulis. Para ulama terdahulu juga telah memberikan teladan agung bahwa melalui tulisan nama mereka tetap harum dan dikenang sepanjang zaman. Dalam khazanah keilmuan kita sering mendengar pepatah: “Jika engkau ingin menjelajahi dunia, maka bacalah. Namun jika ingin abadi, maka menulislah.” Menulis adalah warisan luhur yang telah ditanamkan oleh para ulama dan menjadi bagian penting dari tradisi keilmuan Islam yang patut terus dilestarikan.
Kesimpulan
Di era digital sekarang menulis telah menjadi aktivitas yang semakin mudah, cepat, dan dapat dilakukan oleh siapa saja di era komputer dan internet saat ini. Dengan hadirnya teknologi digital siapa pun kini dapat menuangkan ide ke dalam bentuk tulisan melalui perangkat elektronik seperti ponsel, laptop, atau tablet, bahkan hanya dengan koneksi internet. Ini berbeda dengan masa lalu ketika menulis membutuhkan alat tulis fisik dan proses penyebaran yang terbatas. Aplikasi penulisan cloud, media sosial, dan blog memungkinkan setiap orang untuk menyimpan, membagikan, dan mempublikasikan tulisannya secara instan di seluruh dunia. Kemudahan ini tidak hanya mempengaruhi proses penulisan secara teknis tetapi juga membuka pintu ke dunia literasi dan komunikasi yang lebih luas.
Baca Juga: 3 Manfaat Menulis yang Jarang Orang Ketahui
[1] Kambali Zutas, “Literacy Tradition in Islamic Education in Colonial Period,” Al-Hayat: Journal of Islamic Education 1, no. 1 (2017): 16–31.
[2] Rasyid Anwar Dalimuthe, Masruroh Lubis, and Ruslan Efendi, “Melacak Tradisi Menulis Ulama Indonesia Abad Ke-19-21 (KH. Hasyim Asy’ari Dan Ramli Abdul Wahid),” Al-Fikru: Jurnal Ilmiah 16, no. 1 (2022): 148–62.
[3] Bahrul Ulum, “Tradisi Menulis Ulama Indonesia (Abad 19-21),” WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 4, no. 2 (2019): 15–15.
[4] Ahmad Zaini, “Pemikiran Tasawuf Imam Al-Ghazali,” Esoterik: Jurnal Akhlak Dan Tasawuf 2, no. 1 (2016): 150.
[5] M. Azizzullah Ilyas, “Ajaran Syeikh Nawawi Al-Bantani Tentang Pendidikan Akhlak Anak,” AR-RIAYAH: Jurnal Pendidikan Dasar 2, no. 2 (2018): 113–26.
Penulis: Ahmad Firdaus Mahasantri M2 Mahad Aly Hasyim Asy’ari Tebuireng
Editor: Sutan Alam Budi