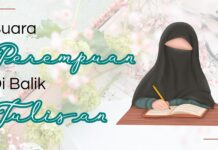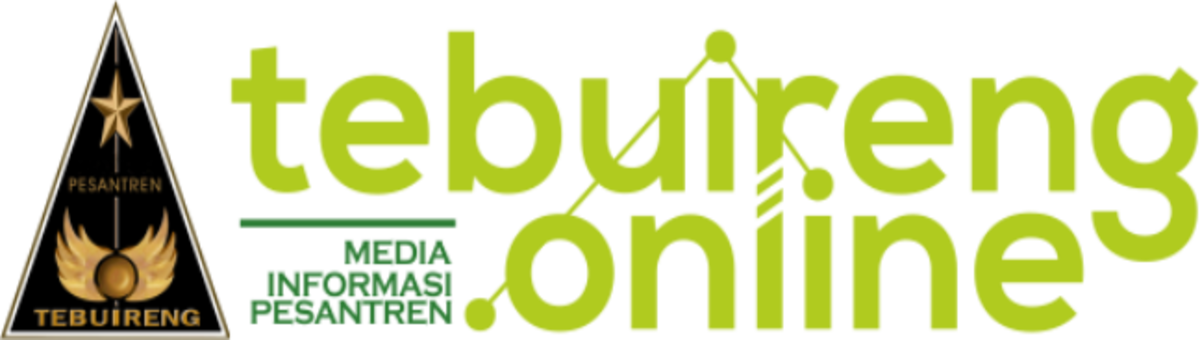Oleh: M. Rizki Syahrul Ramadhan*
Pembicaraan tentang awal mula pondok pesantren tidak akan pernah mencapai titik terang, sebab pondok pesantren telah setua Islam di Indonesia itu sendiri. Pelacakan secara ilmiah terhadap hal itu akan berujung pada banyak pilihan teori dan penyimpulan subjektif belaka. Namun, sejarah tidak hanya berisi awal mula, rekam jejak perkembangan juga termasuk darinya. Tentunya, perkembangan juga tidak kalah penting untuk dimuthola’ah.
Zamakhsyari Dhofier, seorang penulis buku indah berjudul Tradisi Pesantren, melalui hasil penelitian itu, menjadi terekam perkembangan pesantren sejak zaman Belanda hingga masanya, tahun 1978. Tanpa maksud plagiasi, baiknya dinarasikan ulang pembacaan yang berhasil penulis cerna dari Tradisi Pesantren.
Narasi Ulang Sejarah
Berangkat dari praduga bahwa bentuk yang mendasari bangunan pesantren adalah kelompok belajar dan tarekat, Islam berkembang secara gencar melalui fasilitas Kerajaan Demak. Sayangnya Belanda datang, Islam yang semerbak di perkotaan terdesak oleh resolusi pun ordonansi. Geserlah para kiai ke desa dan lahirlah pesantren sebagaimana kita kenal. Sebuah tempat yang dijadikan alternatif penyebaran Islam di Indonesia.
Dengan berpindah ke desa, taktik dakwah mengalami perubahan dari orientasi kuantitas ke orientasi kualitas. Maka dapat dimaklumi mengapa pesantren pada mulanya hanya fokus menggembleng segelintir kader. Seiring berjalannya waktu, peminat pesantren semakin meningkat. Belanda kelabakan dengan fenomena yang mungkin mengancam kekuasaannya, mengingat masyarakat muslim yang terorganisir dari pesantren sangat mungkin melakukan pemberontakan kepada Belanda yang notabene kafir.
Guna mereda resah, Belanda mendirikan sekolah ala Barat yang ditujukan bagi pribumi. Usaha tersebut sukses. Pribumi antusias menyikapi usaha “pencerdasan” Belanda. Sebagaimana lumrahnya proses sejarah ala Ibn Khaldun, di mana para pemain utama saling bergantian merebut puncak, pesantren pada gilirannya juga mencoba adaptatif terhadap perkembangan yang terjadi.
Tercatat dua perubahan penting dalam rangka itu. Pembukaan pesantren untuk santri putri pada tahun 1910 dan pengajaran ilmu umum dalam bentuk madrasah pada tahun 1920. Pesantren putri mula-mula diawali dari Pesantren Denanyar, dan madrasah diawali oleh (salah satunya) Pesantren Tebuireng. Dari perubahan yang disebut terakhir ini pesantren mengalami perubahan tradisi yang cukup signifikan dengan keuntungan dan kerugian tersendiri.
Dilema Madrasah
Masa awal pendirian madrasah dihadapkan pada dua problem mendasar, yaitu proporsionalitas kurikulum dan tenaga kerja profesional. Pesantren yang sejak awal mula pendirian diperuntukkan sebagai media dakwah sekaligus kaderisasi tertuntut untuk tetap ajeg menyuplai keilmuan Islam bagi para santri. Keilmuan umum yang dimuat di madrasah tidak boleh menghalangi misi utama. Akhirnya perpaduan pengajaran keilmuan Islam dan umum harus diatur sedemikian rupa agar proporsional.
Untuk meracik kurikulum tidak dibutuhkan begitu banyak tenaga, berbeda halnya dengan perealisasian kurikulum. Dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) harian, madrasah membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak, terutama tenaga pengajar keilmuan umum. Di awal abad 20, sumber daya manusia yang mumpuni dalam keilmuan umum nampaknya tidak banyak dimiliki pesantren. Ada, namun tidak banyak.
Dua tantangan di atas ternyata tidak tergerus waktu. Di abad 21 ini pesantren juga masih terus membenahi kurikulum dan tenaga kerja. Di Tebuireng, misalnya, unit pendidikan yang dahulu bernama madrasah telah berkembang sedemikian pesat. Para santri dikelompokkan ke dalam unit-unit sesuai minatnya. Tersebut SMA Trensains yang fokus pada sains, Madrasah Muallimin yang fokus pada turast, dan unit yang lain dengan fokusnya masing-masing. Akhirnya, tenaga kerja profesional juga harus didapatkan guna memaksimalkan KBM di masing-masing unit. Jika tenaga dari alumni pesantren kurang mumpuni, solusi yang sementara tergambar adalah memanfaatkan link kiai.
Perkembangan semacam itu nampaknya akan terus terjadi. Madrasah, yang telah berkembang menjadi berbagai unit, akan terus adaptatif terhadap kebutuhan. Pesantren terus mencetak santri yang beraneka ragam dengan tidak lupa, atau jangan sampai lupa, dengan tujuan awal, yaitu dakwah Islam dan pengaderan masyarakat muslim Indonesia.
Tradisi yang Menghilang
Sistem madrasah membuahkan hasil. Pesantren masih dapat bersaing dengan lembaga pendidikan Belanda. Melalui sistem ini, para kiai berhasil mengonsolidasi kedudukan pesantren dalam menghadapi perkembangan sekolah-sekolah Belanda. Tercatat pada tahun 1920 dan 1930, jumlah pesantren besar dan santrinya melonjak berlipat ganda. Di Pesantren Tebuireng sendiri, jumlah santri pada tahun 1920 adalah 200 orang, kemudian pada tahun 1930 menjadi 1500 orang santri.
Keberhasilan terlihat dalam hal persaingan peminat antara pesantren dan sekolah Belanda, yang terwujud dalam kuantitas peserta didik. Dalam keberhasilan seperti itu, madrasah sebenarnya juga meninggalkan bekas lain. Bekas yang sebagian orang menyayangkannya, yaitu hilangnya tradisi “santri kelana” dari pesantren.
Di masa lampau, seorang santri seperti Kiai Wahab Hasbullah akan berkelana dari satu pesantren ke pesantren lain untuk memuaskan kehausan akan pengetahuan tanpa peduli ijazah formal. Berawal dari Pesantren Tambakberas yang dipimpin oleh ayahnya, Kiai Wahab berkelana melanjutkan pelajarannya ke Pesantren Pelangitan, Pesantren Mojosari, dan banyak pesantren lain hingga ke Pesantren Tebuireng. Contoh lain adalah Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy’ari. Dalam hasil penelitian mahasantri Ma’had Aly Tebuireng, Septian Pribadi, tercatat pada tahun 1886 Hadratussyaikh mulai berkelana mencari ilmu. Di umur ke-15 itu, Hadratussyaikh tidak hanya berdiam diri di satu atau dua pesantren saja.
Dengan berkembangnya sistem madrasah sejak permulaan abad ke-20, salah satu ciri penting tradisi pesantren ini menghilang. Laku santri kelana yang dahulu lumrah dilakukan para kiai ketika menjadi santri harus dikorbankan demi sistem kelas yang bertingkat-tingkat dan ijazah formal. Sistem kelas dan ketergantungan kepada ijazah formal sebagai tanda keberhasilan pendidikan menyebabkan seorang santri harus tinggal dalam satu pesantren saja untuk waktu bertahun-tahun.
Melalui laku santri kelana, santri akan dapat mendalami empat atau lima kitab dasar dari guru yang berlainan sampai benar-benar menguasainya. Namun dengan madrasah, seorang santri hampir tidak mungkin mengulangi sebuah kitab dengan kiai yang lain setelah menyelesaikannya di suatu madrasah. Hilangnya tradisi santri kelana nampaknya memang merupakan konsekuensi logis ketika sistem madrasah dimunculkan.
Santri Tanpa Kelana
Manusia akan menjadi lemah jika terus beralasan dan menyalahkan keadaan. Hilangnya tradisi santri kelana tidak boleh menjadikan santri kehilangan gairah dalam meniti jalan para kiai terdahulu. Ijazah formal yang ditawarkan madrasah memang menjadi kebutuhan yang tidak sepele lagi di era ini. Tanpa ijazah, manufer langkah para santri ke depan akan sangat terbatas.
Sistem muaddalah dan legalitas perguruan tinggi pesantren yang bernama Ma’had Aly kiranya telah membuktikan bagaimana pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, telah mengupayakan santri-santri mendapat ijazah formal. Namun didapatkannya ijazah juga tidak boleh membuat seorang santri terlena. Idealisme dalam mencari ilmu harus tetap diupayakan oleh pribadi santri. Setelah kehilangan kesempatan berkelana, santri harus menembel kekurangan dengan upaya masing-masing.
Sistem pengajian sorogan dan bandongan, ditambah lagi dengan kelompok musyawarah adalah alternatif upaya tersebut. Ketiga model belajar ini harus diupayakan dengan inisiatif santri itu sendiri. Dengan sorogan ke berbagai guru, mengikuti bandongan di berbagai halaqah, dan bermusyawarah dalam kelompok-kelompok tertentu akan mematangkan keilmuan santri walalaupun tanpa berkelana. Jika belum juga puas, para santri dapat menerapkan laku santri kelana ketika liburan madrasah dengan cara mengikuti pengajian kilatan di pesantren tertentu.
Keinginan meniru para kiai terdahulu memang harus dimiliki para santri hari ini. Namun, ketika keadaan telah berkembang sedemikian rupa, aspek yang ditiru tidaklah harus berupa aktivitas fisik para kiai. Ketika laku santri kelana yang telah menghilang memang sulit ditiru, sila mencari aspek lain yang lebih esensial. Bahwa para kiai mencari ilmu guna meneguhkan visi dakwah Islam, memperjuangkan nilai-nilai keislaman, serta menjadi problem solver masyarakat, harus diingat dan dicitakan oleh para santri.
*Penulis adalah Mahasantri Ma’had Aly Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang.