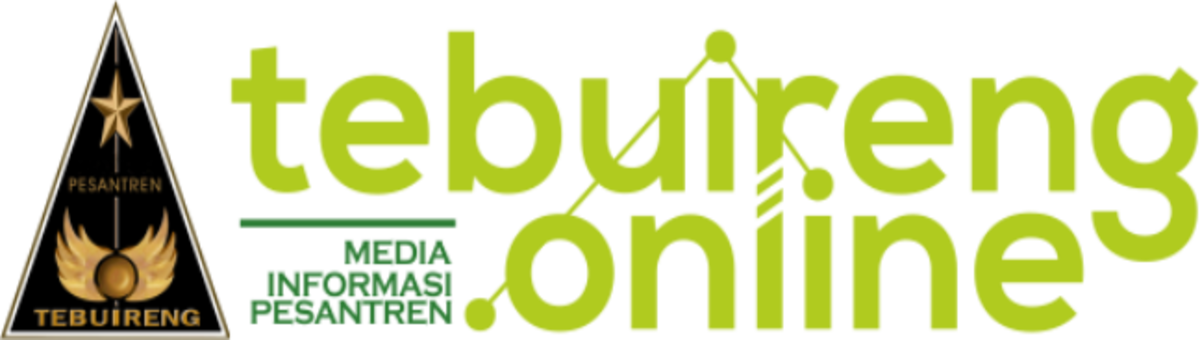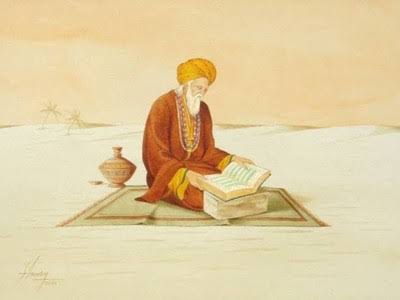
Tasawuf merupakan salah satu kekayaan intelektual umat Islam yang keberadaannya kini semakin dibutuhkan. Dari perspektif sejarah dan teologi, tasawuf berperan dalam membimbing serta mengarahkan perjalanan hidup manusia agar meraih keselamatan di dunia dan akhirat.[1] Tasawuf kerap kali mendapat stigma negatif, dianggap sebagai penghambat kemajuan dan identik dengan kemunduran.
Tasawuf juga dituduh menjauh dari realitas kehidupan dunia, membangun sikap stagnan, serta menumbuhkan apatisme yang dianggap sebagai penyebab kemunduran umat Islam. Banyak kalangan modernis yang memandang tasawuf atau tarekat sebagai lembaga kesufian dan kewalian yang tidak selaras dengan modernitas serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan oleh karakter tasawuf yang lebih menekankan pada makna batiniah dan pengalaman transendental.[2]
Akan tetapi pendekatan yang berbeda diterapkan oleh seorang sufi terkemuka bernama Abu Hasan Asy-Syadzili. Tidak semua sufi menjalani tasawuf dengan gaya hidup sederhana atau minimalis. Asy-Syadzili justru menerapkan konsep tasawuf high living (gaya hidup berstandar tinggi). Namun, gaya hidup seperti ini bukan bertujuan untuk memuaskan hawa nafsu atau sekadar mencari gengsi belaka, melainkan sebagai bentuk ekspresi rasa syukur yang tulus dan mendalam kepada Allah SWT. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Imam As-Syibli:[3]
قال الشبلي رحمه الله الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعمة
Artinya: As-Syibli Rahimahullah berkata, “Syukur adalah melihat Sang Pemberi nikmat, bukan melihat nikmat.
Mengenal Pemikiran Tasawuf Imam Al-Syadzili
Nama lengkapnya adalah Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar al-Syadzili. Ia dilahirkan di desa Ghamarah, yang terletak tidak jauh dari kota Saptah di kawasan Maghrib al-Aqsha atau Maroko, wilayah paling barat di Afrika Utara, pada tahun 593 H/1197 M. Maroko sendiri dikenal sebagai salah satu wilayah dunia Islam yang tetap mempertahankan semangat spiritual, bahkan hingga akhir abad ke-13 H/19 M.[4]
Tasawuf yang diajarkan oleh Asy-Syadzili ini sejalan dengan ajaran Imam al-Ghazali, yaitu tasawuf yang berlandaskan al-Qur’an dan hadits, serta berfokus pada asketisme, penyucian jiwa, dan pembinaan moral. Corak tasawuf ini bersifat moderat dengan konsep zuhud yang lebih seimbang. Menurut al-Syadzili, zuhud bukanlah menjauhi kehidupan dunia, melainkan membersihkan hati dari ketergantungan selain kepada Allah SWT.[5] Syekh Abdul Wahab As-Sya’rani dalam kitabnya Al-Minahus Saniyyah mengatakan;
وقد كان أبو الحسن الشاذلي يقول لأصحابه: كلوا من اطيب الطعام واشربوا من ألذ الشراب وناموا على اوطاء الفراش والبسوا الين الثياب فإن أحدكم إذا فعل ذلك وقال الحمد لله يستجيب كل عضو فيه للشكر
Artinya: Abu al-Hasan al-Syadzili berkata kepada para sahabatnya; “Makanlah makanan yang terbaik, minumlah minuman yang paling lezat, tidurlah di tempat tidur yang paling empuk dan kenakanlah pakaian yang paling halus, karena jika salah satu dari kalian melakukan hal ini dan mengucapkan syukur kepada Allah, maka seluruh organ tubuhnya akan merespons dengan ucapan syukur”.
Secara etimologi, istilah tasawuf memiliki berbagai makna yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya oleh Harun Nasution yang menjelaskan lima istilah yang berkaitan dengan tasawuf, yaitu Al-Suffah (sekelompok sahabat muhajirin dan anshar yang tinggal di serambi masjid), Shaff (barisan), Sufi (suci), Sophos (hikmah atau kebijaksanaan), dan Suf (kain wol).[6] Menurut pandangan para ahli, makna tasawuf akan sangat bergantung pada perspektif, pemahaman, dan pengalaman masing-masing tokoh. Secara umum, terdapat tiga sudut pandang yang digunakan untuk mendefinisikan tasawuf, yaitu manusia sebagai makhluk yang terbatas, manusia sebagai makhluk yang harus berjuang, dan manusia sebagai makhluk yang ber-Tuhan.[7]
Dari sosok Abu Hasan Asy-Syadzili ini melahirkan pemahaman bahwa tasawuf bukan lagi dipandang sebagai gaya hidup yang ketinggalan zaman, melainkan sebagai sebuah ajaran yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan dinamika kehidupan modern. Melalui tasawuf, seseorang dapat membangun rasa syukur yang mendalam, sehingga hati menjadi tenang dalam menjalani hidup dan beribadah. Hal ini senada dalam kitab Mausu’ah Fiqh al-Qulub karya Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri.[8]
وحقيقة الشكر: ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناءً واعترافاً .. وعلى قلبه شهوداً ومحبة، وعلى جوارحه انقياداً وطاعة.
Artinya: Hakikat rasa syukur adalah merasakan limpahan nikmat Allah yang tercermin melalui lisan dengan ungkapan pujian dan pengakuan, tertanam di hati sebagai kesaksian dan rasa cinta, serta diwujudkan melalui anggota tubuh dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan.
Bahwa Kesempurnaan syukur terletak pada kemampuan melihat nikmat sekaligus mengenali Sang Pemberi. Semakin dalam seseorang menyadari dan menyaksikan nikmat tersebut, semakin sempurna pula rasa syukurnya. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa menjalani hidup dengan selera tinggi (high living) diperbolehkan oleh Imam Abu Hasan Asy-Syadzili dan corak sufi seperti ini sangat logis dan mungkin bisa diterapkan oleh pengamal tasawuf modern. selaras dengan ajaran Rasulullah SAW tentang zuhud, yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar dalam kitab Sunan At-Tirmidz:[9]
عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا لَيْسَتْ بِتَحْرِيمِ الحَلَالِ وَلَا إِضَاعَةِ المَالِ وَلَكِنَّ الزَّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا أَنْ لَا تَكُونَ بِمَا فِي يَدَيْكَ أَوْثَقَ مِمَّا فِي يَدِ اللَّهِ وَأَنْ تَكُونَ فِي ثَوَابِ المُصِيبَةِ إِذَا أَنْتَ أُصِبْتَ بِهَا أَرْغَبَ فِيهَا لَوْ أَنَّهَا أُبْقِيَتْ لَكَ.
Artinya: Zuhud terhadap dunia bukanlah mengharamkan yang halal dan menyianyiakan harta, akan tetapi, zuhud terhadap dunia adalah engkau lebih percaya pada apa-apa yang ada di sisi Allah Swt daripada apa apa yang ada di tanganmu dan pahala musibah yang menimpamu membuatmu lebih suka seandainya ia terus menimpamu.
Hadis ini memberi pengertian bahwa hakikat zuhud bukanlah meninggalkan kenikmatan dunia secara keseluruhan, melainkan menjaga hati agar tidak terikat pada dunia serta selalu tetap bersyukur atas segala nikmat yang Allah SWT berikan. Zuhud sejati terletak pada ketenangan hati dan kesederhanaan jiwa, bukan pada meninggalkan harta, pekerjaan, atau usaha hingga menjadi beban bagi orang lain. Justru, seorang yang zuhud mampu memanfaatkan dunia sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan akhirat, bahkan meskipun menjalani hidup dengan standar yang tinggi (high living), selama hatinya tetap tertuju kepada Allah SWT.
Baca Juga: Peranan Tasawuf dan Tarekat dalam Problem Sosial Masyarakat
[1] Nur Azizah and Miftakhul Jannah, “Spiritualitas Masyarakat Modern Dalam Tasawuf Buya Hamka,” Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy 3, no. 1 (2022): 85–108.
[2] Fadhilah Irsyad, “Pemikiran Sufistik Abu Said Al-Baji Dan Abu Hasan Asy-Syadzili: Lahirnya Madrasah Syadziliyah Di Tunisia,” Tanwir: Journal of Islamic Civilization 1, no. 1 (2024): 44–63.
[3] Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Ihya’ Ulum Ad-Din (Dar Al-Ma’rifah – Beirut, n.d.).
[4] “Distingsi Dan Diaspora Tasawuf Abû Al-Ḥasan al-Shâdhilî | Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam,” accessed March 16, 2025, https://jurnalfuf.uinsa.ac.id/index.php/teosofi/article/view/13.
[5] Mihmidaty Yaâ, “PEMIKIRAN DAN MATERI PENDIDIKAN TASAWUF DALAM PERSPEKTIF IMAM ABU HASAN ALI AL-SYADZILI,” Urwatul Wutsqo 4, no. 1 (2015), https://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/wutsqa/article/view/1018.
[6] Nasution Harun, “Falsafat dan Mistisisme dalam Islam / Harun Nasution” (jakarta: Bulan Bintang, 1983.).
[7] “Akhlak Tasawuf – Abuddin Nata,” Rajagrafindo Persada (blog), accessed March 16, 2025, https://www.rajagrafindo.co.id/produk/akhlak-tasawuf/.
[8] Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, Mausu’ah Fiqh Al-Qulub (Bayt Al-Afkar Ad-Dawliyyah, n.d.).
[9] Muhammad bin ’Isa At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi (Syarikah Maktabah wa Mathba’ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi – Mesir, n.d.).
Penulis: Ahmad Firdaus, Mahasantri M2 Mahad Aly Tebuireng