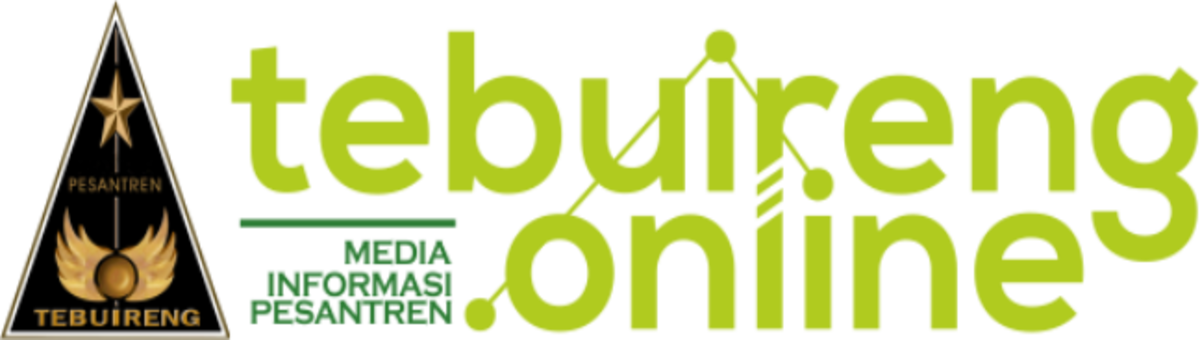Sebagai lembaga pendidikan yang berakar dalam tradisi Islam, pesantren dipandang sebagai salah satu model pendidikan khas Indonesia yang tetap melestarikan tradisi dan budaya lokal. Selain berfungsi sebagai pusat pendidikan agama pesantren juga menjadi tempat pembelajaran moral, etika, dan nilai-nilai kehidupan yang terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.[1] Di lingkungan pesantren pendidikan karakter bukanlah sesuatu yang baru. Sejak dini pembentukan karakter santri telah menjadi prioritas utama melalui pengajaran akhlak. Di pesantren akhlak menempati posisi yang sangat penting diikuti oleh bidang lainnya seperti fiqh, nahwu sharaf (tata bahasa Arab), tarikh (sejarah) Islam, dan sebagainya.[2] Seperti saat seorang kiai berjalan semua santri akan menyingkir dan memberi jalan berdiri tegak tanpa bergerak. Mereka menundukkan kepala ke tanah dan tidak berani menatap langsung. Sikap tunduk dan tawadhu’ yang ditunjukkan oleh santri merupakan ciri khas pesantren yang sulit ditemukan di lembaga pendidikan umum atau modern. Rasa hormat seperti ini ditanamkan kepada santri dan dianggap sebagai hal yang paling penting.[3]
Tradisi dan budaya di lingkungan pesantren khususnya pesantren salaf sangat menekankan nilai-nilai adab atau tata krama. Para santri menunjukkan penghormatan yang tinggi kepada kiai dan keluarganya. Salah satu wujud dari sikap hormat tersebut adalah bersikap rendah hati ketika berhadapan dengan kiai, gus, maupun guru di dalam kelas. Rasa hormat, takzim, serta kepatuhan kepada kiai menjadi salah satu nilai utama yang ditanamkan kepada setiap santri sejak awal.[4] Sikap hormat ini bukan sekadar kebiasaan tanpa makna tetapi merupakan bagian dari ajaran Islam yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai ini tidak hanya berkembang di lingkungan pesantren melainkan telah ada sejak zaman para sahabat. Dahulu para sahabat juga menunjukkan sikap yang sama ketika berhadapan dengan Nabi Muhammad sebagai wujud penghormatan dan keteladanan yang menjadi bagian penting dalam pendidikan dan kehidupan keislaman.
Sayyid Muhammad Alwi al-Maliki al-Hasani dalam kitab Mafahim-nya mengutip sebuah hadis,
كَانَ يَخْرُجُ عَلَى أَصْحَابِهِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَفِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَلَا يَرْفَعُ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَصَرَهُ إِلَيْهِ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَإِنَّهُمَا كَانَا يَنْظُرَانِ إِلَيْهِ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِمَا وَيَتَبَسَّمَانِ إِلَيْهِ وَيَتَبَسَّمُ إِلَيْهِمَا
Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah Saw. Keluar menemui sahabat dari Muhajirin dan Ansor mereka pada duduk dan terdapat pula Abu Bakar serta Umar, maka tidak ada satupun dari mereka yang mengangkat tatapannya pada Nabi Saw.
Makna dari frasa “di atas kepalanya sahabat ada burung” adalah sebuah kiasan yang menggambarkan betapa para sahabat menundukkan kepala dan tubuh mereka dengan penuh takzim serta rasa hormat kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka begitu khusyuk dan diam hingga seolah-olah tidak ingin mengusik burung yang hinggap di kepala mereka. Dalam riwayat selanjutnya, juga disebutkan bahwa:
إذا تكلم أطرق جلساؤه وكأنما على رؤوسهم الطير
Artinya: “Tatkala Nabi SAW. Berbicara sahabat yang duduk di sekitarnya menunduk seolah-olah diatas kepalanya ada burung.[5]
Penerapan Sifat Tawadhu’
Secara etimologi, istilah tawadhu berasal dari kata wadh’a, yang berarti menurunkan atau merendahkan, serta dari kata ittadha’a, yang memiliki makna merendahkan diri. Selain itu, tawadhu juga dapat diartikan sebagai sikap rendah hati terhadap sesuatu. Sementara dalam terminologi, tawadhu merujuk pada sikap menunjukkan kerendahan hati terhadap sesuatu yang dianggap mulia. Bahkan, ada yang mendefinisikannya sebagai tindakan menghormati seseorang karena keutamaannya, menerima kebenaran, dan sebagainya.[6] Dalam kitab Mu’jam Al-Ausad terdapat hadis yang diriwayatkan oleh abu hurairah mengatakan:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ، وَتَعَلَّمُوا لِلْعِلْمِ السَّكِينَةَ، وَالْوَقَارَ، وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ تَعْلَمُونَ مِنْهُ»
Artinya: Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda “Pelajarilah ilmu, dan belajarlah untuk bersikap tenang dan hormat, dan rendahkanlah dirimu kepada orang yang kamu pelajari.
Santri atau murid harus memiliki sikap tawadhu terhadap guru atau kyainya sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. Hal ini sejalan dengan penjelasan dalam kitab Ta’limul Muta’alim karya Syaikh Zarnuji, yang diterjemahkan oleh Aliy As’ad. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa seorang pelajar harus siap menghadapi kesulitan dan kerendahan hati dalam menuntut ilmu. Kasih sayang yang berlebihan dilarang kecuali dalam konteks menuntut ilmu sehingga murid dianjurkan untuk menjalin hubungan baik dengan guru, teman sekelas, dan para ulama agar lebih mudah menyerap ilmu dari mereka. Selain meneladani akhlak Rasulullah SAW sikap ini juga memberikan manfaat besar bagi para murid.[7] Sikap hormat, takzim, serta kepatuhan penuh kepada kiai merupakan salah satu nilai utama yang diajarkan kepada setiap santri sejak awal. Tradisi pesantren ini memiliki nuansa sufistik dan berlandaskan ibadah. Banyak kiai yang terhubung dengan tarekat dan membimbing para pengikutnya dalam menjalankan ibadah serta amalan-amalan khas dalam ajaran tasawuf.[8]
Dalam ajaran Islam sebagaimana dijelaskan dalam hadis seorang guru terutama kyai di lingkungan pesantren memiliki kedudukan yang mulia sebagai penyambung risalah para nabi. Peran ini menjadikannya bukan sekadar pendidik tetapi juga pewaris ilmu dan nilai-nilai keislaman yang harus dijaga dan dihormati. karenanya menghormati guru bukan hanya sebuah bentuk adab saja tetapi juga sebuah amalan yang harus diterapkan oleh setiap santri dalam kehidupannya. Hal ini turut dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Tanqihul Qaul yang menegaskan betapa pentingnya sikap penghormatan seorang murid terhadap gurunya.
وقال صلى الله عليه وسلم أكْرِمُوا العُلَمَاءَ فإنَّهُمْ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ، فَمَنْ أكرَمَهُمْ فَقَدْ أَكْرَمَ الله وَرَسُولَهُ رواه الخطيب البغدادي عن جابر
Artinya: Hendaklah kamu semua memuliakan para ulama karena mereka itu adalah pewaris para nabi. Maka, siapa memuliakan mereka, berarti memuliakan Allah dan rasul-Nya (HR Al Khatib Al Baghdadi dari Jabir RA.(
Dari hadis diatas bisa kita pahami bahawasanya seorang kyai berperan sebagai panutan di pesantren sehingga pembentukan sikap tawadhu pada murid berlangsung secara terus-menerus karena kyai senantiasa memberikan teladan bagi para santrinya. Dalam cakupan yang lebih luas kyai juga disebut sebagai ulama. Istilah kyai sendiri awalnya merujuk pada ulama tradisional di Pulau Jawa meskipun saat ini penggunaannya menjadi lebih umum mencakup ulama baik dari kalangan tradisional maupun modernis serta tidak terbatas pada Pulau Jawa saja. Perlu ditekankan bahwa peran kyai dalam membimbing, membina, dan mengembangkan pendidikan Islam bagi para santri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan Islam di masyarakat Indonesia.[9]
Bantahan Atas Tuduhan Feodalisme di Pesantren
Feodalisme pada dasarnya merupakan sistem politik yang berkembang di Eropa pada Abad Pertengahan. Dalam sistem ini para bangsawan yang memiliki kendali atas tanah sebagai sumber utama kehidupan memberikan hak pengelolaan tanah kepada para pengikut setia mereka. Sebagai imbalannya para pengikut mendapatkan perlindungan serta penghidupan, meskipun seiring waktu mereka harus menyewa tanah tersebut. Kesetiaan para pengikut ini kemudian membentuk struktur sosial feodal yang menyerupai piramida di mana kaum bangsawan berada di puncak sementara para pengikut menempati posisi di bawahnya.[10]
Sementara pondok pesantren telah lama dikenal sebagai institusi pendidikan yang menerapkan pendidikan akhlak. Sebagai bagian dari sub sistem Pendidikan Nasional yang bersifat independen di Indonesia pondok pesantren dianggap oleh banyak pihak memiliki keunggulan serta karakteristik khas dalam mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai akhlak kepada para santrinya.[11] Salah satu wujud penerapan akhlak tercermin dalam sikap ta’dzim yang ditunjukkan oleh santri terhadap guru dan kyainya. Ta’dzim adalah bentuk penghormatan dan kepatuhan penuh santri terhadap kiai yang dihormati. ketika seorang kiai memberikan perintah, santri diharapkan untuk melaksanakannya. Namun ta’dzim di sini bukan sekadar kepatuhan buta terhadap figur kiai melainkan bentuk penghormatan karena kiai dianggap sebagai sosok utama yang memiliki kedalaman ilmu, moralitas yang luhur, serta semangat juang dalam memberdayakan masyarakat.[12]
Apa yang berlaku dalam tradisi pesantren adalah bentuk sikap budaya yang memang terus dipegang secara berkelanjutan selain mempelajari ilmu yang ada di dalam pesantren tak mungkin juga untuk tidak disertai adab yang bagus sebagaimana perbedaan utama antara sekolah di pesantren dan sekolah umum terletak pada penerapan akhlak yang diterapkan dengan disiplin tinggi kepada para santri. Hal ini berpengaruh pada pembentukan etika, kesopanan, dan tata krama dalam hubungan antara guru dan murid maupun antar sesama santri. Adab kesopanan dan tata krama dijaga dengan ketat menjadikannya ciri khas yang membedakan lingkungan pesantren dari masyarakat umum. Di sini akhlak menjadi fondasi utama sebelum mempelajari disiplin ilmu lainnya. Sebagai lembaga keagamaan pesantren telah membuktikan bahwa nilai-nilai yang diajarkan tetap relevan dengan perkembangan zaman dan mampu bersaing dengan sekolah umum dalam mencetak generasi unggul yang berakhlakul karimah. Sebab tanpa akhlak yang baik setinggi apa pun pendidikan yang diperoleh dan sehebat apa pun ilmu yang dikuasai ilmu tersebut berpotensi membawa dampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain akibat lemahnya moral.[13]
Kesimpulan
Melihat dari apa yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki sistem yang unik dan khas yang tidak dapat disamakan dengan sistem feodalisme. Kepatuhan seorang santri terhadap gurunya bukanlah bentuk kepatuhan yang muncul tanpa alasan atau sekadar tradisi turun-temurun tanpa landasan. Sebaliknya sikap ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur dalam Islam terutama konsep tawadhu’ atau kerendahan hati yang menjadi bagian penting dalam menuntut ilmu. Sistem semacam ini tidak didasarkan pada hierarki kekuasaan yang menindas melainkan pada rasa hormat, adab, dan akhlak yang telah menjadi icon. Seorang santri memuliakan gurunya bukan karena paksaan, tetapi karena kesadaran akan pentingnya ilmu dan keberkahan. Nilai-nilai ini selaras dengan ajaran Islam yang menempatkan ilmu sebagai sesuatu yang mulia dan menuntut ilmu sebagai sebuah perjalanan yang harus dijalani dengan penuh kesungguhan serta sikap hormat kepada para pengajarnya. Hubungan antara santri dan guru di pesantren harus dipahami dalam konteks pendidikan dan spiritual bukan dalam kerangka sistem feodalisme yang kaku dan menindas.
Baca Juga: Di Balik Tuduhan Feodalisme dalam Tubuh Pesantren
[1] Shofi Yullah, “Upaya Pondok Pesantren Dalam Membentuk Kepribadian Santri Yang Tawadu Di Pondok Pesantren Istifadah Bluto Sumenep,” JSP: Jurnal Studi Pesantren 2, no. 1 (2023): 68–85.
[2] Zainal Arifin, “Budaya Pesantren Dalam Membangun Karakter Santri,” Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan 6, no. 1 (2014): 1–22.
[3] Riqwan Azizah, “The Relevance of Pesantren Culture: A Review on” Sejarah Etika Pesantren Di Nusantara in Nusantara”,” Risalatuna: Journal of Pesantren Studies 1, no. 1 (2021): 58–83.
[4] Idem
[5] Ahmad Nahrowi S.H, “Mengoreksi Presepsi Netizen Tentang Feodalisme Di Pesantren,” Islami[dot]co, February 4, 2025, https://islami.co/mengoreksi-presepsi-netizen-tentang-feodalisme-di-pesantren/.
[6] Purnama Rozak, “Indikator Tawadhu dalam Keseharian,” Madaniyah 7, no. 1 (January 31, 2017): 174–87.
[7] Mustika Mahardika, “Revitalisasi Sikap Tawadhu Dalam Diri Santri Studi Kasus Pondok Pesantren Miftahul Falah Teluk Dalem Rumbia,” DIMAR: Jurnal Pendidikan Islam 1, no. 2 (2020), http://ejournal.stit-almubarok.ac.id/index.php/DIMAR/article/view/25.
[8] Martin van Bruinessen, Kitab kuning, pesantren, dan tarekat: tradisi-tradisi Islam di Indonesia (Mizan, 1995).
[9] Sugeng Haryanto, Persepsi Santri Terhadap Perilaku Kepemimpinan Kiai Di Pondok Pesantren: Studi Interaksionisme Simbolik Di Pondok Pensantren Sidogiri-Pasuruan (Kementerian Agama RI, 2012).
[10] H. M. A. Tihami, “Kyai Dan Jawara Banten: Keislaman, Kepemimpinan Dan Magic,” Refleksi 14, no. 1 (2015): 1–24.
[11] Edy Edy, Robiatul Hadawiyah, and Ohan Burhanudin, “Implementasi Pendidikan Akhlak Di Pondok Pesantren Studi Pada Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Tazkiyatunnufus,” Edusifa: Jurnal Pendidikan Islam 6, no. 1 (2022): 1–13.
[12] Fahim Yustahar, “NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM TRADISI TA’DZIM TERHADAP KYAI DI PESANTREN MAHASISWA AN NAJAH PURWOKERTO” (PhD Thesis, IAIN Purwokerto, 2020), https://repository.uinsaizu.ac.id/7069/2/SKRIPSI%20FULL%20FAHIM.pdf.
[13] Ainul Yaqin, Pendidikan Akhlak/Moral Berbasis Teori Kognitif – Rajawali Pers (PT. RajaGrafindo Persada, 2021).
Penulis: Ahmad Firdaus, Mahasantri M2 Mahad Aly Hasyim Asy’ari Tebuireng