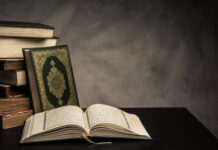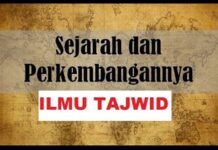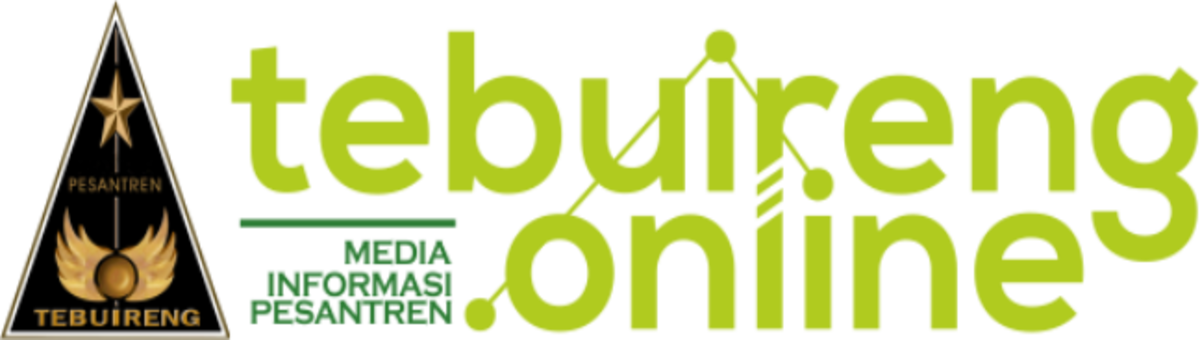Shalat tarawih merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan pada bulan Ramadan. Dalam praktiknya, jumlah rakaat shalat tarawih menjadi salah satu topik yang sering diperdebatkan di kalangan ulama. Namun pada dasarnya ulama sepakat tidak ada batas tertentu yang dijelaskan Rasulullah terkait jumlah bilangan rakat shalat tarawih, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Al-Hafiz As-Suyuthi
فَأَقُولُ: الَّذِي وَرَدَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ وَالْحَسَانُ وَالضَّعِيفَةُ الْأَمْرُ بِقِيَامِ رَمَضَانَ، وَالتَّرْغِيبُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصٍ بِعَدَدٍ، وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عِشْرِينَ رَكْعَةً، وَإِنَّمَا صَلَّى لَيَالِيَ صَلَاةً لَمْ يُذْكَرْ عَدَدُهَا ثُمَّ تَأَخَّرَ فِي اللَّيْلَةِ الرَّابِعَةِ ; خَشْيَةَ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْهِمْ فَيَعْجِزُوا عَنْهَا
Maka aku katakan: Hadis-hadis yang sahih, hasan, dan dhaif yang telah diriwayatkan menunjukkan perintah untuk menunaikan salat malam di bulan Ramadan serta anjuran untuk melakukannya tanpa pembatasan jumlah rakaat tertentu. Tidak terdapat riwayat yang sahih bahwa Nabi ﷺ pernah melaksanakan Salat Tarawih sebanyak 20 rakaat. Yang ada, beliau ﷺ melaksanakan salat beberapa malam tanpa disebutkan jumlah rakaatnya, kemudian beliau tidak keluar pada malam keempat karena khawatir salat tersebut diwajibkan atas mereka sehingga mereka tidak mampu melaksanakannya.[1]
Adapun penetapan jumlah rakaat shalat tarawih sebanyak 20 rakaat didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi. Dalam riwayat tersebut, disebutkan bahwa praktik shalat tarawih pada masa kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab berjumlah 20 rakaat. Riwayat ini kemudian menjadi dasar bagi para ulama dalam melakukan istinbath hukum, sehingga mayoritas mereka bersepakat bahwa jumlah rakaat shalat tarawih adalah 20 rakaat. Berikut adalah riwayat yang menjelaskan pelaksanaan shalat tarawih sebanyak 20 rakaat pada masa Sayyidina Umar.
وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ فَنْجَوَيْهِ الدِّيْنَوَرِيُّ بِالدَّامَغَانِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ السُّنِّيُّ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أنبأ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: ” كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً ” قَالَ: ” وَكَانُوا يَقْرَءُونَ بِالْمَئِينِ، وَكَانُوا يَتَوَكَّئُونَ عَلَى عِصِيِّهِمْ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ شِدَّةِ الْقِيَامِ “
Telah mengabarkan kepada kami Abu Abdillah Al-Husain bin Muhammad bin Al-Husain bin Fanjawaih Ad-Dinawari di Damaghan, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Ishaq As-Sunni, ia berkata: Telah memberitakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz Al-Baghawi, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Al-Ja’d, ia berkata: Telah memberitakan kepada kami Ibnu Abi Dzi’b, dari Yazid bin Khushaifah, dari As-Sa’ib bin Yazid, ia berkata: “Dahulu mereka melaksanakan salat (Tarawih) pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu ‘anhu di bulan Ramadan sebanyak 20 rakaat.” Ia (As-Sa’ib bin Yazid) juga berkata: “Mereka membaca (Al-Qur’an) dengan surah-surah yang panjang (melebihi 100 ayat), dan pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu ‘anhu, mereka bertumpu pada tongkat mereka karena panjangnya salat malam.”[2]
Hadis ini dinyatakan sahih oleh sejumlah ulama hadis terkemuka, di antaranya An-Nawawi dalam Al-Khulāṣah dan Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhażżab, Az-Zaila‘i dalam Naṣb ar-Rāyah, As-Subki dalam Syarḥ al-Minhāj, Ibnul-‘Iraqi dalam Tarḥ at-Tathrīb, Badruddin Al-‘Aini dalam ‘Umdatul-Qārī, As-Suyuthi dalam Al-Maṣābīḥ fī Ṣalāt at-Tarāwīḥ, serta ‘Ali Al-Qārī dalam Syarḥ al-Muwaṭṭa’, dan lainnya.[3]
Meskipun hadis di atas telah dinyatakan sahih oleh sejumlah ulama hadis terkemuka, namun hal itu tidak menjamin terlepas dari kritik tajam kalangan Wahabi, salah satunya Syaikh Nashiruddin Al-Albani. Dalam kajiannya, Al-Albani menilai hadis ini sebagai hadis lemah (dha‘if). Menurutnya, kelemahan tersebut disebabkan oleh adanya perawi yang cacat dalam sanadnya, yaitu Ibn Khushaifah, yang ia anggap sebagai perawi yang mungkar sehingga tidak boleh menyendiri dalam sebuah periwayatan, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Selain itu, menurut Al-Albani, kelemahan hadis ini juga diperkuat oleh adanya pertentangan dalam periwayatan. Ibn Khushaifah dinilai menyelisihi riwayat Muhammad bin Yusuf yang meriwayatkan suatu hadis tentang shalat tarawih yang dilakukan di zaman Sayyidina Umar dengan 11 rakaat, sedangkan Muhammad bin Yusuf adalah seorang perawi yang lebih tsiqah (terpercaya) dalam periwayatan. Ketidaksesuaian ini menyebabkan hadis tersebut tergolong sebagai hadis syādz, sehingga tidak bisa digunakan sebagai landasan dalam beramal.[4]
Status Hadis Shalat Tarawih 20 Rakaat
Menanggapi pernyataan Al-Albani di atas, penulis akan menyampaikan beberapa analisis yang membuktikan adanya kekeliruan dalam tuduhan yang dikeluarkan Al-Albani mengenai lemahnya hadis tarawih 20 rakaat. Ulasan ini akan menguraikan secara sistematis dua poin utama yang menjadi dasar kesalahan Al-Albani, dengan merujuk pada prinsip-prinsip dalam ilmu hadis serta pandangan ulama yang lebih otoritatif dalam menilai validitas riwayat terkait.
Pertama, pernyataan Al-Albani yang menuduh bahwa Ibn Khushaifah meriwayatkan hadis tentang Salat Tarawih 20 rakaat secara sendirian tidaklah tepat. Setelah dilakukan penelitian melalui aplikasi Khadim Al-Haramain, ditemukan beberapa riwayat lain yang juga membahas jumlah rakaat Salat Tarawih sebanyak 20 rakaat. Hadis ini memiliki sembilan syawahid atau riwayat pendukung dari berbagai sahabat Nabi, seperti Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas, dan Syaṭir bin Syakl Al-‘Absi. Selain itu, riwayat ini semakin kuat dengan adanya dukungan dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abi Mulaikah, dan Al-Harits Al-A‘war. Tidak hanya itu, Aṭa’ bin Abi Rabah, Utsman bin Affan, serta Suwaid bin Ghaflah Al-Madhhiji juga meriwayatkan hadis serupa, yang semakin menegaskan eksistensi dan keabsahannya dalam kajian ilmu hadis.
Di sisi lain kekeliruan yang nampak dalam pernyataan Al-Albani adalah tuduhannya terhadap Ibn Khushaifah sebagai perawi mungkar, dengan merujuk pada klaim Imam Ahmad bin Hanbal. Berdasarkan hal tersebut, Al-Albani menyimpulkan bahwa hadis ini mengandung perawi majruh (tercela), sehingga dinilai tidak sahih. Namun, pemahaman ini kurang tepat. Istilah mungkar yang digunakan oleh Imam Ahmad terhadap Ibn Khushaifah sebenarnya bukanlah bentuk jarh (kritik negatif) dalam makna yang umum digunakan dalam ilmu hadis. Sebaliknya, istilah tersebut merujuk pada periwayatan seorang rawi yang menyampaikan hadis secara sendirian tanpa adanya dukungan riwayat dari perawi lain (gharib). Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar, yang menegaskan bahwa penyebutan mungkar dalam konteks ini tidak serta-merta menunjukkan kecacatan seorang perawi, melainkan lebih kepada kondisi periwayatan yang bersifat individual, bahkan Ibn Hajar menilai Ibn Khusaifah sebagai perawi yang tsiqah dan hujjah hal itu juga disepakati oleh Yahya Ibn Ma’in seorang ulama hadis yang terkenal sangat ketat dalam menyeleksi suatu hadis (mutasyaddidin), tidak hanya itu, menurut Ibn Hajar Imam Malik serta para ulama hadis di zaman itu juga menjadikan hadis yang diriwayatkan Ibn Khusaifah sebagai hujjah.[5]
Dari pernyataan di atas, jelas bahwa Ibnu Khusaifah adalah seorang rawi yang terpercaya (tsiqat). Menurut al-Hafiz aż-Żahabi, periwayatan yang disampaikan secara sendiri (tafarrud) tidak selalu menunjukkan kekurangan pada seorang rawi. Justru, jika hal tersebut terjadi pada rawi yang tsiqat seperti Ibnu Khusaifah, itu menandakan bahwa ia memiliki keunggulan dalam hal informasi yang tidak dimiliki oleh perawi lain. Oleh karena itu, ia tidak perlu diragukan kecuali jika terdapat bukti yang menunjukkan kesalahannya. Aż-Żahabi berkata:
بل الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع له، وأكمل لرتبته، وأدل على اعتنائه بعلم الاثر، وضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوها، اللهم إلا أن يتبين غلطه ووهمه في الشئ فيعرف ذلك
Justru, apabila seorang rawi yang tsiqat dan hafiz meriwayatkan hadits secara sendiri, hal itu justru menjadi keunggulan baginya, menyempurnakan kedudukannya, serta menunjukkan perhatiannya yang besar terhadap ilmu hadis dan ketelitiannya dalam meriwayatkan dibandingkan dengan rekan-rekannya yang tidak mengetahuinya. Kecuali jika terbukti bahwa ia melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam suatu riwayat, maka hal itu dapat diketahui.[6]
Kedua, tuduhan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khusaifah berstatus syadz karena bertentangan (ta’arud) dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih tsiqah, yaitu Muhammad bin Yusuf, tidaklah tepat. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa perbedaan antara kedua perawi dalam kasus ini masih dapat direkonsiliasi. Dengan demikian, riwayat yang tampaknya bertentangan pada awalnya bisa saja dikompromikan sehingga keduanya tetap dapat diterima. Hal ini bisa kita buktikan dengan pengkompromian yang dilakukan Ibnu Mulaqqin dalam kitabnya berikut:
وقال الداودي وغيره: ليست هذه الرواية معارضة لرواية من روى عن السائب: ثلاثا وعشرين ركعة، ولا ما روى مالك، عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة بمعارضة لرواية السائب؛ لأن عمر جعل الناس يقومون في أول أمره بإحدى عشرة كما فعل، وكانوا يقرءون بالمئين ويطولون القراءة، ثم زاد عمر بعد ذلك فجعلها ثلاثا وعشرين ركعة على ما رواه يزيد بن رومان، وبهذا قال الثوري والكوفيون والشافعي -أي بالوتر- وأحمد، فكان الأمر على ذلك إلى زمن معاوية، فشق على الناس طول القيام؛ لطول القراءة فخفف القراءة، وكثروا من الركوع، وكانوا يصلون تسعا وثلاثين ركعة، الوتر منها ثلاث ركعات، فاستقر الأمر على ذلك وتواطأ عليه الناس وبهذا قال مالك، فليس ما جاء من اختلاف أحاديث رمضان بتناقض، وإنما ذلك في زمان بعد زمان
Menurut Ad-Dawudi dan para ulama lainnya, perbedaan jumlah rakaat shalat tarawih yang diriwayatkan dari berbagai sumber tidaklah saling bertentangan. Misalnya, riwayat yang menyebutkan bahwa orang-orang di masa Umar bin Khattab melaksanakan shalat tarawih sebanyak dua puluh tiga rakaat tidak bertentangan dengan riwayat lain yang menyatakan bahwa Umar pada awalnya menetapkan sebelas rakaat. Pada awalnya, Umar memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan shalat malam di bulan Ramadan dengan sebelas rakaat, sebagaimana yang pernah dilakukan sebelumnya. Saat itu, bacaan dalam shalat sangat panjang, karena mereka membaca surah-surah yang memiliki ratusan ayat. Namun, seiring berjalannya waktu, Umar menambah jumlah rakaat menjadi dua puluh tiga, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Yazid bin Ruman. Pendekatan ini juga didukung oleh ulama seperti Ats-Tsauri, para ulama Kufah, Imam Asy-Syafi’i (yang juga menambahkan witir dalam hitungan rakaat), serta Imam Ahmad bin Hanbal. Praktik ini terus berlanjut hingga masa pemerintahan Mu’awiyah. Pada masa itu, masyarakat mulai merasa kesulitan dengan panjangnya bacaan dalam shalat. Untuk meringankan beban mereka, bacaan shalat diperpendek, tetapi jumlah rakaat ditambah. Saat itu, kaum muslimin melaksanakan shalat malam sebanyak tiga puluh sembilan rakaat, termasuk tiga rakaat witir. Akhirnya, jumlah rakaat shalat tarawih yang beragam ini menjadi bagian dari perkembangan ibadah dari masa ke masa. Oleh karena itu, perbedaan jumlah rakaat dalam berbagai riwayat bukanlah bentuk kontradiksi, melainkan perubahan yang terjadi sesuai dengan kebutuhan umat Islam di setiap zaman.[7]
Berdasarkan pemaparan Ibn Mulaqqin yang mengutip pendapat Ad-Dawudi, dapat disimpulkan bahwa klaim Albani yang menyatakan riwayat Ibnu Khusaifah tentang shalat tarawih 20 rakaat bertentangan dengan riwayat Muhammad bin Yusuf tentang shalat tarawih 11 rakaat tidaklah tepat. Pandangan Albani ini juga berseberangan dengan mayoritas ulama yang lebih memilih untuk mengkompromikan kedua riwayat tersebut agar tidak dianggap saling bertentangan. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa klaim kedhaifan yang diberikan oleh Albani tidaklah tepat, karena dua poin utama yang ia sampaikan pada kenyataannya tidak sesuai dengan fakta. Oleh karena itu, hadis tentang shalat tarawih 20 rakaat tetap berstatus sahih, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh para ulama hadis terkemuka sejak awal.
Baca Juga: Mengenal Sanad Doa Kamilin setelah Shalat Tarawih
[1] As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr. Al-Hawi lil-Fatawi. (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr li al-Tiba‘ah wa al-Nashr, 2004). Juz 1, Hlm 413.
[2] Al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa al-Khusrawjurdi al-Khurasani. As-Sunan al-Kubra. (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003). Juz 2, Hlm 698.
[3] Bachrul Widad Dkk, Dalil Paripurna Amaliah Aswaja, (Pasuruan: Sidogiri Penerbit 2024), Hlm 280.
[4] Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. Ṣalāt at-Tarāwīḥ. (Riyadh: Maktabah al-Ma‘ārif li al-Nashr wa al-Tawzī‘, 1421 H). Hlm 57-58.
[5] Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Ahmad bin Ali. Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari. (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1379 H). Juz 1, Hlm 453.
[6] Aż-Żahabi, Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaymaz. Mīzān al-I‘tidāl fī Naqd al-Rijāl. (Beirut, Lebanon: Dār al-Ma‘rifah li al-Thibā‘ah wa al-Nashr, 1382 H/1963 M). Juz 3, Hlm 140.
[7] Ibnu al-Mulaqqin, Sirajuddin Abu Hafsh Umar bin Ali bin Ahmad al-Anshari asy-Syafi’i. At-Tawdih li Syarh al-Jami’ as-Shahih. (Damaskus, Suriah: Dar al-Nawadir, 1429 H/2008 M). Juz 13, Hlm 557-558.
Penulis: Ma’sum Ahlul Choir, Mahasantri Marhalah Tsaniyah (M2) Ma’had Aly Hasyim Asy’ari