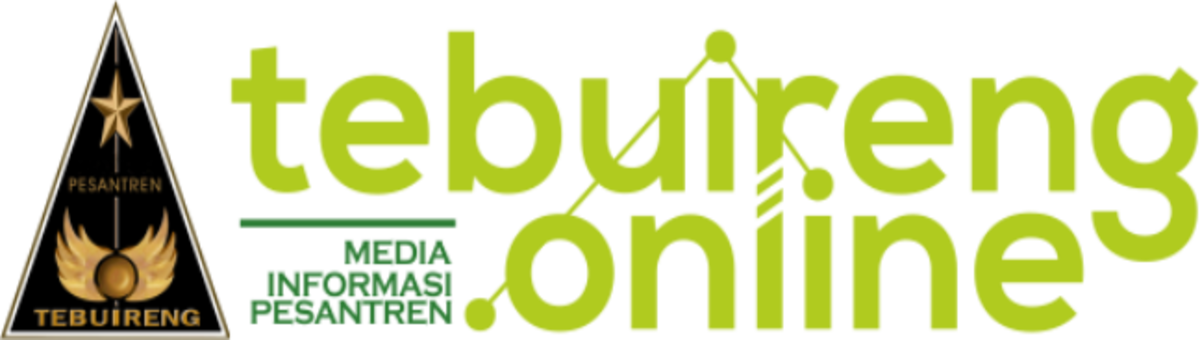Pengasuh Pesantren Tebuireng dari Masa ke Masa
- Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy’ari
KH. Hasyim Asy’ari memiliki nama lengkap Muhammad Hasyim bin Asy’ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim atau yang populer dengan nama Pangeran Benawa bin Abdul Rahman yang juga dikenal dengan julukan Jaka Tingkir (Sultan Hadiwijaya) bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fatah bin Maulana Ishaq bin Ainul Yakin yang populer dengan sebutan Sunan Giri. Sementara dari jalur ibu adalah Muhammad Hasyim binti Halimah binti Layyinah binti Sihah bin Abdul Jabbar bin Ahmad bin Pangeran Sambo bin Pangeran Benawa bin Jaka Tingkir atau juga dikenal dengan nama Mas Karebet bin Lembu Peteng (Prabu Brawijaya VI). Penyebutan pertama menunjuk pada silsilah keturunan dari jalur bapak, sedangkan yang kedua dari jalur ibu.
Kiai Hasyim dilahirkan dari pasangan Kiai Asy’ari dan Halimah pada hari Selasa kliwon tanggal 14 Februari tahun 1871 M atau bertepatan dengan 12 Dzulqa’dah tahun 1287 H. Tempat kelahiran beliau berada disekitar 2 kilometer ke arah utara dari kota Jombang, tepatnya di Pesantren Gedang. Gedang sendiri merupakan salah satu dusun yang terletak di desa Tambakrejo kecamatan Jombang.
Pada usianya yang ke-21, Kiai Hasyim menikah dengan Nafisah, salah seorang putri Kiai Ya’qub (Siwalan Panji, Sidoarjo). Pernikahan itu dilangsungkan pada tahun 1892 M/1308 H. Tidak lama kemudian, Kiai Hasyim bersama istri dan mertuanya berangkat ke Makkah guna menunaikan ibadah haji. Bersama istrinya, Nafisah, Kiai Hasyim kemudian melanjutkan tinggal di Makkah untuk menuntut ilmu. Tujuh bulan kemudian, Nafisah menninggal dunia setelah melahirkan seorang putra bernama Abdullah. Empat puluh hari kemudian, Abdullah menyusul ibu ke alam baka. Kematian dua orang yang sangat dicintainya itu, membuat Kiai Hasyim sangat terpukul. Kiai Hasyim akhirnya memutuskan tidak berlama-lama di Tanah Suci dan kembali ke Indonesia setahun kemudian.
Setelah lama menduda, Kiai Hasyim menikah lagi dengan seorang gadis anak Kiai Romli dari desa Karangkates (Kediri) bernama Khadijah. Pernikahannya dilakukan sekembalinya dari Makkah pada tahun 1899 M/1325 H. Pernikahannya dengan istri kedua juga tidak bertahan lama, karena dua tahun kemudian (1901), Khadijah meninggal.
Untuk ketiga kalinya, Kiai Hasyim menikah lagi dengan perempuan nama Nafiqah, anak Kiai Ilyas, pengasuh Pesantren Sewulan Madiun. Dan mendapatkan sepuluh orang anak, yaitu: Hannah, Khoiriyah, Aisyah, Azzah, Abdul Wahid, Abdul Hakim, Abdul Karim, Ubaidillah, Mashurah, dan Muhammad Yusuf. Perkawinan Kiai Hasyim dengan Nafiqah juga berhenti di tengah jalan, karena Nafiqah meninggal dunia pada tahun 1920 M.
Sepeninggal Nafiqah, Kiai Hasyim memutuskan menikah lagi dengan Masrurah, putri Kiai Hasan yang juga pengasuh Pesantren Kapurejo, pagu (Kediri). Dari hasil perkawinan keempatnya ini, Kiai Hasyim memiliki empat orang anak: Abdul Qadir, Fatimah, Khadijah dan Muhammad Ya’qub. Perkawinan dengan Masrurah ini merupakan perkawinan terakhir bagi Kiai Hsyim hingga akhir hayatnya.
Kiai Hasyim dikenal sebagai tokoh yang haus pengetahuan agama (islam). Untuk mengobati kehausannya itu, Kiai Hasyim pergi ke berbagai pondok pesantren terkenal di Jawa Timur saat itu. Tidak hanya itu, Kiai Hasyim juga menghabiskan waktu cukup lama untuk mendalami islam di tanah suci (Makkah dan Madinah). Dapat dikatakan, Kiai Hasyim termasuk dari sekian santri yang benar-benar secara serius menerapkan falsafah Jawa, “Luru ilmu kanti lelaku (mencari ilmu adalah dengan berkelana) atau sambi kelana”
Pada usia sekitar memasuki 13 tahun, Kiai Hasyim telah mampu menguasai berbagai bidang kajian islam dan dipercaya membantu ayahnya mengajar santri yang lebih senior. Selanjutnya Kiai Hasyim mulai menjelajahi beberapa pesantren. Mula-mula, Kiai Hasyim belajar di pesantren Wonokoyo (Probolinggo), lalu berpindah ke pesantren Langitan (Tuban). Merasa belum cukup, Kiai Hasyim melanjutkan pengembaraan intelektualnya ke Pesantren Tenggilis (Surabaya), dan kemudian berpindah ke Pesantren Kademangan (Bangkalan), yang saat itu diasuh oleh Kiai Kholil. Setelah dari pesantren Kiai Kholil, Kiai Hasyim melanjutkan di pesantren Siwalan Panji (Sidoarjo) yang diasuh oleh Kiai Ya’kub.
Atas nasihat Kiai Ya’kub, Kiai Hasyim akhirnya meninggalkan tanah air untuk berguru pada ulama-ulama terkenal di Makkah. Di Makkah, Kiai Hasyim berguru pada Syaikh Ahmad Amin al-Attar, Sayyid Sultan bin Hashim, Sayyid Ahmad bin Hasan al-Attas, Syaikh Sa’id al-Yamani, Sayyid Alawi bin Ahmad al-Saqqaf, Sayyid Abbas Maliki, Sayyid Abdullah al-Zawawi, Syaikh Salih Bafadal, dan Syaikh Sultan Hasim Dagastana, Syaikh Shuayb bin Abd al-Rahman, Syaikh Ibrahim Arab, Syaikh Rahmatullah, Sayyid Alwi al-Saqqaf, Sayyid Abu Bakr Shata al-Dimyati, dan Sayyid Husayn al-Habshi yang saat itu menjadi multi di Makkah. Selain itu, Kiai Hasyim juga menimba pengetahuan dari Syaikh Ahmad Khatib Minankabawi, Syaikh Nawawi al-Bnatani dan Syaikh Mahfuz al-Tirmisi. Tiga nama yang disebut terakhir (Khatib, Nawawi dan Mahfuz) adalah guru besar di Makkah saat itu yang juga memberikan pengaruh signifikan dalam pembentukan intelektual Kiai Hasyim di masa selanjutnya.
Presatasi belajar Kiai Hasyim yang menonjol, membuatnya kemudian juga mmperoleh kepercaaan untuk mengajar di Masjid al-Haram. Beberapa ulama terkenal dari berbagai negara tercatat pernah belajar kepadanya. Di antaranya ialah Syaikh Sa’d Allah al-Maymani (mufti di Bombay, India), Syaikh Umar Hamdan (ahli hadith di Makkah), al-Shihan Ahmad bin Abdullah (Syiria), KH. Abdul Wahhanb Chasbullah (Tambakberas, Jombang), K. H. R Asnawi (Kudus), KH. Dahlan (Kudus), KH. Bisri Syansuri (Denanyar, Jombang), dan KH. Saleh (Tayu).
- KH. Abdul Wahid Hasyim
KH. Abdul Wahid Hasyim merupakan pengasuh kedua Pesantren Tebuireng; memimpin Tebuireng selama tiga tahun (1947 – 1950). Salah seorang anggota BPUPKI dan perumus Pancasila ini, merupakan reformis dunia pendidikan pesantren dan pendidikan Islam Indonesia. Pahlawan nasional ini juga dikenal sebagai pendiri IAIN (sekarang UIN) dan merupakan Menteri Agama tiga kabinet (Kabinet Hatta, Kabinet Natsir, dan Kabinet Sukiman).
Beliau dilahirkan pada, Jum’at legi, 05 Rabi’ul Awal 1333 H. atau pada tanggal 01 Juni 1914 M. Beliau adalah Putera kelima dari pasangan KH. M. Hasyim Asy’ari dengan Bu Nyai Hj. Nafiqah.
Sejak kecil Abdul Wahid sudah masuk Madrasah Tebuireng dan sudah lulus pada usia yang sangat belia, 12 tahun. Selama bersekolah, ia giat mempelajari ilmu-ilmu kesustraan dan budaya Arab secara outodidak. Dia juga mempunyai hobi membaca yang sangat kuat. Dalam sehari, dia membaca minimal lima jam.
Ketika berusia 13 tahun, Abdul Wahid mulai melakukan pengembaraan mencari ilmu. Awalnya ia belajar di Pondok Siwalan, Panji, Sidoarjo. Di sana ia mondok mulai awal Ramadhan hingga tanggal 25 Ramadhan (hanya 25 hari). Setelah itu pindah ke Pesantren Lirboyo, Kediri, sebuah pesantren yang didirikan oleh KH. Abdul Karim, teman dan sekaligus murid ayahnya.
Ketika kembali ke Tebuireng, umurnya baru mencapai 15 tahun dan baru mengenal huruf latin. Dengan mengenal huruf latin, semangat belajarnya semakin bertambah. Ia belajar ilmu bumi, bahasa asing, matematika, dll. Dia juga berlangganan koran dan majalah, baik yang berbahasa Indonesia maupun Arab.
Pemuda Abdul Wahid mulai belajar Bahasa Belanda ketika berlangganan majalah tiga bahasa, ”Sumber Pengetahuan” Bandung. Tetapi dia hanya mengambil dua bahasa saja, yaitu Bahasa Arab dan Belanda. Setelah itu dia mulai belajar Bahasa Inggris.
Pada tahun 1932, ketika umurnya baru 18 tahun, Abdul Wahid pergi ke tanah suci Mekkah bersama sepupunya, Muhammad Ilyas. Selain menjalankan ibadah haji, mereka berdua juga memperdalam ilmu pengetahuan seperti nahwu, shorof, fiqh, tafsir, dan hadis. Abdul Wahid menetap di tanah suci selama 2 tahun.
Pada tahun 1932, ketika umurnya baru 18 tahun, Abdul Wahid pergi ke tanah suci Mekkah bersama sepupunya, Muhammad Ilyas. Selain menjalankan ibadah haji, mereka berdua juga memperdalam ilmu pengetahuan seperti nahwu, shorof, fiqh, tafsir, dan hadis. Abdul Wahid menetap di tanah suci selama 2 tahun.
- KH. Abdul Karim Hasyim
KH. Abdul Karim dilahirkan di Tebuireng pada tanggal 30 September 1919, dengan nama kecil Abdul Majid. Sejak kecil Abdul Karim dididik langsung oleh kakaknya, Kiai Wahid Hasyim, serta kakak iparnya, Kiai Baidlawi. Dia terkenal sebagai anak yang rajin belajar. Masa pendidikannya lebih banyak dihabiskan di Tebuireng. Dia tercatat sebagai salah seorang siswa pertama Madrasah Nidzamiyah yang didirikan kakaknya, Kiai Wahid Hasyim.
Pada tahun 1943, ketika Jepang berkuasa di Indonesia, Kiai Karim menikah dengan Masykuroh, putri seorang kiai yang kaya raya di Jombang. Melalui perkawinan ini, Kiai Karim dikaruniai empat putra, yaitu Muhammad Nasir, Lilik Nailufari, Muhammad Hasyim, dan Lilik Nafiqoh.
pada tahun 1954, ketika sudah tidak menjabat sebagai pengasuh Tebuireng, Kiai Karim diangkat menjadi Ahli dan Pengawas Pendidikan Agama di Semarang. Lalu pada tahun 1960, Kiai Karim dipindahkan ke wilayah Surabaya dan Bojonegoro. Kemudian pada tahun 1968, dia diangkat menjadi dosen luar biasa pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
Selama satu tahun memimpin Tebuireng, Kiai Karim banyak melakukan reorganisasi dan revitalisasi sistem madrasah. Pada masa kepemimpinannya, madrasah-madrasah di berbagai pesantren sedang mengalami masa-masa suram. Dikatakan suram karena sejak penyerahan KedaulatanRI dari pemerintah Belanda kepada pemerintah RI tahun 1949, Pemerintah lebih memprioritastan sistem persekolahan formal (schooling) daripada madrasah. Sebuah perlakuan diskriminatif yang tidak adil. Perlakuan diskriminatif lainnya terlihat dari keputusan bahwa yang boleh menjadi pegawai negeri hanya mereka yang lulus sekolah umum.
Pada masa Kiai Karim, didirikan pula Madrasah Mu’allimin enam tahun. Jenjang ini lebih berorientasi pada pencetakan calon guru yang memilki kelayakan mengajar. Selain pelajaran agama dan umum, para siswa Mu’allimin juga dibekali keahlian mengajar seperti didaktik-metodik dan ilmu psikologi. Dengan adanya jenjang Mu’allimin, permintaan tenaga guru dari berbagai daerah dapat dipenuhi.
Setelah satu tahun mengasuh Tebuireng, Kiai Karim menyerahkan estafet kepemimpinan kepada Kiai Baidlawi, yang merupakan kakak iparnya sendiri. Pergantian jabatan pengasuh Tebuireng dari Kiai Karim kepada Kiai Baidlawi, merupakan hal yang baru dari sistem kepemimpnan Tebuireng, karena seorang menantu dapat menggantikan kedudukan anak kandung di saat si anak kandung masih hidup.
Pada tahun 1972, ketika Kiai Karim menunaikan ibadah haji bersama Kiai Idris Kamali dan keluarga Pesantren Seblak, Kiai Karim menderita sakit yang diakibatkan oleh perubahan cuaca. Setelah beberapa hari dirawat, akhirnya nyawa beliau tidak bisa tertolong lagi. Kiai Karim meninggal dunia dan jenazahnya dimakamkan di Makkah.
- KH. Ahmad Baidlawi
KH. Baidhawi lahir di Banyumas, Jawa tengah, pada tahun 1898 M. Ayahnya, Kiai Asro, merupakan kiai yang sangat terkenal di Banyumas. Salah seorang cucu Kiai Asro adalah KH. Saifuddin Zuhri, mantan Menteri Agama Republik Indonesia periode 1961-1967 yang juga mertua Gus Solah.
Selama nyantri di berbagai pesantren, Kiai Baidhawi terkenal sangat rajin belajar, baik mempelajari kitab yang telah dikaji ataupun yang belum. Ketekunan itu ditopang oleh kecerdasannya yang luar biasa. Dia selalu menarik simpati sang kiai, di manapun berada, tak terkecuali Kiai Hasyim Asy’ari. Kiai Hasyim sering menunjuk Kiai Baidhawi sebagai pengganti bila sedang berhalangan. Bahkan tidak jarang dalam masalah-masalah tertentu, Kiai Hasyim bermusyawarah dan meminta pertimbangan kepadanya.
Sebagai bentuk penghargaan kepada murid istimewanya itu, Kiai Hasyim memberangkatkannya ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu di sana. Setelah itu, Kiai Baidhawi melanjutkam studinya ke al-Azhar, Kairo, yang merupakan perguruan Islam tertua di dunia.
Sekembalinya dari Mesir, Kiai Baidhawi mengabdikan diri di Tebuireng dengan membantu Hadratus Syeikh mengajar. Tak lama kemudian, Hadratus Syeikh menjodohkannya dengan putri ketiganya, Aisyah. Dari pernikahan ini Kiai Baidhawi dikaruniai 6 putra-putri. Yaitu Muhammad, Ahmad Hamid, Mahmud, Ruqayyah (istri KH. Yusuf Masyhar MQ), Mahmad, dan Kholid.
Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Setelah dikaruniai anak yang ke-6, Nyai Aisyah diapanggil oleh Yang Maha Kuasa. Kesedihan melanda keluarga besar Kiai Baidhawi.
Atas restu keluarga, Kiai Baidhawi kemudian menikah lagi dengan Nyai Bani’, adik Kiai Mahfudz Anwar (Seblak). Dari perkawinan ini Kiai Baidhawi dikaruniai seorang putri bernama Muniroh.
Kemudian Kiai Baidhawi menikah lagi dengan keponakan Kiai Mahfudz Anwar bernama Nadhifah. Dari pernikahan ini beliau dikaruniai 5 putra-putri. Yaitu Muthohar, Hafsoh, Munawar, Munawir, dan Fatimah.
Kiai Baidhawi menjadi pengasuh Tebuireng setelah Kiai Karim memintanya untuk menggantikan kedudukannya. Salah satu peran penting Kiai Baidhawi di Tebuireng adalah pengenalan sistem klasikal (madrasah). Sebagaimana diketahui, sejak awal berdirinya, Tebuireng menggunakan sistem pengajian sorogan dan bandongan. Namun sejak tahun 1919, Kiai Baidhawi bersama Kiai Maksum mulai memperkenalkan sistem klasikal, meskipun materi pelajarannya masih terbatas pada kitab-kitab klasik (penambahan materi umum baru
Selama masa kepemimpinannya, Kiai Baidlawi tidak melakukan perubahan sistem maupun kurikulum di Tebuireng. Kiai Baidhawi meneruskan dan memelihara sistem yang sudah ada.
Ketika kepengasuhan Tebuireng ingin diteruskan oleh KH. Abdul Kholik Hasyim, Kiai Baidhawi sama sekali tidak merasa keberatan. Dia menyerahkan kursi pengasuh kepada adik iparnya itu dengan ikhlas hati. Baginya, figure pemimpin tidaklah penting. Yang penting adalah kelangsungan proses belajar-mengajar di pesantren Tebuireng, terlepas siapa pengasuhnya.
Meskipun tidak lagi menjadi pengasuh Tebuireng, Kiai Baidhawi tetap tekun membantu proses belajar-mengajar di sana. Beliau ikut mengajar di Madrasah Salafiyyah Syafi’iyyah Tebuireng. Tak jarang bila ada waktu longgar, beliau memantau para santri ke kamar-kamar.
Jumat sore di tahun 1955, cuaca di langit Tebuireng terasa sejuk. Kiai Baidhawi, yang pada siang harinya menjadi imam salat jumat dan ikut mendoakan korban bencana di Aceh, pada sore harinya mengalami demam tinggi. Demam itu terus dirasakan hingga malam hari.
Pada pertengahan malam, para santri dikejutkan oleh berita bahwa KH. Baidhawi telah berpulang ke rahmatuLlah. Allah Swt. telah memanggilnya meninggalkan kehidupan fana ini. Inna liLlahi wa Inna ilahi Raji’un.
- KH. Abdul Choliq Hasyim
KH. Adul Choliq Hasyim, lahir pada tahun 1916 putra keeanam dari Hadrautussyaikh Hasyim Asy’ari dan Nyai Nafiqah. Abdul Hafidz merupakan nama kecil KH Abdul Choliq Hasyim. Sejak kecil kelebihan Gus Choliq sudah mulai tampak. Terlihat dari kejadian ketika ada tamu ayahnya yang datang dengan mobil misalnya, Gus Choliq menekan ringan bodi mobil tersebut dengan jarinya. Anehnya seketika itu bagian yang dipencetnya penyok, padahal terbuat dari besi baja yang keras. Terjadi pula ketika, sang ayah pernah menghukumnya. Gus Kholiq diikat di sebuah pohon sawo dan diberi kelangrang (semut merah ganas). Namun semut-semut itu hanya lewat begitu saja dan tidak mau menggigit tubuh Gus Choliq.
Sejak kecil Abdul Choliq dididik langsung oleh Hadratussyaikh (ayah). Setelah dianggap mampu, Abdul Choliq melanjutkan pendidikannnya ke Pondok Pesantren Sekar Putih, Nganjuk. Lalu dilanjutkan menuju Pesantren Kasingan, Rembang (kota pesisir laut Utara). Di sana beliau belajar kepada Kiai Kholil bin Harun yang terkenal sebagai pakar nahwu, bahkan sampai dijuluki Imam Sibawaih Zamanihi. Beliau melanjutkan pendidikannya ke Pesantren Kajen, Juwono, Pati, Jawa Tengah.
Pada tahun 1932 Abdul Choliq Hasyim muda, pada saat itu berusia 16 tahun pergi ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Ia bermukim selama empat tahun sambil memperdalam keilmuan, salah seorang gurunya adalah Syaikh Ali al Maliki al Murtadha. Tahun 1936, Abdul Choliq pulang ke tanah air. Selang beberapa waktu sang ayah menjodohkannya dengan seorang wanita salehah bernama Afifah putra seorang saudagar dari Kecamatan Ngoro (Jombang) bernama Haji Dimyati. Selang dua tahun Nyai Afifah wafat disebabkan sakit.
Setelah itu, Abdul Choliq dinikahkan lagi dengan salah satu keponakan Kiai Baidlowi asal Purbalingga bernama Siti Azzah. Pada tahun 1942, lahir bayi laki-laki dari pasangan KH Choliq Hasyim dan Sitti Azzaah bernamakan Abdul Hakam, yang merupakan putra tunggal Kiai Choliq.
Kepemimpinannya di Tebuireng banyak melakukan pembenahan pada sistem pendidikan dan pengajaran kitab kuning, yang pada tahun-tahun sebelumnya digantikan dengan sistem klasikal. Langkah pertama yang diambilnya ialah meminta bantuan kakak iparnya, Kiai Idris Kamali (tahun 1953), untuk mengajar di Tebuireng. Kiai Idris diminta untuk mengajarkan kembali kitab-kitab kuning guna mempertahankan sistem salaf, serta melakukan revitalisasi sistem pengajaran.
Dalam memimpin Tebuireng, Kiai Choliq terkenal sangat disiplin. Ini mungkin merupakan pengaruh tidak langsung dari jiwa militernya. Meskipun demikian, Kiai Choliq sangat hormat kepada Kiai yang telah membantu beliau mengajar di Pesantren Tebuireng, seperti Kiai Idris, Kiai Adlan Ali, Kiai Shobirin, Kiai Mansur, dan Kiai Manan. Sedangkan Kiai Choliq mengajar kitab-kitab dalam hal tasawwuf.
Pada masa Kiai Choliq, madrasah yang telah dirintis oleh para pendahulunya tetap dipertahankan. Saat itu Madrasah Tebuireng terdiri dari tiga jenjang, yakni Ibtidaiyah (SD), Tsanawiyah (SLTP), dan Mu’allimin. Pada masa ini pula, Madrasah Nidzamiyah yang dulunya didirikan oleh Kiai Wahid, berganti nama menjadi Madrasah Salafiyah Syafi’iyah
Senin, 21 Juni 1965, tiga bulan atau 100 hari sebelum meletusnya peristiwa G.30.S/PKI. Kiai Choliq menderita sakit. Semua keluarga mencemaskan kondisi beliau yang semakin menurun, keluarga besar Tebuireng mengharap kesembuhan untuk pengasuh pesantren. Namun, Allah telah menghendaki Kiai Choliq untuk menghadap kepada-Nya
- KH. Muhammad Yusuf Hasyim
Pak Ud lahir pada 3 Agustus 1929, di tengah suasana santri yang tengah khusyuk melantunkan ayat-ayat suci al-Quran dan lengkingan suara azan yang memenuhi angkasa Tebuireng. Dia adalah anak terakhir (bungsu) dari tujuh bersaudara (selain empat saudaranya yang meninggal di waktu kecil).
Masa kecilnya dihabiskan di Tebuireng. Dia belajar membaca al-Quran langsung dari ayahandanya. Ketika melakukan perjalanan, Kiai Hasyim sering meminta Muhammad Yusuf kecil untuk mengulangi hapalan ayat-ayat Al-Quran, baik saat naik mobil, kereta api, atau naik delman (dokar).
Sejak berumur 12 tahun, beliau mondok di Pesantren Al-Quran Sedayu Lawas, Gresik, yang dipimpin oleh Kiai Munawar. Kemudian pindah ke pesantren Krapyak, Jogjakarta, di bawah asuhan Kiai Ali Ma’sum. Setelah dari Krapyak, Pak Ud sempat menimba ilmu di pondok modern Tegal, Ponorogo.
Meskipun tidak sempat mengenyam pendidikan formal, tapi Pak Ud rajin membaca dan banyak bergaul dengan kalangan terpelajar. Hal itu diimbangi dengan ketajaman intuisi dan keluwesan bergaul. Ini sangat mendukung ketika Pak Ud harus terjun sebagai politisi Nasional di kemudian hari.
- KH. Salahuddin Wahid
Memiliki nama lengkap Salahuddin Al Ayyubi, atau biasa disapa Gus Sholah lahir di Kota Jombang pada 11 September 1942, beliau anak ketiga dari 6 bersaudara. Semasa kecil waktunya banyak dihabiskan di Pesantren Denanyar, Jombang, tempat tinggal kakeknya dari garis ibu, KH. Bisri Syansuri. Pada tahun 1947 Salahuddin pindah ke Tebuireng. Menyusul wafatnya Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy’ari yang digantikan oleh ayahnya KH. Wahid Hasyim. Selanjutnya pada awal tahun 1950, ketika ayahnya diangkat menjadi Menteri Agama, Salahuddin ikut pindah ke Jakarta.
Pendidikan dasarnya ditempuh di SD KRIS (Kebangkitan Rakyat Indonesia Sulewesi), dimana para gurunya banyak yang menjadi anggota pergerakan. Ketika kelas IV, Salahuddin pindah ke SD Perwari yang terletak di seberang kampus UI Salemba. Antara tahun 1955-1958, Salahuddin melanjutkan sekolahnya di SMP Negeri 1 Cikini. Di SMP ini ia memilih jurusan B (ilmu pasti). Setelah lulus SMP ia masuk SMA Negeri 1 yang populer dengan sebutan SMA Budut (Budi Utomo).
Tahun 1962 Salahuddin tamat SMA dan melanjutkan pendidikannya ke Institut Teknologi Bandung (ITB). Dia memilih jurusan arsitektur, meskipun sebenarnya ia juga berminat masuk jurusan ekonomi dan jurusan hukum. Semasa kuliah di Bandung, ia aktif dalam kegiatan senat mahasiswa dan dewan mahasiswa. Sejak tahun 1967, aktif di organisasi mahasiswa ekstra kampus, dan memilih Pergerakan Mahasiswa Islam Indonsia (PMII) sebagai wadahnya.
Pada bulan Februari 2006, KH. Yusuf Hasyim menelpon Gus Sholah dan menyampikan niatnya untuk mundur dari jabatan Pengasuh Tebuireng. KH. Yusuf Hasyim meminta Gus Sholah untuk menggantikannya. Lalu pada tanggal 12 April 2006, Gus Sholah bertemu dengan KH. Yusuf Hasyim beserta keluarga besar Tebuireng serta para alumni senior, untuk mematangkan rencana pengunduran diri KH. Yusuf Hasyim dan naiknya Gus Sholah sebagai Pengasuh Tebuireng.
Keesokan harinya, pergantian pengasuh diresmikan bersama dengan acara “Tahlil Akbar Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari dan Temu Alumni Nasional Pondok Pesantren Tebuireng”. Setelah hari yang bersejarah tersebutlah kiprah Gus Sholah dimulai untuk Pesantren Tebuireng.
Ketika KH. Salahuddin Wahid memangku jabatan Pengasuh Pesantren Tebuireng, ia banyak melakukan perombakan dan pembaharuan di pesantren. Perombakaan dan pembahruan tersebut bukan tanpa alasan. Tujuan pembaharuan itu adalah agar Pesantren Tebuireng dapat bersaing dengan tuntutan zaman yang semakin maju dan modern. Di tangan KH. Salahuddin Wahid Pesantren Tebuireng telah menjadi cerminan pesantren tua yang selalu siap mengikuti perkembangan zaman.
KH. Abdul Hakim Machfudz.
Setelah kewafatan KH. Salahuddin Wahid pada 02 Februari 2020, tongkat estafet kepengasuhan Pesantren Tebuireng dilanjutkan oleh KH. Abdul Hakim Machfudz. Pada 2015, KH. Abdul Hakim Macfudz sendiri diamanahi oleh KH. Salahuddin Wahid untuk menjadi wakil Pengasuh Pesantren Tebuireng, yang mana tugas utamanya adalah mempelajari segala aspek yang ada di Pesantren Tebuireng. Langkah ini, sebagaimana yang dituturkan oleh KH. Abdul Hakim Machfudz, pada peringatan 7 hari kewafatan KH. Salahuddin Wahid adalah sebuah upaya tersendiri untuk mempersiapkan dirinya kelak menjadi pengasuh Pesantren Tebuireng di suatu hari kelak.
KH. Abdul Hakim Machfudz dilahirkan pada tanggal 17 Agustus 1958, putra dari KH. Mahfudz Anwar bin KH. Alwi (Pondok Pesantren Paculgowang Jombang). Sedangkan ibu beliau bernaa Nyai Hj. Abidah Ma’shum yang mana beliau adalah putri dari Nyai Hj. Khoiriyah Hasyi, putri dari Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy’ari.
Pendidikan agama beliau ditempuh langsung dari bimbingan orang tuanya, yakni pada kala itu di Pondok Pesantren Sunan Ampel Jombang. Selanjutnya beliau melanjutkan Pendidikan di SMPN Jombang, kemudian di SMAN Jombang dan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta.
Sebelum menjadi wakil pengasuh Pesantren Tebuireng, KH. Abdul Hakim Machfudz memiliki kiprah kariri, antara lain; Kepala Cabang Wilayah Cilegon, PT Djakarta Llyod, Eksportir (Komoditi seperti pinang, minyak atsiri), Pendiri PT Energi Mineral Langgeng (EML), yang bergerak dib Perusahaan Migas Nasional, Pendiri PT. Bama Berita Sarana (BBS Group), yang merupakan salah satu stasiun televisi berjaringan di Indonesia. Menjadi Wakil Ketua dari KADIN (Kadin atau Kamar Dagang dan Industri Indonesia adalah organisasi yang menjadi wadah bagi para pelaku usaha di Indonesia. Kadin berperan sebagai jembatan penghubung antara pemerintah dan dunia usaha) Kemudian pada tahun 2020 beliau diamanahi menjadi Pengasuh Pesantren Tebuireng menggantikan KH. Salahuddin Wahid. Semenjak menjadi pengasuh Pesantren Tebuireng, KH. Abdul Hakim Machfudz diamanahi beberapa jabatan di organisasi Nadhatul Ulama, seperti Ketua PBNU, dan saat ini menjabat Ketua PWNU Jawa Timur masa periode 2024-2029.
Tugas utama KH. Abdul Hakim Machfudz saat menjadi pengasuh Pesantren Tebuireng ialah melanjutkan segala hal yang sudah dilakukan oleh para pengasuh-pengasuh sebelumnya. Pada era beliau juga, KH. Abdul Hakim Machfudz mampu memperluas jaringan dan menguatkan Ikatan Alumni Pesantren Tebuireng (IKAPETE) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Tercatat, di masa beliau jumlah Pengurus Wilayah IKAPETE sebanyak 18 dan Pengurus Cabag berjumlah 79. Selain itu juga, terdapat beberapa pondok cabang Pesantren Tebuireng, yang lahir pada era kepengasuhan KH. Abdul Hakim Machfudz, seperti pendirian Pesantren Tebuireng XV Nur Hasyim Bina Aswaja di daerah Karang Taruna Pelai Hari, Tanah Laut, Kalimatan Selata. Pesantren Tebuireng XVI Tahfidzul Quran al-Musthofa, yang berlokasi di Kecamatan Parakan, Kab. Temanggung, Jawa Tengah. Lalu ada Tebuireng XVII Pesantren NU Abdul Jamil, yang bertempat di Banyumas, Jawa Tengah. Seanjutnya ada Tebuireng cabang XVII Yayasan KH. M. Asy’ari Pododadi, di wilayah Terban, Perkalongan Jawa Tengah. Dan terakhir ada Pesantren Tebuireng XIX Nurul Hidayah, yang terletak di Dususn Labuah Tereng, Lombok Barat.