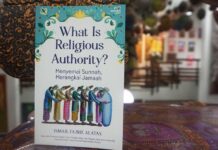Hari-hari di kota yang dingin dan sibuk sudah terlalu lama membeku dalam ingatan Adrian Firman. Sudah dua tahun lebih sejak ia meninggalkan kampung halaman, dua tahun yang penuh dengan kegagalan dan harapan yang sirna. Tanpa bisa menggapai apa yang ia impikan, Adrian merasa seolah tak memiliki apa-apa lagi. Setiap malam, langit yang penuh bintang selalu mengingatkan akan keluarga di rumah, di desa yang tak jauh dari sana. Namun, bukan rumah yang kini menghantuinya—melainkan rasa malu yang begitu besar karena ia merasa tak membawa apapun untuk mereka.
Hari raya sebentar lagi tiba. Suara-suara bersemangat dari anak-anak yang berlomba menyusun ketupat terdengar jelas di telinganya, meski ia berada jauh di sana, di kota yang ramai. Ia tahu, di rumah, ibu dan ayahnya pasti sudah mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Ibu akan memasak opor ayam, sementara ayah akan menggantungkan ketupat yang sudah selesai dijahit. Keluarga besar yang akan datang juga pasti menantinya, seperti biasa, dengan sambutan hangat yang tak pernah berubah.
Namun, ada satu hal yang selalu mengganjal di hatinya: Adrian merasa dirinya tidak lebih dari seorang yang gagal. Saat ia pulang, ia tak akan membawa oleh-oleh, tak akan membawa kabar gembira, tak akan membanggakan kedua orang tuanya dengan keberhasilan yang mereka harapkan.
Sudah beberapa kali Adrian mencoba untuk pulang, namun ia selalu menundanya. Setiap kali ada kesempatan, hati kecilnya berkata, “Apa yang bisa kuberikan pada mereka? Aku tak punya apa-apa.” Ia ingat betul saat pertama kali pergi, ayah dan ibunya mengantarnya hingga ke terminal, dengan harapan besar agar anak mereka bisa sukses dan membawa kebanggaan bagi keluarga.
Namun, kenyataan berkata lain. Adrian datang ke kota besar dengan penuh semangat, siap untuk mengejar impian. Ia mulai bekerja sebagai asisten di sebuah kantor kecil, berharap bisa belajar dan berkembang. Namun kenyataan, seiring waktu, tidak sesuai dengan yang ia bayangkan. Setiap hari yang dilalui penuh dengan kekecewaan.
Gaji yang pas-pasan, pekerjaan yang tak sesuai harapan, serta rekan-rekan kerja yang lebih pandai dan lebih beruntung darinya, semuanya semakin membuatnya merasa terpinggirkan. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, “Apa yang salah dengan diriku?”
Di kota ini, Adrian merasa seperti orang asing. Setiap kali ia berusaha untuk meraih sesuatu, selalu ada yang menghalangi, entah itu kegagalan atau ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Banyak teman-temannya yang sukses dengan cara mereka sendiri, tetapi Adrian seolah terperangkap dalam rutinitas yang tak membuahkan hasil.
******
Lama kelamaan, rasa percaya dirinya semakin luntur. Ia tak tahu bagaimana menjelaskan kegagalannya kepada orang tuanya yang selalu berharap banyak padanya. Setiap kali ia menulis surat atau menelepon, ia hanya bisa bercerita tentang hari-hari yang datar dan pekerjaan yang tak memuaskan. Tanpa sadar, ia mulai menghindari panggilan ibu atau ayah yang selalu ingin tahu kabarnya. Rasa malu semakin menyelubungi dirinya, seakan tak ada lagi yang bisa ia banggakan.
Pada suatu malam menjelang Lebaran, Adrian duduk sendiri di kamarnya, menatap ponsel di tangan. Sudah beberapa kali ia membaca pesan-pesan dari ibu dan ayah yang menanyakan kapan ia pulang. Ayah selalu mengingatkannya untuk tidak lupa membeli ketupat, sementara ibu menanyakan apakah ia sudah makan. Kata-kata itu terasa begitu hangat, namun juga begitu jauh.
Adrian memejamkan mata, merasakan perasaan hampa yang mencekam. Ia ingin sekali kembali ke rumah, ke pelukan ibu yang selalu menenangkan hatinya. Tetapi, malu. Malu sekali. Ia tak ingin pulang dengan tangan kosong. Tidak ada yang bisa ia bawa. Tidak ada yang bisa ia banggakan. Ketika ayah dan ibu menyambutnya, bagaimana ia akan melihat mata mereka yang penuh harapan? Apa yang bisa ia berikan selain kesedihan dan kegagalan?
Setelah berjam-jam bergulat dengan perasaan, akhirnya ia memutuskan untuk menelpon ibunya. Dengan hati yang berat, Adrian menekan tombol panggil.
“Ibu,” suara Adrian terdengar serak, seolah ada beban berat yang mengganggu tenggorokannya.
Di seberang sana, suara ibu terdengar begitu lembut. “Adrian, nak, sudah makan? Ibu masak opor ayam favoritmu, lho. Ayah juga sudah beli ketupat, tinggal nunggu kamu pulang saja.”
Adrian terdiam sejenak. Ada sesuatu yang menyesak di dadanya. “Ibu… aku… belum bisa pulang, Bu.”
“Ibu tahu, nak. Tapi kenapa, sayang? Kalau ada apa-apa, Ibu dan Ayah bisa bantu, kok. Jangan malu. Kami cuma ingin kamu pulang dan sehat,” jawab ibu dengan penuh kehangatan.
Airmata tiba-tiba saja jatuh tanpa bisa dibendung. Adrian menunduk, berusaha menyembunyikan isaknya. “Aku… aku merasa gagal, Bu. Aku tidak membawa apa-apa. Aku tidak sukses seperti yang kalian harapkan. Aku takut kalian kecewa.”
Terdengar hening sejenak, lalu ibu menjawab dengan suara penuh kelembutan, “Nak, kamu bukanlah kegagalan bagi Ibu dan Ayah. Kamu adalah anak kami yang paling berharga. Kami tidak pernah berharap kamu menjadi orang yang lebih dari apa yang sudah kamu capai. Yang kami inginkan hanyalah kebahagiaanmu, apapun itu. Pulanglah, sayang. Kami menunggumu.”
Adrian terdiam. Kata-kata itu mengalir begitu saja, menenangkan hatinya yang penuh kegelisahan. Selama ini, ia terlalu lama mendengarkan bisikan-bisikan dari orang luar yang tidak mengerti, terlalu lama khawatir dengan apa yang akan dipikirkan orang lain. Ibu dan ayahnya tidak pernah mempermasalahkan apakah ia sukses atau tidak. Mereka hanya ingin Adrian pulang. Mereka hanya ingin melihat anak mereka kembali, dalam keadaan sehat dan bahagia.
Dengan hati yang lebih tenang, Adrian akhirnya memutuskan untuk pulang. Meskipun tak ada yang bisa ia bawa selain dirinya sendiri, ia tahu, itu sudah cukup bagi orang tuanya. Pulang ke rumah, pulang untuk merasakan hangatnya pelukan ibu, adalah hal yang lebih berharga daripada apapun.
*****
Hari raya tiba. Adrian kembali ke kampung halamannya dengan langkah yang lebih ringan. Saat ia tiba di rumah, ibu langsung menyambutnya dengan pelukan yang hangat, seperti yang selalu ia ingat. “Kamu tidak pernah gagal, nak,” bisik ibu di telinganya. “Kami selalu bangga padamu.”
Adrian hanya bisa tersenyum, menahan air mata yang hampir jatuh lagi. Ia tahu, di rumah, ia selalu diterima apa adanya. Di tengah kegagalannya, ia merasa begitu dicintai. Seperti pelukan ibu yang selalu bisa menenangkan, keluarga adalah tempat yang paling indah untuk kembali.
Penulis: Albii
Editor: Rara Zarary