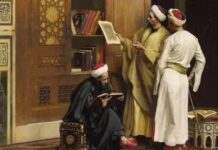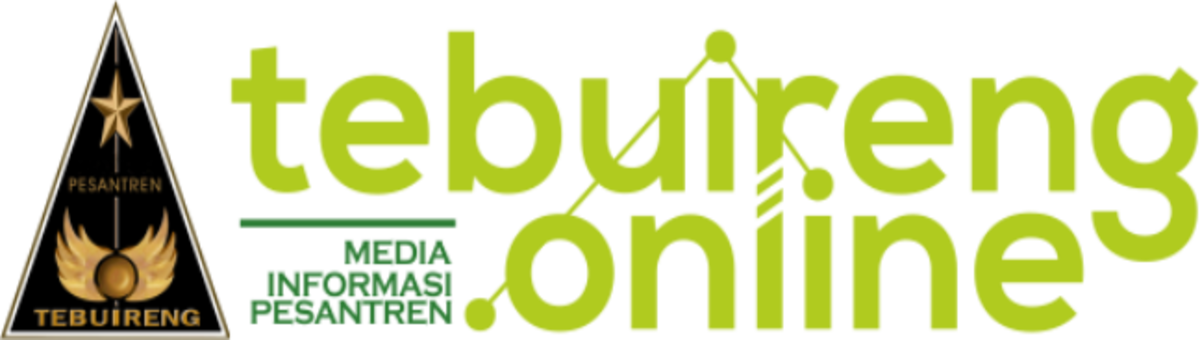Makam merupakan salah satu warisan budaya yang signifikan dari periode Islam, yang mencerminkan cara pandang dan pemikiran masyarakat pada masa itu (Latifundia, 2013; Ambary, 1998). Sebagai hasil dari aktivitas manusia, makam dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan (Soekmono, 1981).
Dari perspektif arsitektur dan filsafat, elemen-elemen utama makam, seperti nisan dan jirat, menunjukkan kesinambungan dengan periode sebelumnya, yaitu prasejarah dan Hindu. Dalam konteks ilmu bangunan, makam umumnya dibangun dengan material batu andesit, batu kapur, tuffa dan kayu yang memiliki dua bagian disebut jirat dan nisan. Untuk individu yang memiliki kedudukan penting, sering kali di atas jirat dibangun struktur tambahan yang disebut cungkup atau kubah (Latifundia, 2013; Rovina, et.al, 2022).
Makam tersebar luas di berbagai wilayah di Indonesia. Di Jawa, bangunan makam yang mencerminkan seni arsitektur bercorak Islam dapat ditemukan di banyak lokasi. Makam-makam yang berasal dari awal penyebaran Islam di Jawa dapat dijumpai baik di daerah pesisir utara maupun di pedalaman Jawa (Novida Abbas, 1984). Salah satu daerah pedalaman Jawa yang kaya akan peninggalan makam kuno dari masa Islam adalah Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.
Baki merupakan salah satu daerah yang menyimpan banyak koleksi makam kuno pada era Islam. Salah satu makam kuno tersebut terletak di Dukuh Butuh, Desa Gedongan, yang dikenal oleh masyarakat setempat sebagai makam sentanan. Menurut penuturan warga sekitar, makam ini merupakan tempat peristirahatan Kyai Benowo dan Kyai Benawi, dua tokoh yang hidup pada masa Pajang.
Deskripsi Makam Sentanan
Makam sentanan terletak di tengah-tengah pemukiman penduduk. Berdasarkan cerita dari warga, dahulu makam ini memiliki area yang cukup luas, dikelilingi oleh pagar tembok yang terbuat dari bata merah, serta dilengkapi dengan dua gapura setinggi pundak orang dewasa di pintu masuknya.
Namun, akibat faktor alam dan pembangunan, lahan makam sentanan mengalami penyempitan. Saat ini, hanya tersisa makam Kyai Benowo dan Benawi, beserta beberapa makam kuno lainnya. Di dalam kompleks makam, terdapat pohon cemara (casuarinaceae), jambu air (syzygium aqueum), dan ketos (protium javanicum burm) yang menambah nuansa keramat tempat ini. Di sekitar kompleks makam juga terlihat sisa-sisa bata merah yang merupakan bekas pagar tembok dan gapura.
Dari segi orientasi, makam sentanan menghadap ke arah utara-selatan, yang menunjukkan bahwa ini adalah makam Islam. Jirat dan nisan di kompleks makam sebagian besar dalam kondisi rusak dan tidak berada pada tempatnya. Hanya beberapa makam yang jirat dan nisannya masih utuh dan asli. Bahan yang digunakan untuk jirat di kompleks ini terdiri dari tiga jenis, yaitu batu andesit, kapur, dan bata merah, sedangkan nisan hanya terbuat dari batu andesit dan kapur.
Nuansa Pajang dan Mataram Islam
Makam Sentanan adalah sebuah kompleks pemakaman yang tidak memiliki identitas jelas. Tidak terdapat inskripsi atau epitaf yang mencantumkan nama, status, tanggal lahir, maupun waktu kematian, yang biasanya ada pada makam-makam Islam lainnya (M. Yaser Arafat, 2021). Namun, di antara sejumlah makam yang ada, terdapat dua makam yang berada di posisi yang dianggap istimewa, di mana masyarakat setempat meyakini bahwa kedua makam tersebut adalah milik Kyai Benowo dan Kyai Benawi.
Dalam tradisi penempatan makam di Jawa, tokoh yang dihormati biasanya diletakkan di bagian tengah, deret paling depan dan arah barat laut kompleks pemakaman, atau jika tidak, mereka akan ditempatkan di lokasi yang lebih tinggi. Kedua makam ini dianggap istimewa karena terletak di bagian paling depan sebelah timur, yang mungkin menunjukkan bahwa mereka adalah tokoh penting atau terhormat pada masa itu.
Makam tokoh ini memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan makam-makam lainnya di kompleks tersebut. Jiratnya terbuat dari susunan bata merah yang cukup besar, sementara nisannya terbuat dari batu andesit. Di sekitar makam kedua tokoh ini, ditemukan bata merah kuno yang merupakan sisa dari pagar tembok dan gapura yang dibangun khusus untuk mengelilingi makam tersebut.
Selain terletak di posisi paling depan dan memiliki ukuran jirat yang besar, menurut pandangan kelompok penggiat nisan kuno, nisan pada kedua makam ini dianggap sebagai nisan sepuh bergaya Demak-Pajang atau masa transisi dari Pajang ke Mataram Islam. Di sebelah barat kedua makam ini, terdapat berbagai bentuk batu nisan yang cukup beragam, mirip dengan model nisan-nisan kuno dari era Mataram Islam, khususnya pada akhir abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-18.
Indikasi Makam Tokoh dan Pemukiman Penduduk
Secara fisik, bentuk makam Sentanan menunjukkan bahwa ini kemungkinan adalah makam tokoh penting atau terhormat yang hidup sekitar pertengahan abad ke-16 hingga akhir abad ke-16. Hal ini dapat dilihat dari pola penempatan dan bentuk nisan pada kedua makam dalam kompleks tersebut. Selain itu, tidak dapat diabaikan bahwa makam-makam di sebelah barat kedua tokoh tersebut mungkin adalah para murid atau pengikut mereka.
Makam Sentanan kemungkinan besar memiliki kesamaan dengan makam-makam kuno Islam lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa nisan-nisan yang terdapat di makam Sentanan, kecuali untuk dua makam tokoh yang dikenal, kemungkinan hanya merupakan nisan masyarakat yang hidup antara akhir abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-18.
Berdasarkan kondisi dan letak makam Sentanan, dapat disimpulkan bahwa kompleks makam ini terletak cukup jauh dari daerah Pajang. Pada abad ke-16, Pajang merupakan pusat pemerintahan, baik saat berstatus sebagai bawahan Demak maupun ketika menjadi Kasultanan. Sekitar akhir abad ke-16, Pajang beralih status menjadi daerah bawahan Mataram Islam.
Jarak antara makam Sentanan dan Pajang diperkirakan sekitar 7 km. Saat ini, jarak tersebut terasa dekat berkat kemudahan akses dan transportasi yang tersedia. Namun, 500 hingga 300 tahun yang lalu, jarak tersebut mungkin dianggap cukup jauh. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah makam Sentanan mungkin merupakan kawasan pinggiran. Dengan demikian, keberadaan makam Sentanan dapat dianggap sebagai indikasi adanya pemukiman kuno di daerah pinggiran Pajang pada masa itu (Chawari, 2010).
Penutup
Makam sentanan merupakan representasi budaya serta karya seni yang dihasilkan oleh manusia pada zamannya. Di dalam kompleks makam ini, terdapat berbagai jenis dan variasi nisan serta jirat yang berasal dari pertengahan abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-18. Menurut cerita masyarakat setempat, makam ini diyakini sebagai tempat peristirahatan Kyai Benowo dan Benawi, dua tokoh yang hidup pada masa Pajang.
Meskipun identitas kedua tokoh tersebut belum terungkap secara historis dan tetap menjadi misteri, analisis terhadap pola penempatan, ukuran jirat, serta bentuk nisan pada kedua makam yang terletak di area yang dikelilingi oleh reruntuhan bata merah dan pepohonan cemara, ketos, serta jambu air menunjukkan indikasi kuat bahwa kompleks makam ini merupakan tempat peristirahatan bagi individu yang memiliki kedudukan penting atau terhormat pada periode pertengahan hingga akhir abad ke-16.
Demikian pula, makam-makam lain yang ada disebelah barat makam utama, mungkin merupakan kerabat atau pengikut dari tokoh tersebut. Selain itu, ada kemungkinan bahwa makam-makam ini juga menjadi tempat peristirahatan bagi penduduk umum yang tinggal di sekitar wilayah tersebut pada periode antara akhir abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-18. Wallahualam.
Sumber
Hasan Muarif Ambary, 1998, Menemukan Peradaban: Arkeologi dan Islam di Indonesia, Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional
Soekmono, 1981, Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia, Yogyakarta: Kanisius
Jurnal
Effie Latifundia, “Makna Penataan Peletakan Makam Kuna di Tepi Sungai Cirende Kecamatan Sukadana-Ciamis”, Jurnal Purbawidya, Volume 2, Nomor2, Tahun 2013. Diakses pada tanggal 06 Februari 2025
Muhammad Chawari, “Kompleks Makam Kuna di Desa Loram Kulon Posisi dan Kronologi Situs Dalam Kerangka Sejarah Kota Kudus”, Jurnal Berkala Arkeologi, Volume 30, Nomor 2, Tahun 2010. Diakses pada tanggal 05 Februari 2025
Yaser Arafat, “Makam Keramat Datuk Tongah: Pembacaan Etnografis Akademisi Pelaku Ziarah”, Jurnal Sejarah Peradaban Islam, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2021. Diakses pada tanggal 05 Februari 2025
Novida Abbas, “Catatan Singkat Mengenai Kompleks Makam Banyusumurup Imogiri”, Jurnal Berkala Arkeologi, Volume 5, Nomor 2, Tahun 1984. Diakses pada tanggal 05 Februari 2025
Rovina, dkk, “Identifikasi Kompleks Makam Lambuto di Desa Lalonggombu Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan, Jurnal Penelitian Arkeologi, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2022. Diakses pada 06 Februari 2025
Penulis: Faisal Muhammad Safii