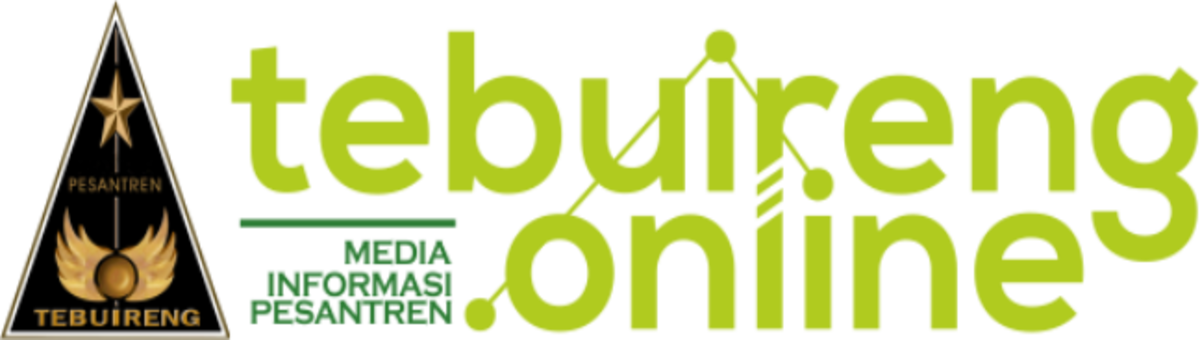Dalam ranah tasawuf pengalaman mistis para sufi cenderung bersifat batiniah dan personal sehingga sulit untuk disampaikan kepada orang lain. Oleh karena itu, pengalaman mistis pada dasarnya terkesan tidak rasional. Dengan demikian, untuk memahami hakikat pengalaman mistis tersebut, seseorang perlu mengalaminya secara langsung.[1] Kajian tentang eksistensi manusia selalu menarik, tidak hanya dalam bidang filsafat, psikologi, atau tasawuf. Studi tentang manusia terus berkembang seiring perkembangan ilmu pengetahuan. Studi tentang manusia adalah sebuah misteri yang belum pernah sepenuhnya terpecahkan,[2]
Manusia akan menjadi objek material setiap bidang ilmu. Manusia adalah makhluk yang terintegrasi dari unsur-unsur jasmani dan ruhani, dan dari kombinasi kedua unsur ini, manusia muncul dalam bentuk yang sempurna.[3] Pemikiran para tokoh sufi dalam studi tasawuf sangat beragam dan masing-masing memiliki ciri khas tersendiri, meskipun tujuannya tetap sama, yaitu menuju al-Haq (Allah SWT). Contohnya Ibnu Arabi dengan konsep wahdat al-wujud, al-Hallaj dengan konsep hulul, Rabi’ah al-Adawiyah dengan konsep mahabbah, dan masih banyak lagi. Selain mereka, ada seorang tokoh sufi yang pemikirannya sangat gemilang dan terkenal, yaitu Imam al-Ghazali, yang dijuluki Hujjatul Islam.[4]
Biografi Ibnu Arabi
Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah al-Hatimi,[5] yang kemudian lebih dikenal sebagai Ibn ‘Arabi. Ia dilahirkan di Murcia, Spanyol, pada hari Senin, 17 Ramadhan 560 H atau 27 Juli 1165 M, saat Andalusia mengalami masa perkembangan. Ayahnya berasal dari keluarga Arab, sedangkan ibunya dari keluarga Berber. Ayah Ibnu Arabi merupakan bagian dari tentara pengawal pribadi Sultan Almohad dan seorang ahli fiqih serta hadits yang juga mendalami tasawuf. Hatim al-Ta’i, leluhurnya, diakui sebagai teladan utama dalam kesatriaan Arab sebelum masa Nabi Muhammad. Keluarga Ibnu Arabi sangat menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan budi pekerti yang luhur. Dikisahkan bahwa Hatim sangat dermawan, bahkan sampai mengutamakan orang lain di atas dirinya sendiri, mengikuti jejak ibunya yang juga sangat dermawan.[6]
Ibn Arabi adalah salah satu tokoh dalam tasawuf falsafi atau mistis yang dikenal sangat kontroversial sepanjang sejarah, dengan banyak pihak yang mengaguminya sekaligus mengkritiknya.[7] Tasawuf falsafi adalah ajaran tasawuf yang menggunakan pendekatan rasional atau filosofis untuk mengenal Tuhan (makrifat), hingga mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tidak hanya sebatas makrifatullah (mengenal Tuhan), tasawuf ini juga mencakup konsep wihdatul wujud (kesatuan wujud). Dengan kata lain, tasawuf falsafi diperkaya oleh pemikiran-pemikiran filsafat. Pendekatan yang digunakan dalam tasawuf falsafi berbeda dengan tasawuf sunni atau salafi. Jika tasawuf sunni dan salafi lebih berfokus pada aspek praktis, tasawuf falsafi menitikberatkan pada aspek teoritis. Oleh karena itu, konsep-konsep dalam tasawuf falsafi lebih mengutamakan penggunaan akal dan pendekatan filosofis, yang sering kali sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi orang awam, atau bahkan dianggap hampir tidak mungkin.[8]
Konsep Wahdatul Wujud Hingga Insan Kamil Ibnu Arabi
Pembahasan mengenai paham wahdat al-wujud (kesatuan wujud) mencakup keyakinan bahwa manusia dapat mencapai penyatuan dengan Tuhan. Paham ini didasarkan pada konsep tentang yang satu (al-wahid) dan yang banyak (al-katsir), yang oleh kaum sufi dimulai dari gagasan wahdat al-wujud sebagai landasan filosofis untuk memahami Tuhan dalam hubungannya dengan alam semesta. Tuhan hanya dapat dipahami melalui penggabungan dua sifat yang saling bertentangan dalam diri-Nya. Hakikat wujud sejati hanyalah satu, yaitu Tuhan (al-Haq). Meskipun wujud-Nya satu, Tuhan memanifestasikan Diri-Nya di alam semesta dalam berbagai bentuk yang tak terbatas. Jika dikaitkan dengan Nur Muhammad, konsep wahdat al-adyan menurut Ibn ‘Arabi bersumber dari teorinya tentang “manusia sempurna” (al-insan al-kamil) atau hakikat Muhammad (al-haqiqah al-Muhammadiyyah).[9]
Wahdat al-wujud merupakan sebuah teori yang menyatakan bahwa keberadaan sejati hanya satu yaitu keberadaan Allah SWT. Tidak ada keberadaan yang benar-benar nyata selain keberadaan-Nya. Segala sesuatu yang terlihat oleh indra kita selain Allah SWT dianggap tidak nyata dan hanyalah ilusi yang muncul akibat keterbatasan akal manusia.[10] Maksudnya adalah konsep yang menyatakan bahwa hanya ada satu wujud, yaitu Allah Ta’ala, dan seluruh alam semesta adalah manifestasi dari wujud tersebut. Wujud Yang Satu ini mencakup segala fenomena yang ada dan menjadi sumber daya akal yang menerangi seluruh alam semesta. Sebagai sumber kosmos yang mengatur alam semesta, Wujud Yang Satu ini juga disebut jiwa universal. Ia menampakkan perbuatannya pada setiap makhluk (mikro) di alam semesta, sehingga disebut tubuh universal. Jika dilihat dari sifatnya sebagai inti yang mengarahkan seluruh bentuk kejadian, ia disebut al-Haba’. Secara ringkas, wahdat al-wujud menyatakan bahwa “la maujuda illa al-wujud al-wahid”, yang berarti “Tidak ada yang maujud selain wujud yang Esa.” Meski wujud yang Esa ini tampak beragam dalam bentuk ta’ayyunat, keberagaman tersebut tidak mengubah kesatuan hakikatnya, sama seperti keberagaman individu manusia tidak membuat hakikat manusia menjadi berbilang.
Kehadiran konsep wahdatul wujud sebagai penjabaran praktis dari pandangan pantheisme mengimplikasikan bahwa Tuhan (al-Khaliq) ada dalam segala ciptaan-Nya (al-Makhluq). Melihat konsep pantheisme dari sudut pandang historis, Frans Magnis-Suseno menjelaskan bahwa pantheisme adalah pandangan filsafat yang menyatakan adanya persatuan identitas antara yang diciptakan dengan Pencipta. Munculnya pandangan pantheisme dengan segala paradigma imanen yang ada di dalamnya, dalam memahami hubungan antara ciptaan dan Pencipta, berfungsi sebagai antitesis terhadap munculnya pandangan atheisme yang pesimis terhadap eksistensi Tuhan, dengan pantheisme menegaskan bahwa Tuhan ada dalam segala ciptaan-Nya.[11]
Manifestai Wujud yang Mutlak menurut Ibn Arabi
Tiga tingkatan yang dijelaskan oleh Ibn Arabi dalam menunjukkan manifestasi wujud yang mutlak adalah Ahadiyah (tingkat tertinggi), Wahidiyah, dan Tajalli Syuhudi (Rofi’ie, 2013). Berikut penjelasan masing-masing tingkatan:
- Ahadiyah: Pada tingkat ini, wujud adalah Zat murni yang tampak dalam keberadaan-Nya. Bersifat absolut dan mutlak, tanpa nama atau sifat. Manusia biasa belum dapat mencapai tingkat ini karena terbatas oleh ruang dan waktu. Satu-satunya cara untuk memahami Allah di tingkat ini adalah melalui teologi negatif, yaitu dengan meniadakan segala pemikiran tentang-Nya.
- Wahidiyah: Di tingkat ini, Zat Allah menampakkan diri melalui nama dan sifat-Nya, yang identik dengan Zat itu sendiri. Allah memperkenalkan diri-Nya melalui asma al-husna, yaitu nama-nama yang menunjukkan sifat-sifat-Nya. Artinya, Allah memperkenalkan diri melalui tindakan-Nya yang tercermin dalam nama dan sifat-Nya, sebagaimana yang terdapat dalam asmaul husna yang mendefinisikan-Nya.
- Tajalli Syuhudi: Pada tingkatan ini, nama dan sifat Allah tampak secara empiris dalam kenyataan yang dapat disaksikan oleh alam semesta. Melalui perkataan “Kun”, kenyataan itu menjadi nyata dan dapat dirasakan oleh indera. Artinya, manifestasi Allah dalam bentuk nyata dari nama dan sifat-Nya bisa dirasakan oleh panca indera.[12]
Selanjutnya, Insan kamil merupakan manusia yang ideal dalam hal eksistensi dan pengetahuannya. Kesempurnaan eksistensinya terletak pada kenyataan bahwa ia adalah manifestasi sempurna dari citra Tuhan, yang mencerminkan nama-nama dan sifat-sifat Tuhan secara menyeluruh. Sementara itu, kesempurnaan pengetahuannya dicapai melalui tingkat kesadaran tertinggi, yaitu kesadaran akan kesatuan esensinya dengan Tuhan yang dikenal sebagai makrifat.[13] Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu ‘Arabi dalam teori emanasinya, yaitu bagaimana suatu wujud yang mumkin berasal dari Dzat yang wajib al-wujud, manusia kamil adalah kenyataan yang tidak dapat dilepaskan dari ajaran Nur Muhammad.[14]
Pada dasarnya, kesempurnaan insan kamil muncul karena Tuhan menampakkan diri secara sempurna dalam dirinya melalui hakikat Muhammad (al-Haqiqah al-Muhammadiyah).[15] Manusia yang dimaksud oleh Ibnu ‘Arabi dalam ungkapan tersebut merujuk pada konsep pemikirannya tentang manusia sempurna (insan al-kamil). Memang benar bahwa manusia berfungsi sebagai perantara antara alam dan Tuhan, agar Tuhan dapat dikenal, dan dengan demikian, manusia menjadi sebab adanya alam. Tujuan utama penciptaan alam dan seluruh isinya adalah untuk memungkinkan Tuhan dikenal.
Oleh karena itu, setiap makhluk adalah tempat manifestasi Tuhan, dan manusia, terutama manusia sempurna, menjadi tempat manifestasi Tuhan secara sempurna. Hanya manusia sempurnalah yang mampu menerima anugerah nama dan sifat-sifat Tuhan. Ibn ‘Arabi menyatakan bahwa alam adalah cermin Tuhan. Sementara alam tanpa manusia bagaikan cermin yang buram, yang tidak dapat memantulkan gambarnya dengan jelas. Gambar Tuhan tidak akan terlihat dengan jelas dalam cermin seperti itu. Oleh karena itu, perintah Tuhan mengharuskan agar cermin (alam) itu menjadi jernih, sehingga dapat memantulkan gambaran-Nya dengan sempurna.
Kesimpulan
Artinya konsep pemahaman tasawuf yang dikembangkan oleh Ibnu Arabi merupakan perpaduan antara kekuatan akal dan kehalusan hati. Corak pemikiran ini masuk dalam kategori tasawuf falsafi, karena memuat unsur-unsur filsafat yang mendalam dan abstrak. Untuk itu, memahami ajaran-ajaran tasawuf Ibnu Arabi secara utuh diperlukan sinergi yang selaras antara nalar rasional, daya pikir kritis, dan kepekaan spiritual. Tanpa keseimbangan ini, pemahaman terhadap gagasan-gagasannya bisa menjadi kabur dan berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam menafsirkan makna yang ia sampaikan. Maka penting bagi pembaca untuk menyelami pola ajaran yang diperkenalkan oleh Ibnu Arabi dengan ketajaman analisis agar dapat menangkap esensi spiritual dan intelektual yang terkandung di dalamnya.
Baca Juga: Memahami Ilmu Tasawuf dan Tokoh Sufi Dunia
[1] Nurcholish Madjid, Islam: Doktrin & Peradaban (Gramedia pustaka utama, 2019).
[2] Yunasril Ali, Manusia Citra Ilahi: Pengembangan Konsep Insan Kamil Ibn Arabî Oleh al-Jîlî, Cet. 1 (Jakarta: Paramadina, 1997).
[3] M. Quraish Shihab, “Membumikan” Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Mizan Pustaka, 2007).
[4] Lidia Artika et al., “Biografi Tokoh Tasawuf Al-Ghazali,” Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Kebudayaan 1, no. 2 (2023): 29–55.
[5] E. J. Brill, E.J. Brill’s First Encyclopaedia of Islam: 1913-1936. S – Ṭaiba (BRILL, 1993).
[6] AKBARLITA ARI KURNIA, “PENDIDIKAN INTEGRAL BERBASIS TAUHID DALAM MEMBENTUK INSAN KAMIL,” accessed December 23, 2024, https://core.ac.uk/download/pdf/227535006.pdf.
[7] Eka Ismaya Indra Purnamanita, “Kajian Tasawuf Falsafi Mengenai Wahdat Al-Wujud Ibn Arabi (1165-1243 M),” TIN: Terapan Informatika Nusantara 4, no. 6 (2023): 345–49.
[8] Alwi Shihab, Islam sufistik: “Islam pertama” dan pengaruhnya hingga kini di Indonesia (Mizan, 2001).
[9] Adenan Adenan and Tondi Nasution, “Wahdat Al-Wujud Dan Implikasinya Terhadap Insan Kamil,” Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam 2, no. 1 (2020), https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/7609.
[10] Abd Al-Jalil Ibn Abd Al and Karim Salim, “Wahdat Al-Wujud Inda Ibn Arabi, T 638 H/1240 M,” 2002, https://philpapers.org/rec/SALWAI-2.
[11] Franz Magnis-Suseno S.J, Menalar Tuhan (PT Kanisius, n.d.).
[12] Eka Ismaya Indra Purnamanita, “Kajian Tasawuf Falsafi Mengenai Wahdat Al-Wujud Ibn Arabi (1165-1243 M),” TIN: Terapan Informatika Nusantara 4, no. 6 (2023): 345–49.
[13] Akilah Mahmud, “Insan Kamil Perspektif Ibnu Arabi,” Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman 9, no. 2 (2014): 33–45.
[14] Atang Abdul Hakim and Beni Ahmad Saebani, “Filsafat Umum,” Bandung: Pustaka Setia, 2008, https://www.researchgate.net/profile/Lukmanul-Hakim-24/publication/372241727_Lukmanul_Hakim_FILSAFAT_UMUM_Upaya_untuk_Mengenal_Memahami_Filsafat_Lebih_Awal/links/64ac290d8de7ed28ba8a03d3/Lukmanul-Hakim-FILSAFAT-UMUM-Upaya-untuk-Mengenal-Memahami-Filsafat-Lebih-Awal.pdf.
[15] Adenan Adenan and Tondi Nasution, “Wahdat Al-Wujud Dan Implikasinya Terhadap Insan Kamil,” Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam 2, no. 1 (2020), https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/7609.
Penulis: Ahmad Firdaus, Mahasantri M2 Mahad Aly Hasyim Asy’ari Tebuireng
Editor: Sutan Alam Budi