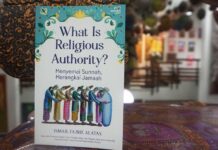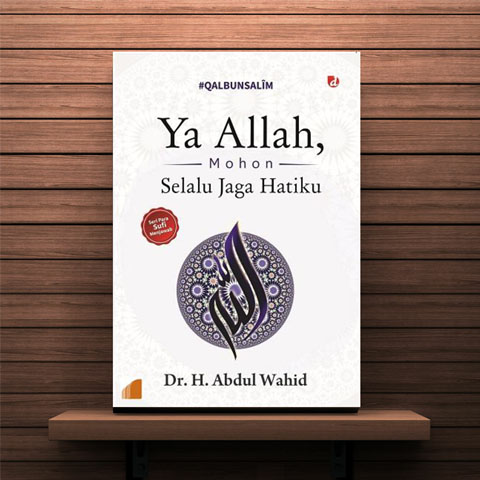
Oleh: Muhammad Faiz As.*
Judul Buku: Ya Allah Mohon Selalu Jaga Hatiku
Penulis: Dr. Abdul Wahid, M.Ag.
Cetakan: I, Maret 2018
Penerbit: Diva Press
Tebal: 416 Halaman
ISBN: 978-602-391-528-6
Menurut telaah Imam al-Ghazali, hati ibarat raja dan anggota tubuh lain adalah pasukan yang senantiasa manut pada titah rajanya. Beliau mendudukkan hati sebagai sentral yang mengorganisir segenap jaringan tubuh, baik fisik atau pun batin. Jika dicerna lebih jauh, pendapat Imam al-Ghazali ini berkelit kelindan dengan sabda Nabi bahwa hati menjadi tolok ukur baik dan buruknya kualitas seluruh anggota tubuh.
Melalui hati, manusia dapat mencapai dan merasakan kedekatan dengan Allah Swt. Bagi seorang sufi, penjernihan hati dari beragam anasir dosa adalah suatu kemutlakan. Sebab hati yang masih sesak dengan dosa mustahil bisa menjembatani seorang salik bersua dengan rabbnya. Bahkan jika dibiakkan dan dibiarkan hingga menumpuk di dasar hati, dosa-dosa tersebut berpotensi memalingkannya dari Allah Swt.
Sesuai judulnya: “Ya Allah Mohon Selalu Jaga Hatiku”, buah tangan Dr. Abdul Wahid, M.Ag. ini adalah semacam ihktiar interpersonal, antar hamba dengan hamba, untuk bersama-sama menjaga kesucian hati dan ketaatan kepada Allah Swt. Karena seperti buku sebelumnya (Terhubung dengan Tuhan), buku ke-2 dari seri “Para Sufi Menjawab” ini adalah jawaban dari aneka pertanyaan yang dilayangkan kepada penulis oleh berbagai kalangan berkaitan dengan problematik tazkiyatun nafsi, yang lebih dikerucutkan pada taubat dan zuhud.
Di pertanyaan pertama soal taubat, ada seorang bernama Man Toyo yang ceritanya tengah dilanda skeptisme tentang diterima atau tidaknya taubat yang dia lakukan lantaran dosanya yang terlalu berjibun. Dari kacamata penulis, persoalan demikian adalah suatu keberuntungan bagi penanya. Karena ia masih diberi kesadaran bertaubat oleh Allah tanpa melalui teguran keras setelah sekian banyak dosa yang diperbuat. Hal tersebut sekaligus mengejawantahkan kasih sayang Allah dan mengisyaratkan bahwa ampunan-Nya yang jauh lebih akbar dari dosa hamba-Nya, seberapapun banyaknya.
Sayangnya, kita sebagai manusia seringkali masih termakan bujuk rayu setan untuk kembali mengulangi dosa pasca pertaubatan. Hingga seakan-akan kita mengkhianati “ikrar kembali” kepada Allah dan menipu-Nya dengan deraian air mata dusta. Kasus ini dialami oleh seorang penanya bernama Muhammad Farid Majdi yang mendambakan pegangan yang teguh agar tidak terus-menerus dipermainkan setan untuk kembali terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan dan dosa.
Sebagai jalan keluar, Dr. Abdul Wahid menyarankan 5 hal agar senantiasa istiqamah dalam taubat. Pertama: selalu ingat dampak negatif dosa dan maksiat, sebagaimana perintah Allah yang selalu berdampak positif terhadap pelakunya. Kedua: merasakan semua yang dilakukan ada rekam jejaknya. Ketiga: menyadari datangnya kematian. Keempat: menghindari teman yang tidak baik dan terakhir: meneladani sikap para nabi, sahabat dan sufi (hlm. 207-232).
Pada babak kedua buku ini, Dr. Abdul Wahid menguliti dalam-dalam makna zuhud dan implementasinya. Dalam berbagai literatur, term zuhud akrab didefinisikan sebagai rasa “tidak suka” atau tidak mencintai sesuatu yang bersifat materi, semacam jabatan dan harta kekayaan. Sebagai sebuah rasa, zuhud berpusat dalam diri kita yang dalam tasawuf disebut al-qalb. Sementara itu, para sufi, seperti Syekh al-Bouthi seringkali mengartikan “materi” atau “duniawi” secara ekstrem sebagai “segala sesuatu selain Allah”. Pemaknaan demikian berimplikasi pada pengaplikasian zuhud yang cenderung sulit dan berat.
Selanjutnya, muncul pertanyaan dari seorang Ahmad Mubarak yang sedang mengalami ambigu soal mana hidup yang lebih baik, miskin atau kaya? Menurutnya orang miskin menempati kedudukan yang istimewa dalam Islam. Namun di sisi lain muncul asumsi bahwa kekayaan dapat menjadi instrumen untuk melakukan amal yang berpahala besar, seperti bersedekah dan naik haji.
Gagasan awal yang disampaikan penulis untuk menjawab persoalan ini adalah melegitimasi segenap usaha untuk manjadi kaya dengan tujuan orang tersebut mampu melakukan ibadah semaksimal mungkin dengan memanfaatkan kekayaannya, baik dalam ranah personal-individual atau komunal-sosial. Gagasan ini selaras dengan ajaran neo-sufisme, yang mencitrakan dunia sebagai sarana bagi seorang sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan malah mengalienasikan diri darinya.
Namun di sisi lain penulis juga membabarkan bahwa tidak semua orang kaya bersedia menghibahkan hartanya yang semula berupa aset ekonomi pribadi menjadi aset sosial (dalam arti menolong mereka yang membutuhkan). Karena bagaimana pun kekayaan adalah ujian yang sangat menggilakan dan melenakan manusia. Siapapun yang tidak mampu menggaris batas kecukupan, niscaya akan terbawa arus keserakahan yang malah semakin menyengsarakan sesamanya.
Secara keseluruhan, jawaban-jawaban yang disajikan penulis diramu dengan pembahasan yang sederhana dan komprehensif. Mekanisme tanya-jawab yang digunakan pun membuat buku ini lebih komunikatif dengan pembacanya. Di tengah zaman yang dihempas krisis di setiap lininya, lebih-lebih dalam area spiritual, kehadiran buku setebal 416 halaman ini dapat menjadi oase yang menyegarkan guna meraih qalbun salim, yang diistilahkan dalam epilog buku ini sebagai hati yang jernih dan terselematkan dari berbagai penyakit. Semoga! Salam Literasi!
*Pengurus Perpustakaan Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-guluk, Sumenep, Madura.