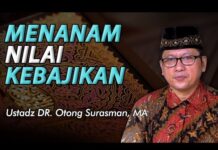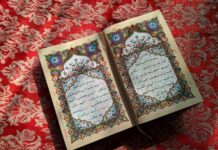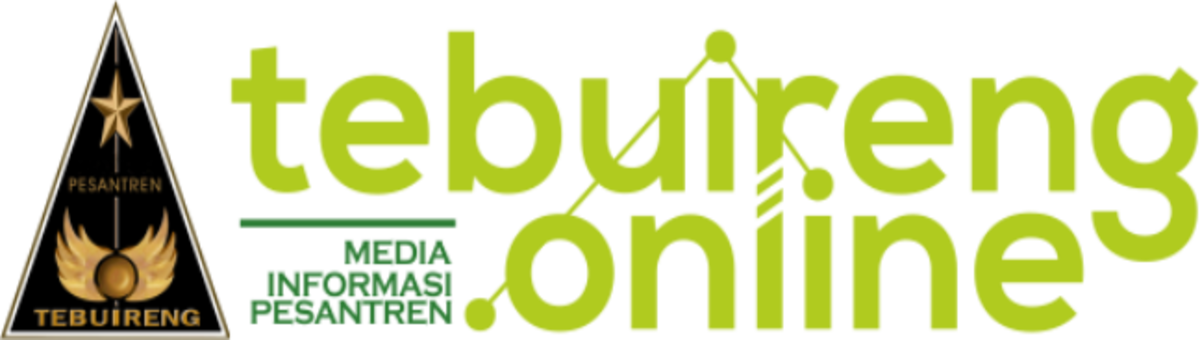Dalam kajian istinbath al-ahkam, kita kerap kali dihadapkan pada sebuah kenyataan yang tidak mudah: dalil-dalil syariat yang menjadi rujukan hukum ternyata tampak bertentangan satu sama lain. Kondisi ini tentu menuntut kecermatan dan ketelitian dalam memahami teks-teks tersebut. Dari sinilah, para ulama tidak tinggal diam. Mereka merespons tantangan ini dengan melahirkan berbagai teori dan metode kompromi, yang dikenal dengan istilah taufiq, untuk mengharmonisasikan dalil-dalil yang tampak saling bertentangan.
Namun, terkadang tidak semua dalil-dalil syariat yang tampak bertentangan dapat dikompromikan atau dikompilasikan satu sama lain. Dalam kondisi seperti ini, para ulama tidak berhenti pada upaya taufiq (kompromi) semata, melainkan mengembangkan teori-teori lain sebagai solusi dalam menghadapi pertentangan dalil-dalil tersebut. Salah satu teori yang muncul adalah naskh (penghapusan hukum), yaitu ketika salah satu dalil dinyatakan telah dihapus hukumnya oleh dalil lain yang datang setelahnya. Teori ini digunakan jika tidak memungkinkan dilakukan kompromi secara makna, dan ada indikasi kuat bahwa dalil yang satu datang lebih dahulu daripada yang lain, serta terdapat dalil yang menunjukkan adanya penghapusan tersebut.[1] Selain itu, ulama juga menggunakan pendekatan tarjih, yaitu menguatkan salah satu dalil atas yang lainnya berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, seperti kekuatan sanad, keumuman penerapan, atau kesesuaian dengan kaidah-kaidah syar’i lainnya.[2]
Akan tetapi, apabila kita merenungkannya kembali dengan saksama, hampir tidak ditemukan dalil-dalil syariat yang bertentangan secara hakiki. Hal ini karena perbedaan yang tampak di antara dalil-dalil tersebut hanya bersifat lahiriah saja, sedangkan secara hakikat, dalil-dalil itu sebenarnya tidak saling bertentangan. KH. Ali Musthafa Yaqub dalam kitabnya mengatakan “sebagaimana ditegaskan oleh Imam Nawawi, pertentangan yang tampak antara satu hadis dengan hadis lain, atau antara hadis dengan Al-Quran, sejatinya hanyalah bersifat lahiriah dalam makna. Pada hakikatnya, tidak ada kontradiksi di antara keduanya karena keduanya berasal dari sumber yang sama, yakni wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta‘ala. Perbedaan yang muncul dalam pemahaman terhadap hadis sebenarnya bersifat relatif; bisa jadi suatu hadis dianggap bertentangan dengan Al-Quran, hadis lain, atau bahkan akal sehat oleh seseorang, namun tidak demikian menurut orang lain”.[3]
Ibnu Khuzaimah dikenal sebagai salah satu ulama yang paling cermat dan bijak dalam menangani persoalan perbedaan dalil. Ia bahkan pernah menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya dua hadis yang benar-benar saling bertentangan. Oleh karena itu, siapa saja yang menemukan dua hadis yang tampak bertolak belakang, dipersilakan membawanya kepadanya agar ia dapat menjelaskan cara untuk mengompromikan keduanya.”[4] Pernyataan KH. Ali Musthafa Yaqub ini juga didukung oleh Syekh Abdul Wahab Khalaf dalam kitabnya, beliau menyatakan:
فإن وجد نصان ظاهرهما التعارض وجب الاجتهاد في صرفهما عن هذا الظاهر، والوقوف على حقيقة المراد منهما تنزيها للشارع العليم الحكيم عن التناقض في تشريعه. فإن أمكن إزالة التعارض الظاهري بين النصين بالجمع والتوفيق بينهما، جميع بينهما وعمل بهما، وكان هذا بيانا؛ لأنه لا تعارض في الحقيقة بينهما.
Apabila ditemukan dua nash (teks syar’i) yang secara lahiriah tampak saling bertentangan, maka wajib dilakukan ijtihad untuk mengalihkan makna lahiriah tersebut dan mencari hakikat maksud sebenarnya dari kedua nash tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pensucian terhadap Syāri‘ (Pembuat syariat) Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana dari segala bentuk pertentangan dalam syariat-Nya. Jika memungkinkan untuk menghilangkan pertentangan lahiriah antara kedua nash dengan cara mengompromikan dan menggabungkan maknanya, maka keduanya dikompromikan dan diamalkan bersama. Dalam hal ini, kompromi tersebut merupakan bentuk penjelasan, karena pada hakikatnya tidak ada pertentangan di antara keduanya.
Melihat pernyataan KH. Ali Musthafa Yaqub dan Syekh Abdul Wahab Khalaf di atas, dapat disimpulkan bahwa teori nasikh-mansukh maupun teori tarjih nyaris tidak dapat diterapkan. Hal ini disebabkan karena kedua teori tersebut baru bisa digunakan apabila dua dalil yang tampak bertentangan secara lahiriah benar-benar tidak dapat dikompromikan. Selama masih memungkinkan untuk mengompromikan dalil-dalil yang secara zahir tampak bertentangan, maka tidak diperbolehkan langsung beranjak kepada penerapan teori nasikh-mansukh atau tarjih.[5] Pandangan ini juga sejalan dengan pernyataan Ibn Hazm yang meyakini bahwa tidak ada satu pun dalil syariat yang lebih unggul dari yang lain, karena seluruhnya bersumber dari Zat yang sama, yaitu Allah, Sang Pemberi wahyu. Oleh karena itu, apabila terdapat pertentangan secara lahiriah di antara dalil-dalil tersebut, maka menurut Ibn Hazm, hukumnya wajib untuk mengompromikan keduanya dan mengamalkannya sesuai dengan konteks masing-masing. Berikut adalah pernyataan beliau yang mendukung pandangan tersebut:
إذا تعارض الحديثان أو الآيتان أو الآية والحديث فيما يظن من لا يعلم ففرض على كل مسلم استعمال كل ذلك لأنه ليس بعض ذلك أولى بالاستعمال من بعض ولا حديث بأوجب من حديث آخر مثله ولا آية أولى بالطاعة لها من آية أخرى مثلها وكل من عند الله عز وجل وكل سواء في باب وجوب الطاعة والاستعمال ولا فرق
Apabila dua hadis, dua ayat, atau antara ayat dan hadis tampak bertentangan menurut dugaan orang yang tidak memiliki ilmu, maka wajib bagi setiap Muslim untuk tetap mengamalkan semuanya. Sebab, tidak ada satu bagian pun dari dalil-dalil itu yang lebih layak untuk diamalkan dibandingkan yang lain; tidak ada satu hadis yang lebih wajib ditaati dibandingkan hadis lain yang sejenis, dan tidak ada satu ayat pun yang lebih utama untuk dipatuhi daripada ayat lain yang sepadan. Semuanya berasal dari Allah ‘Azza wa Jalla, dan semuanya setara dalam hal kewajiban untuk ditaati dan diamalkan, tanpa ada perbedaan.[6]
Setelah mencermati pernyataan Ibn Hazm di atas, kita dapat mengambil benang merah bahwa setiap dalil memiliki konteks dan situasi tersendiri. Oleh karena itu, ketika terdapat dalil-dalil yang tampak bertentangan, tidak serta-merta salah satunya ditinggalkan. Sebaliknya, seluruh dalil tetap diamalkan sesuai dengan konteks masing-masing, tanpa harus menghapus (nasakh) atau mengunggulkan (tarjih) salah satunya secara mutlak.
Sebagai ilustrasi untuk menguatkan analisis penulis terhadap pandangan ulama yang telah disebutkan sebelumnya, akan disajikan satu contoh tentang perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait penerapan teori nasikh-mansukh terhadap ayat-ayat damai dalam Al-Qur’an. Salah satu ulama yang terkenal dalam hal ini adalah Ibnul ‘Arabi. Ia berpendapat bahwa seluruh ayat damai dalam Al-Qur’an yang jumlahnya mencapai 124 ayat telah dinaskh (dihapus hukumnya) oleh ayat as-saif, yakni Surah At-Taubah ayat 5.[7] Namun demikian, pandangan ini kemudian ditolak oleh sebagian ulama lain dengan alasan bahwa semua ayat Al-Quran yang tampaknya saling bertentangan sebenarnya dapat dikompromikan tanpa harus menetapkan adanya nasakh. Di antara ulama yang mengkritik pandangan Ibnul ‘Arabi ialah Al-Syatibhi, menurut beliau mayoritas klaim nasakh pada ayat-ayat Alquran setelah ditelusuri lebih lanjut ternyata tidak saling bertentangan dan masih mungkin dikompromikan (jam’u). Sementara prinisp lain menyatakan, tidak boleh menasakh teks-teks syariat bila di masih mungkin dikompromikan. Al-Syathibi menyatakan:
أن غالب ما ادعي فيه النسخ اذا تامل وجدته متنازعا فيه ومحتمل، وقريبا من التأويل بالجمع بين الدليلين على وجه من كون الثاني بيانا لمجمل او تخصيصا لعموم او تقييدا لمطلق وما اشبه ذلك من وجوه الجمع مع البقاء على الاصل من الاحكام في الاول والثاني. وقد اسقط ابن العربي من الناسخ والمنسوخ كثيرا بهذه الطريقة.
Sebagian besar klaim mengenai nasakh, jika dikaji lebih mendalam, ternyata tidak sepenuhnya dapat diterima karena masih memungkinkan untuk ditafsirkan dengan pendekatan lain. Pendekatan yang lebih tepat dalam banyak kasus justru adalah menakwil dan mengompromikan dua dalil dalam satu kerangka pemahaman. Misalnya, dalil kedua dapat dipahami sebagai penjelas atas ayat yang masih bersifat mujmal (umum dan belum terperinci), atau berfungsi sebagai pembatas ayat yang mutlak, atau sebagai pengecualian terhadap ayat yang bersifat umum. Semua bentuk ini merupakan metode kompromi yang memungkinkan kedua dalil tetap berlaku tanpa harus meniadakan salah satunya. Namun, dalam penerapan teori nasikh-mansukh, Ibn ‘Arabi sering kali tidak mengindahkan pendekatan kompromi semacam ini.[8]
Oleh karena itu, al-Zarkasyi dan al-Suyuthi menolak keras pandangan yang menyatakan bahwa ayat-ayat yang bernuansa damai telah dinasakh (dihapus hukumnya) oleh ayat-ayat yang berisi perintah perang. Menurut mereka, hubungan antara ayat-ayat tersebut bukanlah nasakh-mansukh, melainkan bersifat munsa’, yaitu masing-masing ayat diberlakukan sesuai dengan situasi dan kondisi yang relevan, bukan untuk saling me-nasakh. Dalam hal ini, al-Zarkasyi menegaskan bahwa:
وبهذا التحقيق تبين ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة بآية السيف وليست كذلك، بل هي من المنساء بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلة توجب ذلك الحكم. ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر وليس بنسخ إنما النسخ الإزالة حتى لا يجوز امتثاله أبدا.
“Dengan pembuktian ini menjadi jelas kelemahan pendapat banyak ulama tafsir yang mengklaim ayat-ayat yang menganjurkan perdamaian dinasakh dengan ayat perang, padahal tidak dinasakh, tetapi termasuk dalam teori munsa’. Yakni masing-masing perintah wajib dikerjakan dalam konteks tertentu karena suatu alasan yang mewajibkannya, lalu dengan ketiadaan alasan itu hukumnya menjadi berubah. Hal ini bukan nasakh. Nasakh adalah ketika suatu hukum dihilangkan secara totalitas sehingga tidak bisa diterapkan selamanya.”[9]
Berdasarkan teori munsa’, yang menekankan penerapan ayat-ayat sesuai dengan konteksnya, ayat-ayat tentang perang tidak dapat dianggap menasakh ayat-ayat yang menganjurkan perdamaian. Ayat-ayat perang diberlakukan dalam situasi konflik, seperti ketika terdapat ancaman atau serangan terhadap umat Islam. Sebaliknya, ayat-ayat damai tetap berlaku dalam kondisi damai, yaitu ketika pihak non-muslim tidak menunjukkan permusuhan atau terdapat perjanjian damai yang disepakati. Dengan demikian, klaim bahwa ayat-ayat damai telah dinasakh oleh ayat-ayat perang menjadi tidak relevan.
Dengan demikian, dalam kesimpulan akhirnya, penulis menegaskan bahwa hampir tidak ditemukan adanya dalil-dalil syar‘i yang benar-benar bertentangan secara hakiki sehingga menuntut penerapan teori nasikh-mansukh atau tarjih. Oleh karena itu, penggunaan konsep nasikh-mansukh maupun tarjih lebih tepat diposisikan sebagai solusi terakhir yang sangat jarang diperlukan. Sebab, kenyataannya, berbagai dalil yang secara lahiriah tampak bertentangan masih dapat dikompromikan melalui pendekatan kontekstual dan pemahaman yang integratif.
Baca Juga: Memahami Kontradiksi Hadis Batal Wudhu Sebab Menyentuh Kemaluan
[1] Mahmud bin Ahmad bin Mahmud Thahan al-Nu‘aymi, Taisir Mushthalah al-Hadits (Riyadh: Maktabah al-Ma‘arif li al-Nasyr wa al-Tauzi‘, cet. ke-10, 1425 H/2004 M). Hlm 72.
[2] Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad bin ‘Abdullah al-Syaukani al-Yamani, Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min ‘Ilm al-Ushul, (Damaskus – Kafr Batna: Dar al-Kitab al-‘Arabi, cet. ke-1, 1419 H/1999 M). Juz 22, Hlm 273.
[3] Ali Musthafa Yaqub, Turuq al-Sahihah Fi Fahmi al-Sunnah al-Nabawiyah, (Jakarta: Maktabah Darussunnah, 2016), Hlm 157.
[4] Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr As-Suyūṭī, Tadrīb ar-Rāwī fī Syarḥ Taqrīb an-Nawāwī, (Riyadh: Dār Ṭayyibah, tanpa tahun). Juz 2, Hlm 652.
[5] Ibn Rajab Al-Hanbali, Fath al-Bārī Syarh Shahīh al-Bukhārī, (Madinah: Maktabah al-Ghurabā’ al-Atsariyyah, 1996 M), Juz 6, Hlm 115.
[6] Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa‘id bin Hazm, Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah). Juz 2, Hlm 21.
[7] Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr As-Suyūṭī, Al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān, (Kairo: Al-Hay’ah al-Miṣriyyah al-‘Āmmah li al-Kitāb, 1394 H/1974 M), Juz 3, Hlm 78.
[8] Abū Isḥāq Ibrāhīm bin Mūsā al-Lakhmī al-Syāṭibī, Al-Muwāfaqāt (Dammam: Dār Ibn ‘Affān, cet. 1, 1417 H/1997 M). Juz 3, Hlm 340.
[9] Badruddin al-Zakasyi al-Syafi’i, al-Burhan fi Uham al-Quran, ( Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1957 M, cet 1), Juz 2, Hlm 42.
Penulis: Ma’sum Ahlul Choir, Mahasantri Marhalah Tsaniyah (M2) Ma’had Aly Hasyim Asy’ari