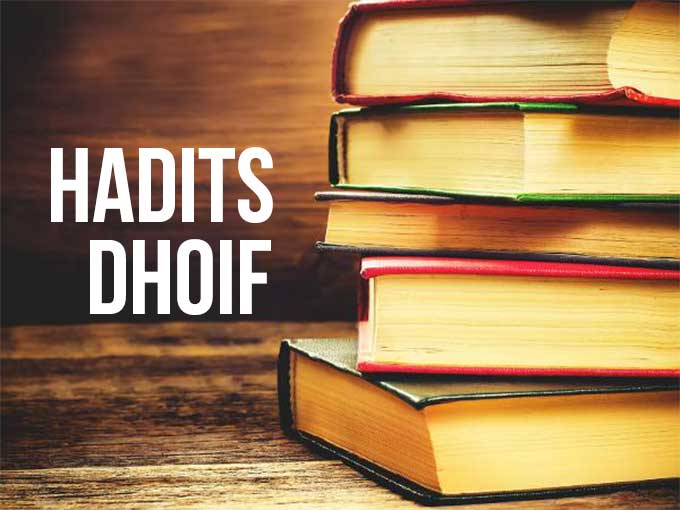Oleh: Nurdiansyah Fikri Alfani*
Dalam pembagian secara global, hadis bisa diklasifikasikan menjadi tiga yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Hadis sahih ialah hadis yang memenuhi beberapa kriteria di antaranya adalah bersambungnya sanad dari awal sampai akhir perawi, dipastikannya status ‘adil dan dhabit-nya rowi, dan tidak adanya syadz maupun ‘illat baik dalam sanad maupun matan hadis.
Bedanya dengan hadis hasan ialah biasanya dalam rantai periwayatan hadis ada sejumlah nama perawi hadis yang belum masuk kategori penilaian ‘adil (ta’dil) pada peringkat tertinggi, para ulama sepakat bahwa hadis sahih dan hasan bisa dipakai untuk pijakan penetapan hukum syar’i. Hal ini berbeda dengan hadis dho’if, banyak yang memperdebatkan apakah bisa dibuat sebagai pijakan hukum atau tidak, bahkan ada yang mengatakan bahwa hadis dho’if tidak bisa sama sekali untuk diamalkan,
Beberapa ulama ada yang masih mau menerima hadis dhoif sebagai pijakan hukum tetapi para ulama tersebut memberikan persyaratan yang sangat ketat mengenai hal ini. Di antaranya adalah an-Nawawi dalam kitab al-Adzkar-nya, beliau memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika akan mengamalkan hadis dho’if, berikut penjelasannya:
قال العلماءُ من المحدّثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويُستحبّ العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعاً . وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يُعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن
(الأذكار, أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 1\8)
“Para ulama dari golongan ahli hadis dan fikih berkata bahwa boleh dan disunnahkan beramal menggunakan hadis dho’if hanya untuk fadhoil a’mal (keutamaan amal), targhib (janji kebahagiaan di akhirat), tarhib (ancaman melakukan dosa) selagi ke-dho’if–annya tidak parah, adapun untuk hukum seperti halal haram maka hanya hadis sahih dan hasan yang boleh dijadikan pijakan.”
Lalu ada juga penjelasan dalam kitab Mughni al-Muhtaj karangan Imam Khatib Asy-Syirbini:
فَائِدَةٌ: شَرْطُ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ أَنْ لَا يَكُونَ شَدِيدَ الضَّعْفِ، وَأَنْ يَدْخُلَ تَحْتَ أَصْلٍ عَامٍّ، وَأَنْ لَا يُعْتَقَدَ سُنِّيَّتُهُ بِذَلِكَ الْحَدِيثِ
(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج, شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي 1\194)
Syarat mengamalkan hadis dhoif adalah apabila tidak sangat dhoif, kandungan hadis tersebut masih ada asalnya dalam prinsip umum islam, dan tidak meyakini kesunnahan tersebut berasal dari Rasulullah SAW.
Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari pendapat dua ulama tadi adalah kebolehan menggunakan hadis dho’if untuk diamalkan dengan syarat-syarat yang dipaparkan di atas. Oleh karena itu, kita sebagai golongan ahlusunnah wal jamaah atau kalangan warga NU (Nahdlatul Ulama) yang notebene sering beramal menggunakan hadis dhoif, seyogyanya kita tetap mengakui bahwa hadis dho’if punya otoritas untuk diamalkan dan mempunyai pijakan hukum asalkan tidak sampai maudhu’ (palsu).
*Santri Tebuireng